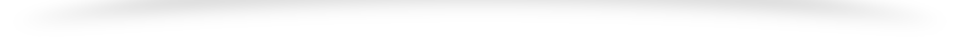Pecihitam.org – Tasawuf, istilah ini tentu tidak asing lagi bagi sebagian umat Islam. Terlebih bagi mereka yang memang berasal dari kalangan orang orang yang amat mendalami ilmu agama terkhususnya pada bidang Tasawuf.
Namun perlu yang diketahui bahwasanya tasawuf sendiri memiliki tingkatan dan definisi yang berbeda beda dari setiap tokoh pengembangnya, dan berikut tingkatan-tingkatan Tasawuf menurut salah satu tokoh yang memang bergelut di bidang ilmu ini.
Dialah Muhammad bin Muhammad Bin Ahmad yang dijuluki sebagai Abu Hamid Al Ghazali, selain itu beliau pun dikenal sebagai Hujjatul Islam.
Setelah imam Al Ghazali jauh berpetualang dengan ilmu ilmu Agama pada akhirnya beliau berada pada jalan tasawuf. Bahkan dalam hal ini, Imam Al Ghazali menciptakan banyak tulisan yang menyangkut dunia tasawuf, beliau menulisnya dengan begitu dalam, meletakkan kaidah kaidahnya serta tak lupalah beliau menjelaskan adab adabnya yang bersifat amaliah dalam bentuk yang terperinci. Berikut penjelasannya:
Jalan (Tarekat)
Dalam langkah awal ini, Al-Ghazali menjadikan kitab Ihya’ Ulumuddin terdiri dari empat bagian utama, yaitu ibadah, adat (kebiasaan), kerusakan-kerusakan, dan keselamatan-keselamatan.
Tentu pada Bagian ibadah mencakup seperti pembicaraan tentang ilmu, kaidah-kaidah dalam tauhid, ibadah, adab dalam membaca al-Qur’an, zikir, doa, dan wirid-wirid.
Kemudian pada bagian adat, al-Ghazali membicarakan mengenai adab-adab sehari-hari sampai kepada adab kenabian. Diantaranya ialah mencakup adab-adab yang berhubungan dengan makan, nikah, bekerja, halal dan haram, kebersamaan, mengasingkan diri, mendengarkan, perasaan, dan amar ma’ruf nahi mungkar (menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran).
Sedangkan bagian tentang kerusakan-kerusakan, di dalamnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa, syahwat-syahwatnya yang terindera, bahaya-bahayanya yang bersifat maknawi semisal marah, dendam, iri, dengki, pelit, pamer, sombong, dan lain sebagainya.
Adapula pada bagian keselamatan-keselamatan Al Ghazali menamakannya dengan istilah Munjiyat. Dimana Al Ghazali memaksudkan nama itu atas segala apa yang dikenal oleh para sufi sebagai magomat dan ahwal. Dan didalamnya mengemukakan tentang taubat, sabar, takut, mengharap, fakir, Zuhud, tauhid, tawakkal, cinta, kerinduan, ridha’ dan lainnya. Serta terdapat pula perihal arti niat, kejujuran, ikhlas, mawas diri, berfikir dan kematian.
Dari keempat bagian utama diataslah dianggap sebagai urutan yang merupakan sebuah keharusan.
Ma’rifah (Pengetahuan)
Dalam hal pengetahuan, Al Ghazali beranggapan bahwa mekanisme pengetahuan para sufi ialah berasal dari hati bukan pada panca Indera atau akal seperti yang diutarakan oleh sebagian umum manusia.
Maka tak heran jikalau Imam Al Ghazali beranggapan bahwa hati bagaikan sebuah kaca. Pengetahuan tak lain adalah terpancarnya hakikat-hakikat dalam cermin tersebut. Di saat kaca hati tersebut tak mengkilap, maka tak mampu memantulkan hakikat-hakikat keilmuan tersebut.
Yang menjadikan kaca hati menjadi buram adalah syahwat badan. “Melakukan ketaatan kepada Allah, memalingkan diri dari tuntutan-tuntutan sahwat, adalah sesuatu yang bisa mengkilapkan hati dan membersihkannya”.
Sedangkan dalam tanggapan lainnya, Al Ghazali mengatakan bahwa pengetahuan terhadap Allah adalah sebuah fitra manusia. Pengetahuan tersebut telah memusat dalam hati.
Fana’ dalam Tauhid atau limit Mukasyafah
Telah diketahui sebelumnya bahwa Fana’ berarti sirna sehingga fana’ dalam Tauhid gambaran Imam Al Ghazali ialah orang yang mengesakan Allah, tak melihat selain kepada-Nya, bahkan tidak melihat dirinya sendiri, namun dalam tinjauan seorang hamba Allah, sehingga inilah yang dikatakan bahwa ia telah sirna (Fana’) dalam keesaan tauhid, dan ia telah sirna dari dirinya sendiri, sehingga dari sinilah muncul sebuah penyataan “Kami dengan diri kami, telah sirna dari diri kami, sehingga kami ada tanpa diri kami”
Al-Ghazali beranggapan bahwa orang yang sampai pada mukasyafah telah masuk di kedalaman hakikat (Ihya’ Ulumuddin, 2, h.256) mengarungi pantai usul dan amal, menyatu dengan kesucian keesaan, mencapai kemurnian keikhlasan, tak ada sesuatu pun yang tersisa di dalamnya, bahkan kemanusiaannya pun telah terbakar, perhatiannya terhadap sifat-sifat manusia telah sirna secara keseluruhan.
Sehingga dari anggapan diatas lagi lagi bukan peleburan/kesirnaan jasadnya, namun fana’ yang dimaksud ialah hatinya. Yang dimaksud dengan hati bukanlah segumpal daging dan darah, namun adalah sebuah ‘inti sari’ yang sangat lembut.
Sedangkan dalam menghadapi permasalahan tauhid. Imam Al Ghazali mengemukakan pemikirannya dengan membagi tauhid menjadi empat tingkatan.
Pertama adalah perkataan manusia “Tidak ada Tuhan selain Allah” dengan lisan, dan hatinya lupa akan arti perkataannya tersebut. Ini adalah tauhid orang-orang munafik.
Kedua adalah membenarkan arti kalimat tersebut sebagaimana umumnya umat Islam membenarkannya. Ini adalah keyakinan masyakarat umum.
Ketiga adalah menyaksikan hal itu dengan jalan kafs, melalui perantara cahaya al-Haq. Ini adalah tingkatan orang-orang yang dekat dengan Allah (al-Muqombin). Sekiranya ia melihat sesuatu yang banyak, namun dengan melihatnya muncul dari zat yang satu.
Sedangkan keempat adalah tak melihat wujud selain satu. Ini adalah persaksiaan (musyahadah) orang-orang yang dapat dipercaya (shadiqin), dan para sufi menamakannya sebagai fana’ dalam tauhid (keesaan).
Dalam permasalahan ini, Al-Ghazali tentunya telah memprediksikan bahwa orang orang bisa saja menentang hal tersebut dengan mengatakan: “Bagaimana mempersepsikan bahwa seorang sufi tak menyaksikan sesuatu selain hanya satu. Padahal jika ia menyaksikan langit, bumi, dan benda-benda yang terindera, maka ia akan menyaksikan sesuatu yang banyak. Bagaimana banyak bisa menjadi satu?.”
Maka dari itu, Al Ghazali memiliki jawaban tersendiri yakni: “Ketahuilah! Bahwa tujuan ini adalah ilmu mukasyafah. Dan rahasia-rahasia ilmu ini, tidak bisa ditulis dalam sebuah buku. Para Arifin telah berkata: “Menyebarluaskan rahasia-rahasia ketuhanan adalah kafir.”
Kemudian hal tersebut berhubungan dengan ilmu muamalah. Sesungguhnya sesuatu terkadang tampak banyak dengan model persaksian dan perenungan tertentu, namun terkadang tampak satu jika dilihat dengan model persaksian dan perenungan lainya.
Maka hal yang wajar jikalau Al-Ghazali beranggapan bahwa ilmu Mukasyafah adalah ilmu yang tertutup. Oleh karenanya orang-orang tersebut menggunakan simbol-simbol tertentu, dan tidak membicarakannya diluar kalangannya sendiri.”
Al-Ghazali berkata: “Ilmu-ilmu semacam itu, tidak boleh diungkapkan, tidak boleh dipublikasikan kepada masyarakat umum, dan orang yang telah mendapatkannya, tidak menampakkannya kepada orang yang tidak mendapatkannya.”
Kebahagiaan
Kebahagiaan dianggap sebagai Tujuan terakhir jalan kesufian bagi Al Ghazali, dan terkait hal ini beliau membicarakan pemikirannya tentang kebahagiaan dalam sebuah buku tersendiri yang berjudul Kimayaus Sya’adah. Sehingga dalam hal ini Al Ghazali berbeda dengan para pendahulunya yang karena membuat teori tentang kebahagiaan secara utuh.
Al-Ghazali beranggapan bahwa jalan menuju kebahagiaan adalah ilmu dan mengamalkannya. Oleh karena itu, ia menyatakan: Saat melihat ilmu, aku melihat sebuah kenikmatan pada dirinya, dicari karenanya, merupakan perantara menuju akhirat dan kebahagiaannya, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tak bisa sampai dihadapan Allah kecuali dengannya. Sesuatu yang paling tinggi tingkatannya yang merupakan hak seorang makhluk adalah kebahagiaan yang abadi.
Sehingga sesuatu yang paling utama adalah perantara untuk sampai kepadanya. Dan tak mungkin mencapainya kecuali dengan ilmu dan amal. Dan tak mungkin sampai pada amal, kecuali dengan ilmu tentang mekanisme melaksanakan amal tersebut. Asal dari sebuah kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah ilmu.
Sumber: Tasawuf Islam (Telaah Historis dan perkembangannya) oleh Abu Wafa’ Al Ghanimi Al Taftazani