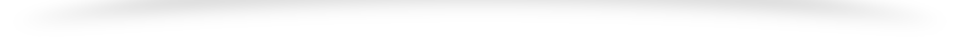Pecihitam.org – Banyak jalan bagi hati seseorang bertaut dengan orang lain. Ada yang “jatuh cinta pada pandangan pertama”, ada yang harus melalui bertahap-tahap kejadian hingga ia mengenal dan mencintai pujaannya, ada pula yang mengenal seseorang dengan terlebih dahulu mengenal seorang yang lain lagi. Dari Cak Nur ke Gus Dur, begitulah pengalaman saya mengenal sang guru bangsa.
Sebetulnya bisa dibilang saya terlambat mengenal dan mempelajari Gus Dur. Seharusnya saya sudah bergelut dengan pemikiran, kiprah dan keteladanan KH. Abdurrahman Wahid sejak 15 tahun yang lalu ketika saya memutuskan untuk berkuliah di Jurusan yang menyediakan alam pikiran orang-orang besar.
Mungkin karena pada masa itu masih terbayang kiprah beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang kebijakannya seringkali kontroversial bagi anak muda awam (sekarang sudah tua) seperti saya, meskipun saya lahir dan tumbuh di kalangan Nahdhiyyin.
Penting kiranya untuk disinggung di sini bahwa kalangan NU Banjar tidak terlalu mengenal Gus Dur. Tokoh yang menjadi panutan dan haluan ke-NU-an mereka adalah KH. Idham Chalid yang berasal dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Kita mengetahui, salah satunya lewat tuturan Greg Barton dalam Biografi Gus Dur (2002), bahwa KH. Idham Chalid dan Gus Dur pernah bersaing sengit dalam perebutan kursi tertinggi NU.
Irisan semacam ini, hemat saya, penting untuk memahami orientasi ideologis yang relatif berbeda antara NU Banjar dan NU Jawa, antara tradisionalisme-konservatif dan tradisionalisme-prograsif, antara kebiasaan mengenakan peci putih dan peci hitam.
Karena itulah, tak heran jika salah seorang senior saya waktu kuliah mengungkapkan kekesalannya karena skripsinya yang mengangkat pemikiran Gus Dur mendapat nilai akhir B, hanya karena ketua tim penguji skripsi tidak suka dengan Gus Dur dan gagasan-gagasannya. Namun justru kejadian itulah yang mulai menarik perhatian saya terhadap sosok Gus Dur.
Meski demikian, hati saya sudah terlebih dahulu tertambat pada Nurcholis Madjid. Sejak duduk di kelas akhir di pesantren saya sudah menaruh perhatian pada ide-ide Cak Nur.
Perhatian itu meningkat menjadi suka ketika masuk kuliah. Saya pun rajin membaca artikel-artikel Cak Nur yang dimuat dalam berbagai buku dan majalah sampai akhirnya saya membeli buku Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan (1987), salah satu karya terbaiknya.
Gagasan Cak Nur yang paling memukau saya adalah yang terkenal dengan jargon “Islam Yes, partai Islam No”. Pada dasarnya ide tersebut, sejauh pemahaman saya, mengandung pesan akan pentingnya memisahkan agama dari institusi agama, agama dari peradaban, agama dari simbol-simbolnya.
Yang satu adalah suatu bangunan spiritualitas yang kerangka-kerangkanya berasal dari Tuhan, sedangkan yang lain adalah bentuk penghayatan spiritualitas tersebut dalam struktur sosial yang dibangun oleh manusia. Bagi seorang pemuda yang sedang bersemangat dan sedang mencari jati diri, ide semacam tentu sungguh memikat.
Pemikiran tersebut bertalian dengan gagasan sekularisasi Cak Nur yang baru saya fahami pada masa-masa akhir kuliah. Penting untuk diketahui bahwa sekularisasi berbeda dengan sekularisme yang Cak Nur sendiri tolak.
Uniknya, ide sekularisasi mengundang penolakan dan kecaman dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan agamawan, mungkin karena ada rentetan huruf “sekular” pada istilah sekulariasi.
Akan tetapi, gagasan tersebut justru terasa semakin urgen untuk dihayati di masa sekarang ini, tatkala banyak terjadi kesilap-pahaman antara agama dengan institusi agama dan simbol-simbolnya dalam pola keberagamaan umat Islam.
Di masanya ide-ide Cak Nur ditolak tapi justru bisa mendapatkan momentum di masa sekarang. Karena itulah, saya melihat sosok Cak Nur seakan-akan seperti manusia masa depan yang naik mesin waktu dan hidup di masa lalu. Ia lebih maju dari masyarakatnya kala itu. Ia memandang ke depan ketika orang-orang masih sibuk mengurusi masa kini mereka.
Di sini saya belajar bahwa suatu gagasan ditolak tidak mesti karena memang salah, tapi karena gagasan itu telalu maju di zamannya. Karena Gus Dur sezaman dengan Cak Nur, yang muncul di pikiran saya adalah: jangan-jangan Gus Dur juga begitu!
Rupanya hal itu benar. Bertahun-tahun sebelum “Islam Nusantara”, Gus Dur sudah menggagas Pribumisasi Islam. Melalui gagasan tersebut Gus Dur mengetengahkan suatu model pemahaman Islam kontekstual, yang dalam bahasa sederhana, pemahaman Islam yang sesuai dengan kondisi, situasi dan budaya di mana Islam dihayati oleh para pemeluknya.
Ide tersebut kemudian berkelindan dengan bentuk pemahaman dan produk syari’at Islam yang kontekstual, sebagaimana diusung oleh Islam Nusantara NU dan Islam Berkemajuan ala Muhammadiyah.
Kita juga tidak bisa melupakan ide-ide Gus Dur tentang pluralisme, kemanusiaan dan keadilan sosial yang sudah lama diusungnya namun baru benar-benar dapat ia terapkan ketika dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia. Ide-ide lama tersebut juga semakin terasa urgensinya ketika politik identitas menghantui keberagamaan dan kebangsaan kita saat ini.
Dengan demikian, bagi saya, gagasan-gagasan Cak Nur dan Gus Dur mesti dipelajari saat ini. Tulisan-tulisan mereka harus dibaca kembali oleh generasi masa sekarang yang ingin mencari landasan-landasan konseptual untuk memandang situasi keberagamaan dan kebangsaan yang ada.
Baik Cak Nur maupun Gus Dur, sama-sama membayangkan paradigma keagamaan yang berdialog dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan keindonesiaan. Perbedaannya terletak pada bagaimana keduanya memperlakukan, meminjam istilah Abid al-Jabiri, “turats”, tradisi yang diwariskan orang-orang terdahulu.
Cak Nur menjadikan tradisi sebagai pijakan ideal karena nilai-nilai kemanusiaan dan kemodernan hadir dalam tradisi namun terlalu maju bagi masyarakat zaman dulu, sedangkan Gus Dur lebih cenderung melakukan peninjauan kembali pemahaman Islam.
Menganalisa pemikiran kedua guru bangsa kita ini, yang sama-sama berasal dari Jombang namun menghasilkan dua corak pemikiran berbeda, nampaknya akan menjelaskan kecenderungan berbeda keagamaan Islam Indonesia, dimana yang satu berbasis perkotaan dan yang lainnya berbasis masyarakat kelas menengah ke bawah dan pedesaan.
Akhirnya, kekaguman saya kepada Cak Nur-lah yang membawa saya kepada Gus Dur. Gus Dur sendiri juga memuji dan mengomentari Cak Nur dalam beberapa kesempatan, misalnya dalam tulisan Gus Dur “Cak Nur Tetap Tapi Berubah” (1982) “Tiga Pendekar dari Chicago” (1993).
Bagi saya, sumbangsih pemikiran kedua guru bangsa itu dapat menjadi pijakan di masa sekarang dan mungkin di masa-masa yang akan datang bagi generasi saat ini. Saya berharap dapat mempelajari lebih jauh lagi gagasan-gagasan Gus Dur supaya saya tidak semakin terlambat.