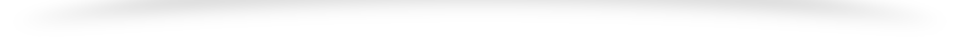Pecihitam.org – Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1 – Kitab Permulaan Wahyu ini, mengemukakan urgensi niat dalam semua perbuatan, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Keterangan hadist dikutip dan diterjemahkan dari Kitab Fathul Bari Jilid 1 Bab Cara Permulaan Turunnya Wahyu Kepada Rasulullah. Halaman 18-29.
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id Al Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”
Keterangan Hadis: عَلَى الْمِنْبَرِ (di atas mimbar), yaitu mimbar masjid Nabawi (Madinah)إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (Tiap-tiap amal perbuatan harus disertai dengan niat). Setiap pekerjaan harus didasari dengan niat.
Al Khauyi mengatakan, seakan-akan Rasulullah memberi pengertian bahwa niat itu bermacam-macam sebagaimana perbuatan. Seperti orang yang melakukan perbuatan dengan motivasi ingin mendapat ridha Allah dan apa yang dijanjikan kepadanya, atau ingin menjauhkan diri dari ancaman-Nya.
Sebagian riwayat menggunakan lafazh anniatu dalam bentuk mufrad (tunggal) dengan alasan, bahwa tempat niat adalah dalam hati, sedangkan hati itu satu, maka kata niyat disebutkan dalam bentuk tunggal. Berbeda dengan perbuatan yang sangat tergantung kepada hal-hal yang bersifat lahiriah yang jumlahnya sangat banyak dan beragam, sehingga dalam hadits tersebut kata ‘amal menggunakan lafazh jama’ (plural) yaitu الْأَعْمَالُ selain itu niat hanya akan kembali kepada Dzat Yang Esa, dan tidak ada sekutu bagi-Nya.
Lafazh hadits yang tertulis dalam kitab Ibnu Hibban adalah الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ dan ini juga terdapat dalam kitab Asy- Syihab karangan Al Qudha’i. Akan tetapi Abu Musa Al Madini dan Imam Nawawi menentang riwayat ini.
Lafazh ” إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ” mengandung arti hashr (pembatasan) menurut para muhaqqiq (peneliti). Setiap perbuatan pasti membutuhkan pelaku, maka kalimat الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ secara lengkap adalah al a’malu shadiratu minal mukallifiina perbuatan yang berasal dari orang-orang mukallaf (orang yang dikenai beban syariat). Dengan demikian apakah perbuatan orang kafir termasuk dalam kategori ini? Jawabnya, tidak termasuk, karena maksud perbuatan dalam hadits ini adalah ibadah, sehingga orang kafir tidak termasuk dalam hadits ini, meskipun mereka diperintahkan untuk melaksanakan dan akan mendapat hukuman apabila meninggalkannya.
بِالنِّيَّاتِ (dengan niat). Huruf ba’ menunjukkan arti mushahabah (menyertai), dan ada juga yang mengartikan sababiyah (menunjukkan sebab). Imam Nawawi mengatakan, bahwa niat berarti maksud, yaitu keinginan yang ada dalam hati. Tetapi Syaikh Al Karmani menambahkan, bahwa keinginan hati adalah melebihi maksud.
Para ahli fikih berselisih pendapat untuk menentukan apakah niat itu termasuk rukun atau syarat? Dalam hal ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan, bahwa mengucapkan niat di awal pekerjaan adalah rukun, sedangkan menyertakannya dalam pekerjaan adalah syarat.
Dalam lafazh hadits tersebut ada kata yang dihilangkan {mahdzuj) sebelum jar majrur (binniyyaat), ada yang mengatakan bahwa lafazh tersebut adalah, tu’tabar (tergantung), takmulu (sempurna), tashihhu (menjadi sah) dan tastaqirru (langgeng).
Ath-Thibi berkata, “Perkataan Allah adalah berfungsi untuk menjelaskan hukum syariat, karena perkataan tersebut ditujukan kepada orang yang mengerti, seakan-akan mereka mendapat perintah apa yang tidak mereka ketahui kecuali dari Allah.”
Baidhawi berkata, “Niat adalah dorongan hati untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan, baik mendatangkan manfaat atau menolak mudharat, sedangkan syariat adalah sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang diridhai Allah dan mengamalkan segala perintah-Nya.”
Niat dalam hadits ini menunjukkan makna etimologi (bahasa), seakan-akan hadits ini mengatakan, “Tidak ada perbuatan kecuali berdasarkan niat.” Tetapi niat bukan inti dari perbuatan tersebut, karena ada beberapa perbuatan yang tidak didasari dengan niat, maka maksud penafian tersebut adalah penafian hukumnya, seperti sah atau kesempurnaan perbuatan.
Guru kami Syaikh Islam berkata, “Yang paling baik adalah menakdirkan bahwa suatu perbuatan tergantung kepada niatnya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits, “Barang siapa melakukan hijrah… ” Dengan demikian lafazh yang dihilangkan menunjukkan isim fa ‘il dan fi ’il. Kemudian lafazh ‘amal (perbuatan) mencakup perkataan (lisan).
Ibnu Daqiq Al ‘Id berkata, “Sebagian ulama mengatakan, bahwa perkataan tidak termasuk dalam perbuatan. Pendapat ini adalah pendapat yang salah, karena bagi saya hadits ini telah memberi penjelasan bahwa perkataan termasuk perbuatan. Karena sikap seseorang yang meninggalkan sesuatu dapat juga dikategorikan dalam perbuatan, meskipun hanya menahan diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan.”
Memang akan terjadi suatu kontradiksi bagi orang yang mengatakan, bahwa perkataan adalah suatu perbuatan, ketika menjumpai orang yang bersumpah untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan, tapi orang itu tetap berbicara. Di sini saya katakan, bahwa masalah sumpah sangat tergantung kepada kebiasaan (‘urf), sedangkan perkataan menurut kebiasaan bukan termasuk perbuatan. Adapun pendapat yang benar, adalah secara hakikat perkataan tidak termasuk dalam perbuatan, akan tetapi secara majaz (kiasan) perkataaan termasuk dalam perbuatan, berdasarkan firman Allah, “Seandainya Allah menginginkan maka mereka tidak akan melakukannya.” dimana ayat tersebut berada setelah ayat zukhrufal qauli (perkataan yang indah), (yaitu sebagian manusia ada yang membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indahindah dengan maksud menipu.)
Ibnu Daqiq Al ‘Id berkata, “Orang yang mensyaratkan niat dalam suatu perbuatan, maka kalimat yang dihapus dalam hadits tersebut diperkirakan adalah kalimat shihhatat a ‘maali (sahnya perbuatan), dan bagi yang tidak mensyaratkan niat, ia memperkirakan kalimat kamaalal a’maali (kesempurnaan perbuatan). Adapun pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama.
Sebagian ulama tidak mensyaratkan niat dalam melakukan suatu perbuatan. Perbedaan tersebut bukan pada tujuannya tapi hanya pada sarana atau wasilahnya saja, maka madzhab Hanafi tidak mensyaratkan niat dalam wudhu, demikian juga Al Auza’i tidak mensyaratkan niat dalam tayammum. Memang diantara ulama terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini, namun inti perbedaan terletak pada apakah niat harus disertakan dalam permulaan suatu perbuatan atau tidak, sebagaimana yang diterangkan dalam pembahasan fikih. ال dalam lafazh النِّيَّاتِ diakhiri dengan dhamir (kata ganti), yaitu al a’malu binniyatiha (amal perbuatan adalah tergantung niatnya).
Dengan demikian, kita dapat membedakan apakah niat shalat atau bukan, shalat fardhu atau sunnah, dhuhur atau ashar, diqashar (diringkas) atau tidak dan seterusnya. Namun demikian, apakah masih diperlukan penegasan jumlah rakaat shalat yang akan dikerjakan? Dalam hal ini memerlukan pembahasan yang panjang. Tapi pendapat yang paling kuat menyatakan tidak perlu lagi menjelaskan jumlah bilangan rakaatnya, seperti seorang musafir yang berniat melakukan shalat qashar, ia tidak perlu menegaskan bahwa jumlah rakaatnya adalah dua, karena hal itu sudah merupakan konsekuensi dari shalat qashar. wallahu a’lam.
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (dan balasan bagi setiap amal manusia sesuai dengan apa yang niatkan). Imam Al Qurthubi berkata, “Kalimat ini menguatkan bahwa suatu perbuatan harus disertai dengan niat dan keikhlasan yang mendalam.” Sedangkan ulama lain berkata, “Kalimat ini membahas permasalahan yang berbeda dengan kalimat pertama ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) karena kalimat pertama menjelaskan bahwa suatu perbuatan harus disertai dengan niat. Adapun kalimat kedua (وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) mempunyai arti bahwa seseorang tidak mendapatkan dari perbuatannya kecuali apa yang diniatkan. Ibnu Daqiq Al ‘Id berkata, “Kalimat kedua memiliki arti bahwa barangsiapa yang berniat, maka akan mendapatkan pahala, baik niat itu dilaksanakan ataupun tidak sebab alasan syariat, dan setiap perbuatan yang tidak diniatkan tidak akan mendapatkan pahala.” Maksud tidak diniatkan di sini adalah tidak ada niat baik secara khusus ataupun umum. Tapi jika seseorang hanya berniat secara umum, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.
Terkadang seseorang mendapat pahala dari perbuatannya tanpa disertai dengan niat sebelumnya, tapi ia mendapat pahala karena melakukan perbuatan yang lain, seperti orang yang melaksanakan shalat ketika masuk masjid, baik shalat fardhu atau sunnah rawatib, maka orang itu mendapat pahala mengerjakan shalat sunnah tahiyatul masjid, baik diniatkan atau tidak, karena yang dilakukannya termasuk dalam kategori penghormatan (tahiyat) terhadap masjid. Berbeda dengan mandi junub pada hari jum’at, ia tidak mendapat pahala mandi sunnah pada hari jum’at menurut pendapat yang kuat (rajih), karena mandi pada hari jum’at merupakan ibadah, bukan hanya membersihkan badan, sehingga memerlukan niat khusus. Permasalahan ini juga berbeda dengan shalat tahiyatul masjid. Wallahu a’lam.
Imam Nawawi berkata, “Kalimat kedua menunjukkan arti bahwa suatu pekerjaan harus disertai niat tertentu, seperti orang yang mengqadha shalat, ia tidak cukup hanya berniat melakukan qadha shalat, akan tetapi harus disertai niat mengqadha shalat yang akan dilaksanakan, apakah shalat ashar atau zhuhur. Ibnu Sam’ani berkata, “Perbuatan di luar ibadah tidak akan mendapatkan pahala kecuali disertai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah (ibadah). Seperti makan, jika diniati untuk menambah kekuatan tubuh agar kuat untuk beribadah, maka ia akan mendapat pahala.
Ibnu Salam berkata, “Kalimat pertama (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) menjelaskan apa yang termasuk dalam kategori perbuatan, sedangkan kalimat kedua (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) menjelaskan tentang akibat dari suatu perbuatan.
Setiap ibadah yang hanya dapat dibedakan dengan niat, maka niat termasuk syarat dalam perbuatan itu, sedangkan perbuatan yang dapat dibedakan dengan sendirinya, maka tidak disyaratkan adanya niat, seperti dzikir, doa dan membaca Al Qur’an, karena perbuatan ini jelas telah membedakan antara ibadah dan kebiasaan sehari-hari (‘adat). Sudah barang tentu semua ini harus dilihat hukum asalnya. Sedangkan apabila seseorang membaca tashbih (subhanallah) ketika takjub, maka ia tidak mendapatkan pahala, kecuali jika membacanya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan mendapat pahala.
Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, “Berdzikir dengan menggerakkan lidah tanpa disertai hati yang khusyu’ tetap akan mendapat pahala, karena berdzikir adalah lebih baik daripada membicarakan orang lain (ghibah), dan lebih baik daripada diam tanpa bertafakkur.” Kemudian dia menambahkan, “Adapun berdzikir dengan lisan saja tidak cukup untuk dikategorikan dalam amalan hati.”
Pendapat tersebut diperkuat dengan hadits Nabi Muhammad SAW, “Setiap sendi kalian adalah shadaqah, ” seorang sahabat bertanya, “Apakah salah satu dari kami yang menyalurkan syahwatnya akan mendapatkan pahala?” Nabi menjawab, “Bagaimana menurut kalian apabila orang itu menyalurkan syahwatnya pada tempat yang haram. “
Imam Ghazali juga mengatakan, bahwa seorang akan mendapatkan pahala dari perbuatan mubah yang dilakukannya, karena perbuatan mubah adalah lebih baik dari perbuatan haram. Secara umum hadits ini menunjukkan tidak diperlukannya niat secara khusus, seperti halnya shalat sunnah tahiyatul masjid, atau suami yang meninggal dan tidak diketahui oleh istrinya, kecuali setelah lewat masa iddah (4 bulan). Maka masa iddah sang istri telah habis dengan sendirinya, karena maksud masa iddah adalah untuk mengetahui bahwa dalam rahim istri tidak ada janin dari suami yang telah meninggal, dan hal itu sudah diketahui oleh sang istri dalam waktu tersebut, dengan demikian tidak wajib bagi sang istri untuk niat iddah lagi.
Imam Al Karmani menentang pendapat Muhyiddin yang mengatakan, bahwa meninggalkan suatu perbuatan tertentu tidak memerlukan niat, karena meninggalkan itu sendiri termasuk perbuatan, yaitu menahan diri untuk tidak melakukannya, sehingga apabila hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dengan menaati perintah syariat, maka harus ada niat untuk meninggalkannya. Sedangkan pernyataan bahwa “altarku fl’lun” (Tidak melakukan sesuatu (meninggalkan) merupakan suatu perbuatan) masih diperselisihkan, sedangkan untuk menjadikan nash sebagai dalil yang diakui, diperlukan adanya kesepakatan yang bebas dari perselisihan. Adapun pengambilan dalil yang kedua tidak sesuai dengan konteks pembahasan, karena masalah yang dibahas adalah apakah meninggalkan suatu perbuatan harus disertai niat, sebagaimana pelakunya akan mendapat dosa jika meninggalkan niat itu? Namun yang diungkapkan Ghazali adalah apakah orang yang meninggalkan niat tetap akan mendapatkan pahala? Dengan demikian perbedaan masalah ini sangat jelas.
Kesimpulannya, bahwa meninggalkan suatu perbuatan yang tidak disertai niat, tidak akan mendapat pahala, akan tetapi yang mendapatkan pahala adalah menahan diri. Karena orang yang tidak terdetik sama sekali dalam hatinya untuk melakukan suatu perbuatan maksiat, tidak sama dengan orang yang terdetik dalam hatinya untuk melakukan perbuatan maksiat, kemudian ia berusaha menahan diri untuk tidak melakukannya karena takut kepada Allah.
Dari uraian di atas kita dapat mengambil intisari, bahwa semua perbuatan membutuhkan niat, dan bukan hanya meninggalkan (tidak melakukan perbuatan tertentu) saja yang perlu niat. Wallahu a ‘lam.
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا (Barangsiapa yang berhijrah untuk mengharapkan dunia). Kalimat seperti ini hampir terdapat dalam semua kitab hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan menghapus sebagian (matan) hadits, yaitu (faman kanaat hijratuhu ilallahi warasuhuilihi) Imam Khaththabi berkata, “Hadits ini terdapat dalam riwayat kami dan kitab hadits para sahabat kami, tetapi baris hadits faman kanaat hijratuhu ilallahi warasuhuilihi) hilang (makhruman) dan tidak tercantum dalam hadits tersebut, saya tidak mengetahui sebab kelalaian ini? Karena Imam Bukhari telah menyebutkan secara lengkap dari jalur selain Humaidi, dan Humaidi juga telah meriwayatkan kepada kami secara lengkap.
Ibnu At-Tin menukil perkataan Khaththabi secara ringkas, dan ia memahami dari perkataan makhruuman (hilang) adalah maqtuu ‘an (terputus) sanadnya, kemudian ibnu At-Tin mengatakan, bahwa hal itu dikarenakan Imam Bukhari tidak pernah bertemu dengan Humaidi, sehingga tampak aneh dari perkataan Bukhari حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ (Humaidi telah menceritakan kepada kami) yang disebutkan berulang kali dalam kitab ini. Tetapi banyak orang yang mengatakan dari biografi Imam Bukhari, bahwa Humaidi adalah salah satu guru Imam Bukhari dalam bidang fikih dan hadits. Ibnu Arabi berkata tentang guru Imam Bukhari, “Tidak ada alasan bagi Bukhari untuk menghilangkan riwayat dari Humaidi, karena Humaidi adalah salah satu guru beliau dalam bidang hadits, dan riwayat ini telah disebutkan dalam kitab musnadnya secara lengkap.” Dia mengatakan, “Beberapa orang mengatakan, “Mungkin saja Imam Bukhari dibacakan atau diriwayatkan beberapa hadits riwayat Humaidi secara lengkap, tetapi sebagian baris hadits hilang dari hafalan Imam Bukhari.” Imam Dawudi berkata, Hilangnya sebagian matan hadits tersebut berasal dari Imam Bukhari, karena riwayat tersebut dapat ditemukan secara lengkap dari para gurunya.”
Kita telah meriwayatkan hadits ini dari jalur Bisyr bin Musa dan Abu Ismail At-Tirmidzi dari Humaidi secara lengkap, seperti dalam Kitab Mushannif karangan Qasim bin Ashbagh, Kitab Mustakhraj karangan Abu Nu’aim, Shahih Abu Awanah dari jalur Humaidi. Jika ditanyakan bahwa hilangnya sebagian baris hadits bukan dari Bukhari, kenapa beliau memulai penulisan kitab ini dengan hadits yang tidak lengkap? Jawabnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Bukhari memilih Humaidi karena beliau adalah gurunya yang terkemuka di kota Makkah. Akan tetapi apabila hilangnya dari Bukhari, maka jawabannya sebagaimana dikatakan oleh Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id Al Hafizh, “bahwa sebaik-baiknya jawaban adalah, dimungkinkan Imam Bukhari memulai penulisan kitab ini dengan mengikuti pengarang-pengarang lain yang memulainya dengan metode penulisan khutbah, yang mencakup maksud dari penulisan kitab ini, seakan-akan beliau memulainya dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Seandainya beliau mempunyai niat mencari dunia atau maksud-maksud yang lain, maka hanya itu yang akan beliau dapatkan.”
Kesimpulannya, bahwa kalimat pertama yang dihilangkan menggambarkan ketulusan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan kalimat yang tidak dihilangkan mencerminkan adanya tarik menarik antara ketulusan niat dan tidak. Maka ketika Imam Bukhari ingin menggambarkan apa yang ada dalam jiwanya dengan menyebutkan hadits ini, beliau menghilangkan makna hadits yang menunjukkan ketulusan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan beliau menulis bagian hadits yang menggambarkan adanya tarik menarik antara ketulusan niat dan tidak. Beliau menyerahkan segalanya kepada Allah untuk memberi balasan niatnya. Disarnping itu sudah menjadi kebiasaan para pengarang kitab untuk mengumpulkan istilah madzhab yang dianutnya dalam isi khutbah kitab, maka imam Bukhari berpendapat, bahwa meringkas sebuah hadits dan meriwayatkan dengan maknanya, mendahulukan yang samar daripada yang jelas, dan menguatkan isnad dengan shighah (bentuk) sama’ (mendengar) daripada yang lainnya adalah diperbolehkan, sebagaimana yang kita lihat dalam periwayatan hadits ini baik dari segi sanad maupun matannya.
Dalam riwayat Hammad bin Zaid pada bab Hijrah kalimat, faman kanats hijratuhu ilallahi warshuluhi diletakkan sesudah kalimat فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا hal itu dimungkinkan, karena riwayat Humaidi sampai kepada Imam Bukhari seperti konteks hadits di atas, yaitu dihilangkan bagian akhirnya, sebagaimana dilakukan oleh orang yang sering meringkas hadits. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa Imam Bukhari membolehkan meringkas hadits secara sembarangan walaupun untuk dirinya sendiri. Inilah pendapat yang paling kuat. Wallahu a lam.
Imam Al Karmani mempunyai pandangan lain dalam hal ini, “Seandainya Bukhari meriwayatkan hadits secara lengkap, kenapa beliau meringkasnya di awal kitab, sedangkan hukum boleh tidaknya meringkas hadits masih diperselisihkan? Tidak mungkin Bukhari menghilangkan sebagian isi hadits, karena konteks pembahasannya berbeda. Mungkin saja ketika menjelaskan “iman itu harus didasari dengan niat dan keyakinan hati” beliau mendengar riwayat hadits ini secara lengkap, sedangkan ketika meriwayatkan “setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya” beliau hanya mendengar seperti yang diriwayatkan di atas. Dengan demikian hilangnya sebagian kalimat hadits berasal dari sebagian guru Imam Bukhari, bukan dari Imam Bukhari. Apabila memang hilangnya dari beliau, maka konteks hadits ini sesuai dengan isi yang dimaksud.
Apabila kamu mengatakan, bahwa kalimat yang dihilangkan sangat sesuai dengan maksud isi hadits tersebut, yaitu bahwa niat harus karena Allah atau Rasul-Nya, maka saya katakan pula, bahwa yang damikian itu adalah pendapat mayoritas kaum muslimin. Pendapat ini dikatakan oleh orang yang tidak melihat dan meneliti perkataan para ulama yang telah saya sebutkan, khususnya Ibnu Arabi.
Imam Al Karmani juga mengatakan, “Hadits ini terkadang diriwayatkan secara lengkap dan terkadang tidak, hal itu disebabkan perawi yang meriwayatkannya juga berbeda. Memang setiap perawi telah meriwayatkan hadits sesuai dengan apa yang dia dengar tanpa ada yang dihilangkan, sedang Bukhari menulis riwayat hadits ini sesuai dengan judul bab yang dibicarakan.”
Seakan-akan Imani Al Karmani menjumpai hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari ini tidak hanya »atu riwayat saja, melainkan terkadang ia mendapatkannya secara lengkap dan terkadang tidak, dan ini dapat dijumpai dalam kitab Jarrn” Ash-Shahih. Karena prinsip Imam Bukhari dalam menulis sebuah hadits adalah tidak menulis satu hadits yang berbeda periwayatannya dalam satu tempat. Apabila ada satu hadits yang mempunyai sanad lebih dari satu, maka ia menulisnya pada tempat yang berbeda dengan sanad yang berbeda pula. dan tidak pernah beliau menulis hadits dengan menghilangkan sebagiannya, sedang pada tempat yang lain beliau menulis secara lengkap, juga tidak dijumpai satu hadits pun dengan sanad dan matan yang sama dan lengkap ditulis pada beberapa tempat, kecuali sebagian kecil saja. Saya menjumpai orang yang selalu meneliti dan mengkaji hadits Bukhari, dimana mereka mendapatkan hal seperti ini kurang lebih dua puluh tempat.
هِجْرَتُهُ (hijrahnya) Hijrah berani meninggalkan, dan hijrah kepada suatu tempat berati pindai i dari satu tempat ke tempat yang lam. Menurut syariat, .hijrah berarti meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam islam hijrah mempunyai dua pengertian. Pertama, pindah dari tempat yang menakutkan ke tempat yang tenang, seperti hijrah ku Negeri Habasyah dan hijrah yang pertama kaii darui Makkah ke Madinah, kedua. Hijrah dari negeri Kafir ke negeri iman, seperti hijrahnya kaum muslimin ke Madinah setelah Rasulullah menetap di sana. Hijrah pada saat itu khusus berpindah ke Madinah, sampai dibukanya kota Makkah (Fathu Mukkah). Setelah itu hijrah tidak dikhususkan lagi, melainkan mempunyai makna umum, yaitu berpindah dari negeri kafir bagi siapa yang memiliki kemampuan.
إِلَى دُنْيَا (mengharapkan dunia)
Lafaz دُنْيَا dibaca dengan dhammah, sedang menurut ibnu qutaibah dibaca kasrah dinyaa kata dunya berasal dari dunuwwu yang berarti dekat, dinamakan demikian karena dunia lebih dahulu daripada akhirat, atau karena dunia sangat dekat dengan kehancuran atau kebinasaan. Namun dalam hal ini ada perbedaan pendapat mengenai hakikat dunia. Sebagian orang mengatakan, bahwa hakikat dunia adalah apa yang ada di atas bumi berupa udara dan angkasa, dan sebagian lain mengatakan, bahwa dunia adalah setiap makhluk yang diciptakan, tapi pendapat yang lebih kuat adalah semua apa yang ada di atas bumi berupa udara dan angkasa sebelum datang hari kiamat. Adapun bila disebutkan salah satu bagian dari dunia tanpa disebutkan secara keseluruhan adalah termasuk bentuk majaz (kiasan).
يُصِيبُهَا (mengharapkan) atau mendapatkannya. امْرَأَةٍ أَوْ ( atau perempuan) Disebutkannya kata perempuan secara khusus setelah kata umum (dunia) adalah untuk menekankan bahwa bahaya dan fitnah yang ditimbulkan oleh perempuan sangat besar. Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa sebab munculnya hadits ini adalah cerita seorang muslim yang ikut berhijrah dengan maksud ingin mengawini seorang perempuan sehingga ia disebut Muhajir Ummu Qais. Ibnu Dihyah meriwayatkan, bahwa nama perempuan itu adalah Qailah.
Ibnu Baththal meriwayatkan dari Ibnu Siraj tentang manfaat disebutkannya kata mar ‘ah (perempuan) secara khusus dalam hadits ini. Hal itu disebabkan kebiasaan orang Arab yang tidak mau mengawinkan anak perempuan mereka dengan hamba sahaya, karena mereka sangat menjaga kehormatan keturunannya. Ketika Islam datang membawa ajaran yang tidak membedakan kedudukan kaum muslimin dalam masalah pernikahan, maka banyak bangsa Arab yang pergi ke Madinah untuk menikahi perempuan tersebut, dimana sebelum itu mereka tidak dapat melakukannya. Tetapi dalam hal ini masih dibutuhkan riwayat yang kuat untuk menyatakan bahwa orang laki-laki yang ikut berhijrah itu adalah seorang hamba sahaya sedangkan perempuan tersebut adalah orang Arab yang terhormat. Karena banyak orang Arab sebelum datangnya Islam telah mengawinkan anak perempuannya dengan hamba sahaya, maka kedatangan Islam di sini telah menghapus kesetaraan yang tidak pada tempatnya.
فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan).
Fungsi kata ganti (dhamir) dalam kalimat فَهِجْرَتُهُ adalah untuk mencakup semuanya, baik perempuan atau lainnya, adapun kata ganti (dhamir) pada kalimat yang dihilangkan sebelumnya faman kaanats hijratuhu ilallahi warashulihi fahijratuhu ilallahi warshulihi adalah untuk mengingat kebesaran Allah dan Rasul-Nya, berbeda dengan perkataan dunya (dunia) dan mar ‘ah (wanita), karena konteksnya adalah untuk menghimbau agar manusia selalu berhati-hati dan menjauhinya.
Imam Al Karmani berkata, “Kalimat إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ berhubungan dengan dengan lafazh al hijrah, maka khabar (predikat) nya dihilangkan dan ditaqdirkan dengan kalimat gabihah (buruk) atau ghairu shahihah (tidak benar), atau dimungkinkan yang menjadi predikat adalah lafazh فَهِجْرَتُهُ dan kalimat إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ adalah sebagai predikat dari (mubtada) subyek kalimat مَنْ كَانَتْ Pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling kuat, karena pendapat yang pertama menunjukkan bahwa setiap hijrah itu secara mutlak adalah tercela, padahal tidak demikian. Kecuali terjadi penduaan dalam niat seperti seseorang yang niat hijrah untuk menjauhi kekufuran dan mengawini seorang wanita, maka hal ini bukan sesuatu yang tercela dan tidak sah, akan tetapi hijrah seperti ini kurang sempurna dibandingkan dengan orang yang berhijrah dengan niat yang tulus.
Seseorang yang berhijrah disertai dengan niat untuk menikahi seorang perempuan, maka ia tidak akan mendapatkan pahala seperti orang yang hanya berniat hijrah, atau seorang yang mempunyai keinginan menikah saja tanpa melakukan hijrah kepada Allah, maka orang itu tetap mendapatkan pahala apabila pernikahan yang dilakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wata ‘ala, karena pernikahan adalah anjuran agama Islam.
Hal ini seperti peristiwa masuk Islamnya shahabat Thalhah, sebagaimana diriwayatkan oleh Nasa’i dan Anas, ia berkata, “Abu Thalhah telah menikahi Ummu Sulaim dengan mahar masuk Islam, karena Ummu Sulaim telah masuk Islam lebih dahulu dari pada Abu Thalhah. Maka ketika Abu Thalhah melamarnya, Ummu Sulaim berkata, “Aku sudah masuk Islam, seandainya kamu masuk Islam, maka saya bersedia dikawini.” Lalu Abu Thalhah masuk islam dan menikahi ummu Sulaim. Hal ini dilakukan atas dasar keinginannya untuk masuk Islam dan menikahi ummu Sulaim, seperti juga orang yang melakukan puasa dengan niat ibadah dan menjaga kesehatan.
Imam Ghazali menggaris bawahi apabila keinginan untuk memperoleh dunia lebih besar dari keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka orang itu tidak mendapatkan pahala, begitu pula apabila terjadi keseimbangan antara keduanya antara keinginan untuk mendapatkan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah, ia tetap tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi apabila seseorang berniat untuk ibadah dan mencampurnya dengan keinginan selain ibadah yang dapat mengurangi keikhlasan, maka Abu Ja’far bin Jarir Ath-Thabari telah menukil perkataan ulama salaf, bahwa yang harus menjadi tolak ukur adalah niat awal, apabila ia memulai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka perubahan niat tidak menggugurkan pahalanya. Wallahu a’lam.
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 663-664 – Kitab Adzan - 30/08/2020
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 662 – Kitab Adzan - 30/08/2020
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 661 – Kitab Adzan - 30/08/2020