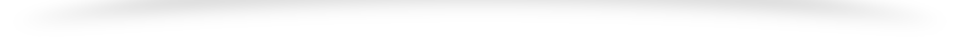Pecihitam.org – Hadits Shahih Al-Bukhari No. 167 – Kitab Wudhu ini, Dalam naskah Imam Bukhari yang dinukil dari lbnu Asakir, sebelum menyebutkan hadits berikut, tercantum satu bab dengan judul “Apabila anjing minum dalam bejana”. Hadis ini menjelaskan tentang perintah untuk membersihkan bejana yang telah dijilat anjing. Keterangan hadist dikutip dan diterjemahkan dari Kitab Fathul Bari Jilid 2 Kitab Wudhu. Halaman 128-143.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا
Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami [‘Abdullah bin Yusuf] dari [Malik] dari [Abu Az Zinad] dari [Al A’raj] dari [Abu Hurairah] berkata, “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika anjing menjilat bejana seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga tujuh kali.”
Keterangan Hadis: إِذَا شَرِبَ (apabila anjing minum) demikian yang terdapat dalam kitab Al Muwaththa’, sementara yang masyhur dari Abu Hurairah melalui riwayat mayoritas perawi adalah dengan lafazh إِذَا وَلَغَ (Apabila anjing menjilat). Inilah lafazh yang masyhur dari segi bahasa.
Apabila dikatakan وَلَغَ يَلَغ berarti anjing minum air dengan ujung lidahnya, atau memasukkan lidahnya ke dalam air dan menggerakgerakkannya. Tsa’lab berkata, “Makna kata وَلَغَ adalah memasukkan lidah ke dalam air ataupun zat cair lainnya, lalu lidah tersebut digerakgerakkan.” lbnu Darastawaih menambahkan, “Baik ia minum atau tidak.” lbnu Makki berkata, “Jika menjilat pada selain zat cair, maka dinamakan لَعِقَ Kemudian Al Mathrazi mengatakan, bahwa jika jilatan itu dilakukan pada wadah yang kosong maka dinamakan لَحِسَ
lbnu Abdul Barr mengklaim bahwa lafazh شَرِبَ (meminum) tidak diriwayatkan selain Malik, dan perawi-perawi lain menukil hadits ini dengan lafazh وَلَغَ (Menjilat). Akan tetapi kenyataan tidaklah seperti yang beliau katakan, sebab telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lbnu Mundzir melalui dua jalur periwayatan dari Hisyam bin Hisan dari lbnu Sirin dari Abu Hurairah, dengan lafazh, إِذَا شَرِبَ (Apabila anjing minum). Akan tetapi yang masyhur dinukil dari Hisyam bin Hisan adalah dengan lafazh, إِذَا وَلَغَ (Apabila anjing menjilat) sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya melalui berbagai jalur periwayatan dari beliau (Hisyam).
Telah diriwayatkan oleh Abu Zinad (salah seorang guru Imam Malik) dengan lafazh, إِذَا شَرِبَ (Apabila anjing minum), demikian pula Warga’ bin Umar sebagaimana yang dikutip oleh Al Jawazqi. Begitu juga yang diriwayatkan melalui Al Mughirah bin Abdurrahman, seperti dikutip oleh Abu Ya’la.
Perlu diketahui, bahwa Imam Malik meriwayatkandengan lafazh, إِذَا وَلَغَ (Apabila anjing menjilat) sebagaimana yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitab beliau yang berjudul Ath-Thaharah melalui jalur periwayatan Isma’il bin Umar, dan dari jalur ini pula hadits ini dinukil oleh Al Isma’ili.
Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam kitabnya Al Mirwatha ‘at melalui jalur periwayatan Abu Ali Al Hanafi dari Malik, terdapat dalam Naskah Sunan Jbnu Majah yang otentik (shahih) melalui riwayat Ruh bin Ubadah dari Malik. Dari sini diketahui bahwa seakan-akan Abu Zinad meriwayatkan dengan dua lafazh tersebut, karena makna keduanya sangatlah mirip. Hanya saja شَرِبَ (meminum) memiliki makna yang lebih khusus daripada وَلَغَ (menjilat), oleh sebab itu kata “meminum” tidak dapat menggantikan fungsi kata “menjilat.”
Makna implisit (tersirat) dari kata وَلَغَ memberi indikasi, bahwa hukum ini hanya terbatas apabila anjing itu memasukkan lidahnya ke dalam bejana berisi air dan menggerak-gerakkannya. Namun apabila dikatakan bahwa perintah untuk mencuci bejana tersebut karena tereemari najis, maka tentu hukum pun berlaku apabila anjing menjilat tempat kering لَعِقَ maupun menjilat bejana dalam keadaan kosong لَحِسَ Sehingga, penggunaan kata وَلَغَ hanyalah karena lafazh ini merupakan fenomena yang umum.
Adapun mengenai masalah apakah bagian badan anjing yang lainnya memiliki hukum yang sama dengan mulutnya? Menurut pendapat yang tertera dalam teks madzhab menyatakan, bahwa hukumnya adalah sama. Alasannya karena mulut adalah sesuatu yang paling mulia pada dirinya, maka tentu bagian-bagian badannya selain mulut kedudukannya di bawah derajat mulut.
Namun dalam madzhab Imam Syafi’i yang lama disebutkan, bahwa hukum seperti itu hanya berlaku bagi mulut anjing dan tidak mencakup bagian-bagian badannya yang lain. Maka sehubungan dengan itu Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Ar-Raudhah, “Ini adalah pandangan yang ganjil (syadz).”
Sementara dalam Syarh Al Muhadzab dikatakan, “Pandangan tersebut sangat kuat dari segi dalil. Sementara alasan yang dikemukakan bahwa mulut merupakan bagian paling mulia pada anjing tidak dapat diterapkan sepenuhnya, sebab mulut ini kadang dipergunakan untuk memakan najis.”
فِي إِنَاء أَحَدكُمْ (Di bejana salah seorang di antara kamu) Secara lahiriah hal ini berlaku umum pada semua bejana, dan secara implisit ia tidak mencakup air yang tergenang. Kesimpulan ini berlaku mutlak (tanpa batasan) menurut Al Auza’i.
Namun sekali lagi jika dikatakan bahwa perintah untuk mencuci bejana disebabkan tercemar najis, maka hukum tersebut berlaku pada air yang sedikit dan tidak mencakup air yang banyak. Sedangkan penyandaran bejana itu kepada seseorang tidak berpengaruh dalam menetapkan hukum, sebab hukum itu tetap berlaku meski bejana itu tidak ada pemiliknya. Demikian pula sabda beliau, “Hendaklah ia mencucinya”, tidak berarti bahwa yang mesti mencuci adalah pemilik bejana itu sendiri.
Kemudian ditambahkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa’i dari jalur periwayatan Ali bin Mushir dari Al A’masy dari Abu Shalih dan Abu Razin, dari Abu Hurairah sehubungan dengan hadits ini, “Hendaklah ia menumpahkan air tersebut”. Ini memperkuat pendapat bahwa perintah untuk mencuci adalah karena bejana tersebut telah tercemar oleh najis, dimana sesuatu yang ditumpahkan bisa saja berupa makanan ataupun minuman. Maka seandainya bekas jilatan anjing itu suci, tentu tidak diperintahkan untuk ditumpahkan karena adanya larangan untuk tidak menyia-nyiakan harta.
Hanya saja Imam An-Nasa’i berkata, “Aku tidak tahu ada perawi lain yang menukil lafazh ‘Hendaklah ia tumpahkan’ kecuali Ali bin Mushir.” Lalu Hamzah Al Kannani berkata, “Sesungguhnya riwayat Ali ini menyelisihi riwayat orang-orang yang lebih tsiqah (terpercaya) darinya.” Ibnu Abdul Barr menambahkan, “Para perawi terkemuka d1 antara murid-murid A’rnasy seperti Mu’awiyah dan Syu’bah tidak pernah menukil lafazh seperti itu.” Demikian pula lbnu Mandah berkata, “Lafazh seperti itu tidak dikenal diriwayatkan dari Nabi SAW kecuali melalui jalur periwayatan Ali bin Mushir.”
Aku Katakan, “Perintah untuk menumpahkan sisa jilatan anjing telah dinukil pula melalui riwayat Atho’ dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, seperti dikutip oleh Ibnu Adji. Akan tetapi penisbatan riwayat tersebut langsung kepada Nabi masih perlu dianalisa lebih lanjut, bahkan yang benar silsilah periwayatannya hanya sampai kepada Abu Hurairah. Demikian pula perintah untuk menumpahkan sisa jilatan anjing telah disebutkan oleh Hammad bin Zaid dari Ayyub dari lbnu Sirin dari Abu Hurairah, dimana silsilah periwayatannya menduduki derajat shahih. Riwayat ini disebutkan oleh Ad-Daruquthni serta para pakar hadits lainnya.”
فَلْيَغْسِلْهُ (Hendaklah ia mencucinya) perintah ini berindikasi untuk dilaksanakan seecpatnya, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa hal itu hanyalah berstatus disukai (mustahab).
سَبْعًا (Tujuh kali). Dalam riwayat Imam Malik tidak disebutkan masalah mencampur air dengan tanah pada salah satu di antara ketujuh pencucian tersebut. Masalah ini juga tidak diriwayatkan oleh para perawi yang menerima hadits ini dari Abu Hurairah kecuali riwayat yang dinukil melalui jalur lbnu Sirin, bahkan sebagian perawi yang menerima hadits ini dari be Jiau juga tidak mencantumkan masalah yang dimaksud.
Selanjutnya para perawi yang menerima hadits tersebut dari lbnu Sirin berbeda dalam menentukan manakah di antara ketujuh pencucian itu yang dicampur dengan tanah. Imam Muslim dan selain beliau meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Hisan dari Ibnu Sirin bahwa pada pencucian pertamalah yang dicampur dengan tanah. Inilah versi yang paling banyak dinukil oleh para perawi dari Ibnu Sirin, yang juga dinukil oleh Abu Rafi’.
Kemudian terjadi kontroversi di antara para perawi yang menerima hadits tersebut melalui jalur Qatadah dari lbnu Sirin. Sa’id bin Basyir menyebutkan dalam riwayatnya dari Qatadah dari Ibnu Sirin, bahwa pencucian yang dicampur dengan tanah adalah pada kali yang pertama, sebagaimana dikutip oleh Ad-Daruquthni. Sementara Abban menyebutkan dalam riwayatnya dari Qatadah dari Ibnu Sirin bahwa yang dicampur dengan tanah adalah yang ketujuh, seperti dinukil oleh Abu Dawud.
Sedangkan Imam Syafi’i menyebutkan dalam riwayatnya dari Sufyan dari Ayyub dari Ibnu Sirin dengan lafazh, “Pada kali yang pertama atau pada salah satu di antara (ketujuh) pencucian tersebut.” Namun dalam riwayat As-Sudi dari Al Bazzar hanya mencantumkan lafazh, “pada salah satu di antara (ketujuh) pencucian tersebut”, sebagaimana lafazh ini juga disebutkan oleh Hisyam bin Urwah dari Abu Zinad dari Ibnu Sirin.
Adapun cara yang ditempuh untuk mengkompromikan riwayatriwayat yang saling kontroversi tersebut adalah dengan mengatakan, “Riwayat dengan lafazh, ‘Salah satu di antara (ketujuh) pencucian tersebut’ belum memberi penjelasan rinci. Sementara riwayat dengan lafazh ‘Pada kali yang pertama” dan “Pada kali yang ketujuh” sama-sama memberi keterangan secara rinci.
Adapun riwayat dengan lafazh, “Pada kali yang pertama atau pada salah satu di antara (ketujuh) pencucian tersebut’ jika kata ‘atau’ pada riwayat ini memberi makna pilihan, yakni boleh memilih salah satu di antaranya, maka lafazh ini harus dikembalikan kepada salah satu di antara dua riwayat yang ada (yakni riwayat yang menyatakan pada kali yang pertama dan riwayat yang menyatakan pada kali yang ketujuh) berdasarkan kaidah ‘lafazh mutlaq (tanpa menyebutkan batasan) harus dikembalikan kepada lafazh muqayyad (yang menyebutkan batasan tertentu).”
Demikianlah yang dicantumkan oleh Imam Syafi’i secara tekstual dalam kitabnya Al Umm, dan ini pula pendapat yang dinyatakan secara tegas oleh Al Mur’isyi serta selain beliau di antara ulama madzhab Syafi’i. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al ‘Id dan As-Subki dalam pembahasan tersendiri. Sedangkan jika kata “atau” pada riwayat di atas hanya timbul dari keraguan perawi, maka riwayat mereka yang menyebutkan tanpa ragu-ragu lebih pantas untuk diterima.
Dengan demikian langkah selanjutnya adalah menentukan manakah yang lebih akurat di antara dua riwayat yang ada, apakah riwayat dengan lafazh “pada kali pertama” ataukah riwayat dengan lafazh “pada kali ketujuh?” Apabila dicermati dengan teliti dapat disimpulkan bahwa riwayat dengan lafazh “Pada kali yang pertama” jauh lebih akurat ditinjau dari segi jumlah periwayat, ketelitian maupun logika. Sebab bila pencucian yang terakhir dicampur dengan tanah, maka seseorang butuh kepada pencucian yang lain untuk membersihkan bejana yang ia cuci. Imam Syafi’i telah menyebutkan secara tekstual dalam kitab Harmalah bahwa riwayat pertama lebih tepat, wallahu A ‘lam.
Hadits ini memberi keterangan tentang beberapa persoalan, di antaranya najis ditinjau dari segi hukum dapat menyebar ke tempat sekitarnya dengan syarat tempat tersebut berupa zat cair. Zat cair dapat berubah menjadi najis bila pada salah satu bagiannya terkena najis, dan bejana yang berisi air seperti itu dihukumi tercemar najis. Air yang sedikit dapat berubah menjadi najis bila kejatuhan najis meskipun tidak berubah salah satu sifatnya, sebab jilatan anjing umumnya tidak dapat merubah sifat-sifat dasar air. Adanya perbedaan hukum air yang kejatuhannya dan air yang ditumpahkan ke dalam najis, karena Rasulullah memerintahkan untuk menumpahkan air yang kejatuhan najis, dan hakekat perintah ini adalah untuk menumpahkan air seluruhnya. Setelah itu diperintahkan pula agar bejana tersebut dicuci, dan tentu saja hakikat perintah ini mengacu pada suatu perbuatan yang dapat dinamakan mencuci, meskipun air yang dipakai mencuci tersebut lebih sedikit daripada yang dibuang.
Pelajaran yang dapat diambil
Ulama madzhab Maliki dan Hanafi memilih pendapat yang berbeda dengan makna zhahir hadits tersebut. Ulama Maliki mengatakan bahwa tidak ada di antara ketujuh pencucian yang dicampur dengan tanah, meskipun menurut riwayat yang masyhur dari mereka mengatakan wajib untuk mencuci bejana yang berisi air bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali. Hal ini karena keterangan untuk mencampur salah satu pencucian tersebut dengan tanah tidak dinukil dalam riwayat Imam Malik.
Al Qarafi (salah seorang ulama madzhab Maliki) berkata, “Terdapat sejumlah hadits Shahih mengenai hal itu, maka sangat mengherankan mengapa mereka tidak berpendapat sebagaimana kandungan hadits-hadits tersebut.”
Lalu diriwayatkan pula pendapat dari Imam Malik yang menyatakan bahwa mencuci bejana sebanyak 7 kali adalah sunah hukumnya. Akan tetapi pendapat yang terkenal di kalangan sahabatnya menyatakan bahwa perintah untuk mencuci sebanyak 7 kali hukumnya wajib, namun tujuannya hanyalah bersifat ibadah semata bukan karena bejana tersebut tercemar najis. Sebab, menurut pandangan mereka anjing adalah suci.
Kemudian ulama-ulama generasi berikutnya dalam madzhab Maliki menyebutkan hikmah yang terkandung dalam perintah untuk mencuci bejana tersebut, bukan karena bejana itu tercemar najis, seperti akan kami terangkan pada pembahasan selanjutnya.
Ada satu riwayat dari Imam Malik yang mengatakan bahwa bejana tersebut hukumnya tercemar najis, namun kaidah dasar beliau mengatakan, “Air tidak berubah menjadi najis kecuali bila berubah salah satu sifatnya.” Oleh sebab itu kewajiban mencuci bejana berisi air bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali bukan karena bejana itu tercemar najis, melainkan demi tujuan ibadah semata. Akan tetapi pendapat ini tidak sejalan dengan sabda Nabi di bagian awal hadits dalam masalah ini, yakni riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim serta ahli hadits lainnya dari Muhammad bin Sirin dan Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah, dimana dikatakan, “Sucinya bejana salah seorang di antara kamu apabila dijilat anjing adalah dengan dicuci sebanyak tujuh kali.”
Letak kontradiksi antara hadits ini dengan pendapat Imam Malik adalah pada kata, “Sucinya”. Hal itu karena kata “suci “biasanya hanya dipergunakan untuk menyatakan sesuatu apabila bersih dari hadats (junub) ataupun najis, sementara mengenai perintah untuk mencuci bejana yang berisi air bekas jilatan anjing tentu bukan untuk membersihkan hadats. Dengan demikian, dapat dipastikan tujuan mencuci di sini adalah untuk menghilangkan najis.
Namun argumentasi ini dapat pula dijawab dengan mengatakan bahwa kata “suci ” penggunaannya tidak hanya terbatas pada bersihnya sesuatu dari hadats (junub) ataupun najis. Sebab telah diketahui bahwa tayammum tidak dapat menghilangkan hadats (junub ), namun N abi SAW menamakannya sebagai perkara yang mensucikan seorang muslim. Di samping itu, kesucian juga dipergunakan pada selain makna di atas, seperti firman Allah, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (Qs. AtTaubah(9): 103) Demikian pula dengan sabda Nabi, “Siwak (menggosok gigi) merupakan kesucian bagi mulut.”
Adapun jawaban untuk bantahan pertama dikatakan, “Sesungguhnya tayammum dilaksanakan karena hadats (junub ). Oleh karena tayammum itu menggantikan fungsi sesuatu yang dapat mensucikan hadats, maka ia pun dinamakan sebagai sesuatu yang mensucikan.” Namun bagi mereka yang berpandangan bahwa tayammum dapat pula menghilangkan hadats (junub ), maka kritik yang dikemukakan tidak mempunyai landasan yang kuat.”
Sedangkan jawaban untuk bantahan kedua dikatakan, “Sesungguhnya lafazh-lafazh yang telah menjadi istilah syariat jika indikasi maknanya menunjukkan pengertiannya secara bahasa dan sekaligus menunjukkan pengertiannya secara syariat, maka lafazh seperti ini mesti diartikan sebagaimana pengertiannya syariat, kecuali bila ada keterangan yang menunjukkan makna yang lain.
Adapun klaim sebagian ulama madzhab Maliki bahwa perintah untuk mencuci tersebut hanya berlaku bagi anjing yang dilarang untuk dipelihara, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa larangan untuk memelihara anjing lebih dahulu ditetapkan daripada perintah untuk mencuci bejana yang berisi air bekas jilatan anjing. Di samping itu, perlu pula faktor penjelas yang menyatakan bahwa perintah tersebut hanya berlaku bagi jilatan anjing yang dilarang untuk dipelihara, sebab kata anjing pada dasamya mencakup semua jenis anjing (baik yang boleh dipelihara maupun yang dilarang). Oleh sebab itu, klaim seperti di atas perlu pembuktian.”
Sama seperti itu, pemyataan mereka yang membedakan antara anjing dari dusun dan anjing perkotaan. Demikian pula dengan klaim mereka bahwa anjing yang dimaksud adalah anjing gila, dan sesungguhnya hikmah perintah mencuci bejana tersebut karena atas pertimbangan medis. Hal ini karena syariat telah memberi perhatian tersendiri terhadap angka tujuh ini sehubungan dengan masalah-masalah medis, seperti sabda beliau, “Siramilah aku sebanyak tujuh timba”, dan sabdanya, “Barangsiapa di pagi hari makan tujuh biji kurma ajwah … “
Kemudian argumentasi ini dibantah dengan mengatakan bahwa anjing gila sama sekali tidak mau mendekati air, lalu bagaimana mungkin diperintahkan mencuci bejana berisi air bekas jilatannya? Selanjutnya pertanyaan ini dijawab oleh Hafizh Ibnu Rusyd, “Anjing gila tidak mendekati air pada saat penyakitnya parah, namun pada awal penyakit itu menjalar ia tetapi minum air.”
Alasan yang dikemukakan oleh ulama madzhab Maliki meskipun memiliki kesesuaian dengan perintah yang ada, namun pengkhususan ini tidak berdasarkan dalil. Adapun alasan perintah mencuci bejana tersebut disebabkan tereemar najis jauh lebih kuat, karena makna tersebut tertera dalam hadits secara tekstual. Sementara telah dinukil riwayat yang akurat dari lbnu Abbas, bahwa sebab perintah mencuci bejana tersebut adalah karena tercemar najis. Riwayat ini dinukil oleh Muhammad bin Al Marwazi melalui silsilah periwayatan yang shahih dan tidak ada satupun riwayat dari para sahabat lain yang menyelisihinya.
Di antara pendapat madzhab Maliki yang masyhur adalah membedakan hukum antara bejana berisi air dengan bejana berisi makanan jika dijilat anjing. Bila bejana tersebut berisi air, maka airnya ditumpahkan. Sedangkan bila berisi makanan, maka makanan itu dimakan lalu bejananya dicuci sebagai wujud ibadah. Alasan mereka bahwasa perintah untuk membuang isi bejana yang dijilat anjing masih bersifat umum, maka ada pengecualian dalam hal ini makanan disebabkan ada larangan menyia-nyiakan harta.
Namun dikatakan kepada mereka, “Justeru larangan menyianyiakan harta telah dibatasi dengan perintah menumpahkan air bekas jilatan anjing. Pandangan ini diperkuat adanya kesepakatan ulama yang mengharuskan membuang zat cair -dalam ukuran yang sedikit- apabila dijilat anjing, meskipun harganya mahal. Dari sini terbukti bahwa larangan menyia-nyiakan harta telah dibatasi oleh perintah untuk menumpahkan air bekas jilatan anjing.”
Setelah jelas bahwa air sisa jilatan anjing hukumnya najis, maka ada kemungkinan hal itu disebabkan air liur anjing itu sendiri adalah najis. Ada pula kemungkinan bahwa air liur anjing pada dasarnya adalah suci, namun ia menjadi najis karena faktor-faktor dari luar, seperti karena kebiasaan anjing memakan bangkai. Akan tetapi kemungkinan pertama lebih beralasan, sebab inilah yang menjadi dasar. Di samping itu jika dikatakan najisnya air bekas jilatan itu karena kemungkinan kedua, maka konsekuensinya hukum ini berlaku pula pada binatang yang lain, misalnya kucing.
Setelah jelas bahwa yang menyebabkan najisnya air sisa jilatan anjing adalah karena memang air liumya adalah najis, maka hal itu tidak langsung menjadi alasan untuk menetapkan najisnya bagian-bagian anjing yang lain, kecuali bila ditetapkan melalui qiyas (analogi). Seperti dikatakan, “Apabila air liur anjing adalah najis, maka mulutnya juga najis. Sebab air liur diproses melalui mulut dan air liur berkedudukan sebagai keringat mulutnya, sementara mulut adalah bagian terrnulia darinya, maka dengan demikian keringat badannya juga najis. Lalu apabila keringat badannya najis, maka seluruh badannya termasuk najis pula sebab keringat diproses dari badan. Hanya saja apakah bagianbagian badan anjing yang Iain disamakan dengan air Iiumya, dalam artian bekasnya mesti dicuci pula sebanyak tujuh kali dimana salah satunya dicampur dengan tanah ataukah tidak demikian? Isyarat mengenai hal ini telah disebutkan dalam perkataan Imam An-Nawawi pada pembahasan terdahulu.
Di Iain pihak, uiama madzhab Hanafi disamping tidak mewajibkan mencampur salah satu air cucian dengan tanah, mereka tidak pula mewajibkan untuk mencuci sebanyak tujuh kali.
Lalu Imam Ath-Thahawi serta ulama-ulama yang lain mengemukakan sejumlah alasan untuk memperkuat pendapat tersebut, di antaranya karena Abu Hurairah sebagai perawi hadits dalam masalah ini justeru berfatwa untuk mencuci bejana bekas jilatan anjing sebanyak tiga kali. Hal ini menurut mereka sebagai bukti bahwa kewajiban mencuci sebanyak tujuh kali telah dihapus (mansukh).
Lalu alasan itu dibantah dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan Abu Hurairah berpandangan mencuci tujuh kali hukumnya hanyalah sunah bukan wajib, atau ada pula kemungkinan beliau lupa akan apa yang diriwayatkannya.
Dengan adanya kemungkinan seperti ini, penghapusan hukum tersebut tidak dapat dipastikan. Di samping itu, telah diriwayatkan pula bahwa Abu Hurairah pemah berfatwa untuk mencuci bejana bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali. Sementara riwayat tentang fatwa beliau yang sesuai dengan apa yang ia riwayatkan jauh Jebih akurat di banding riwayat tentang fatwa beliau yang menyelisihi apa yang ia riwayatkan, baik ditinjau dari segi silsilah periwayatan maupun dari sisi logika.
Adapun dari sisi Jogika nampak jelas, sedangkan dari segi silsilah periwayatan sesungguhnya riwayat tentang fatwa beliau yang sesuai dengan apa yang ia riwayatkan telah dinukil dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, yang mana ini adalah sanad paling shahih. Sedangkan riwayat tentang fatwa beliau yang menyelisihi apa yang ia riwayatkan telah dinukil dari jalur Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atha’ dari Abu Hurairah, dimana silsilah periwayatannya jauh di bawah derajat silsilah periwayatan yang pertama.
Alasan lain yang mereka kemukakan adalah, sesungguhnya tingkat kenajisan kotoran (tahi) jauh lebih berat daripada air sisa jilatan anjing, namun untuk membersihkan kotoran tersebut tidak disyaratkan untuk dicuci sebanyak tujuh kali. Dari sini maka tentu mencuci bejana bekas jilatan anjing lebih pantas lagi untuk tidak dibatasi dengan jumlah tertentu.
Jawaban untuk argumentasi ini saya (Ibnu Hajar) katakan, “Tidak ada kemestian bahwa sesuatu yang lebih tinggi tingkat kenajisannya akan lebih berat pula dalam tinjauan hukumnya. Di samping itu perkataan tersebut merupakan analogi yang menyalahi nash (teks hadits), maka dianggap rusak.”
Mereka mengklaim pula bahwa perintah untuk mencuci bejana bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali ditetapkan pada saat diperintahkan untuk membunuh anjing. Maka ketika dilarang untuk membunuh anjing, perintah untuk mencuci bejana sebanyak tujuh kali ikut terhapus. Klaim ini dibantah berdasarkan bukti bahwa perintah untuk membunuh anjing dikeluarkan pada permulaan hijrah, sedangkan mencuci bejana bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali diperintahkan pada masa akhir kehidupan Rasulullah. Sebab, hadits ini adalah riwayat Abu Hurairah dan Abdullah bin Mughaffal.
Sementara telah disebutkan oleh Abdullah bin Mughaffal, bahwa beliau mendengar Nabi memerintahkan mencuci bejana di saat ia masuk Islam. Padahal beliau masuk Islam pada tahun ketujuh hijrah, sama seperti Abu Hurairah. Bahkan, konteks riwayat Imam muslim sangat jelas menyatakan bahwa perintah mencuci bejana yang dijilat anjing dikeluarkan setelah perintah membunuh anjing.
Ulama madzhab Hanafi memperkuat pendapat mereka yang tidak sejalan dengan hadits tersebut, seraya berdalih bahwa ulama madzhab Syafi’i juga tidak komitmen mengamalkan hadits yang dimaksud. Sebab bila mereka komitmen mengamalkan hadits itu niscaya mereka menetapkan bahwa mencuci bejana bukan hanya tujuh kali tapi delapan kali, berdasarkan kandungan hadits Abdullah bin Mughaffal yang diriwayat-kan oleh Imam Muslim, dengan lafazh, (Cucilah bejana itu tujuh kali, lalu campurkanlah yang kedelapan dalam tanah). Dalam riwayat Ahmad disebutkan, ( dengan tanah).
Jawaban pemyataan ini aku (lbnu Hajar) katakan, “Sikap ulama madzhab Syafi’i yang tidak mengamalkan makna lahiriah hadits Abdullah bin Mughaffal tidaklah menjadi dalih bagi mereka (ulama madzhab Hanafi) untuk meninggalkan hadits dalam persoalan ini. Sebab jika tepat alasan yang dikemukakan oleh ulama madzhab Syafi’i untuk tidak mengamalkan makna lahir yang terkandung dalam hadits Abdullah bin Mughaffal, maka gugurlah dalih yang di-kemukakan oleh ulama madzhab Hanafi. Sedangkan jika tidak, maka kedua madzhab ini samasama tidak mengamalkan hadits, demikian dikatakan oleh lbnu Daqiq Al ‘Id.”
Adapun mengenai alasan ulama madzhab Syafi’i sehingga tidak mengamalkan kandungan hadits Abdullah bin Mughaffal terdiri dari beberapa hal. Sebagian mereka ada yang beralasan karena hadits tersebut menyalahi ijma· (kesepakatan) untuk mencuci bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali saja. Namun perkataan ini perlu ditinjau lebih jauh, sebab pendapat seperti itu telah dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri, dan ini pula yang menjadi pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau seperti dinukil oleh Harb Al Karmani. Lalu diriwayatkan dari Imam Syafi’i, ia berkata, “Ini adalah hadits yang tidak aku ketahui keshahihannya.” Akan tetapi, perkataan beliau ini tidaklah menjadi alasan untuk tidak mengamalkan hadits tersebut bagi mereka yang telah mengetahui keshahihannya.
Sebagian ulama madzhab Syafi’i lebih cenderung menguatkan hadits Abu Hurairah daripada hadits Abdullah bin Mughaffal, padahal menguatkan salah satu dari dua riwayat yang ada tidak boleh ditempuh selama kedua riwayat itu masih dapat dipadukan. Dengan mengamalkan hadits Abdullah bin Mughaffal berarti telah mengamalkan pula hadits Abu Hurairah, namun tidak sebaliknya. Lalu tambahan keterangan dari perawi tsiqah (terpercaya) dapat diterima.
Andaikata kita lebih memilih cara menguatkan salah satu dari dua riwayat yang ada, maka kita tidak akan berpendapat untuk mencampur salah satu pencucian tersebut dengan tanah. Sebab, riwayat Imam Malik yang tidak menyebutkan hal ini jauh lebih kuat daripada riwayat yang menyebutkannya. Meskipun demikian, kita tetap berpendapat untuk mencampur salah satu pencucian dengan tanah untuk pengamalan tambahan keterangan yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah (terpercaya).
Sebagian ulama berusaha mengompromikan antara hadits Abu Hurairah (yang menyatakan mencuci tujuh kali) dengan hadits Abdullah bin Mughaffal (yang menyatakan mencuci delapan kali) dari segi majaz (kiasan). Mereka mengatakan, “Karena tanah merupakan jenis lain dari air, maka percampuran keduanya (antara air dan tanah) pada satu kali cucian dihitung dua kali.”
Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh Ibnu Daqiq Al Id dengan mengatakan bahwa sabda beliau (dan campurlah yang kedelapan dengan tanah) sangat jelas memberi keterangan adanya pencucian tersendiri di samping tujuh kali cucian yang lain. Akan tetapi apabila sebelum dicuci dengan air tujuh kali, bejana tersebut terlebih dahulu digosok dengan tanah, maka bisa saja dikatakan menggosok dengan menggunakan tanah ini dianggap pula mencuci, meski hanya dalam pengertian majaz (kiasan). Cara terakhir ini juga merupakan faktor yang lebih menguatkan bahwa mencampur tanah dilakukan pada awal mencuci
Pembicaraan mengenai persoalan ini dan apa yang berhubungan dengannya sangatlah luas sehingga dapat dijadikan satu tulisan tersendiri, namun apa yang telah kami sebutkan dalam tulisan singkat ini telah mencukupi, wallahu a ‘lam.
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 663-664 – Kitab Adzan - 30/08/2020
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 662 – Kitab Adzan - 30/08/2020
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 661 – Kitab Adzan - 30/08/2020