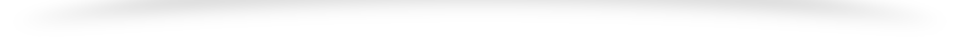Pecihitam.org – Kontekstualisasi sejarah perlu dilakukan untuk dapat memahami atau menjelaskan suatu peristiwa secara sejarah secara utuh. Hal ini berguna pula untuk merinci faktor-faktor yang telah turut berperan dalam pembentukan peristiwa tersebut.
Karena itu, kontekstualisasi sejarah masyarakat Arab pra Islam perlu dilakukan. Hanya saja, kontekstualisasi sejarah masyarakat Arab pra Islam yang akan dilakukan dalam tulisan ini bersifat terbatas, tidak mengungkapkan keseluruhan detil cerita masyarakat arab pra islam yang telah banyak diurai oleh para sejarawan.
Banyak sejarawan seperti Hittl, Hourani, Haekal, dan Hamka, telah berupaya menggambarkan sejarah peradaban Arabia. Secara geografls, hamparan wilayah Arabia sangatlah luas, sekitar 3.700.000 km2, yang terdiri dari hamparan padang pasir dengan sejumlah telaga (oase) yang terisolir, meskipun sebagiannya relatif memadai untuk bercocok tanam.
Hourani menggambarkan bahwa penduduk di wilayah ini adalah nomaden, orang Badui, yang mengembalakan unta, biri-biri atau kambing dengan menggunakan sumber-sumber air padang pasir yang sangat terbatas.
Karena keterbatasan itu, para nomaden ini terkenal pula dengan kebiasaan hidup berpindah-pindah. Namun, di samping itu terdapat pula wilayah yang subur, khususnya di bagian selatan yang meliputi negeri Yaman, Hadramaut, Nejd dan Oman.
Kesuburan inilah yang menjadikan penduduk di wilayah ini kebanyakan terdiri dari para petani yang menanam gandum atau kurma; di samping terdapat pula para pedagang dan pengrajin yang tinggal di kota-kota besar yang kecil.
Hourani menambahkan, para nomaden ini tidak dikontrol oleh suatu kekuasaan yang permanen, melainkan dipimpin oleh ketua kelompok yang terkait dengan keluarga-keluarga yang disekelilingnya berkumpul sejumlah kelompok pendukung yang permanen, yang mengungkapkan kebersamaan dan loyalitas karena adanya kesamaan asal-usul (leluhur).
Kelompok pendukung inilah yang biasanya dipanggil sebagai suku (tribe). Kekuasaan para pemimpin suku tersebut dilaksanakan dari oase di mana mereka memiliki jaringan-jaringan dengan para pedagang yang mengatur perdagangan melalui wilayah yang dikontrol oleh suku tersebut.
Abad keenam, bagi masyarakat Arab tersebut, dikenal pula dengan periode jahiliyah yang biasanya diterjemahkan sebagai masa kelalaian dan barbarisme.
Namun, menurut Jitli, konsep tersebut sebenarnya berarti suatu masa di mana Arabia tidak memiliki dispensasi (toleransi), tidak ada Nabi yang memiliki inspirasi, dan tidak ada pula kitab suci yang diturunkan.
Kalaupun jahiliyah itu sendiri disebut sebanyak empat kali dalam al-Qur’an, yang menggambarkan tentang prasangka jahiliyah (QS. 3: 154), hukum jahiliyah (QS. 9: 50), perhiasan jahiliyah (QS. 33: 33), dan kesombongan jahiliyah (QS. a8: 26).
Menurut Hitti, di kalangan orang Badui agama hanya menempati ruang yang kecil di hati mereka. Hal ini pulalah yang digambarkan oleh al-Qur’an surah at-Taubah (9) ayat: 97.
Meskipun demikian, menurut Hitti juga, agama orang Badui itu mewakili bentuk yang paling awal dan paling primitif dari kepercayaan Semitik.
Agama mereka secara mendasar adalah agama animisme, yaitu penyembahan terhadap objek-objek alam seperti pohon, sumur, gua, dan batu-batuan. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kontras antara oasis dan padang pasir yang menimbulkan konsepsi-konsepsi ketuhanan seperti itu.
Berdasarkan praktik modern di Arab selatan, bahwa tuhan-tuhan diyakini berdiam pada sebuah tempat keramat atau tempat suci. yang disebut haram.
Ciri-ciri dari tempat tersebut, antara lain adalah sebuah tempat atau kota yang jauh dari konflik kesukuan, berfungsi sebagai pusat haji, pusat berkorban, pusat pertemuan dan arbitrasi (bila terjadi konflik).
Sebuah haram juga diawasi oleh suatu keluarga yang mendapat proteksi dari suku yang mengelilinginya. Keluarga seperti itu dapat meraih kekuasaan atau pengaruh dengan memanfaatkan kebanggaan keagamaan mereka, peranannya sebagai arbitrer (penengah) dari perselisihan suku, dan kesempatan-kesempatan untuk berdagang. Salah satu haram yang paling populer saat itu adalah kota Mekkah. Kota ini sebenarnya telah menjadi pusat spiritualitas selama ribuan tahun.
Georgrafer Yunani abad kedua, Ptolemy, telah menyebut kota ini dengan sebutan Makoraba (dari bahasa Arab bagian selatan, maqribah) yang diartikan oleh sebagian orang sebagai tempat pemujaan (temple), meskipun dapat juga bermakna Mekahnya bangsa Arab (Glasse, 1989: 264).