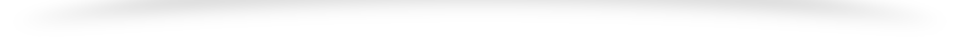Pecihitam.org – Imam Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazaly mewanti-wanti agar manusia tak terjebak perangai buruk. Perangai buruk menjerat manusia. Siapa orang terpenjara perangai buruk, ia bakal susah menjadi saleh. Baik saleh secara spiritual maupun saleh sosial.
Beberapa perangai buruk itu ialah sifat binatang buas (al-sabû’iyah), biologis hewani (al-hayawâniyah), dan watak setan (al-syaithâniyah).
Watak binatang buas adalah selalu memangsa yang lemah. Manusia yang terjerat watak ini, ia merasa superior dan yang liyan adalah inferior. Tak ada kesetaraan, bersifat takabbur – gumedhé. Manusia yang terjerumus watak biologis hewani, ia kerap memenuhi keinginan syahwat perut dan alat kelamin tanpa kompromi nalar dan nurani. Watak setan ialah selalu mengajak kepada laku jahat dan destruktif.
Kesemuanya, kata Imam al-Ghazaly, mesti diwaspadai. Harus ditundukkan. Agar yang mendominasi adalah perangai baik, yakni sifat rabbâniyah.
Kita adalah manusia. Makhluk yang diciptakan dengan cetak-biru tak melulu baik, juga tak paripurna buruk laku. Manusia kadang berbuat baik, kadang beramal maksiat. Tapi itu bukan alasan untuk menafikan satu ikhtiar menjadi manusia saleh bahkan manusia sempurna. Dalam sufisme dikenal sebagai al-insan al-kamil.
Untuk menuju kesempurnaan itu memang tak semudah melempar batu ke sungai. Perlu ada pembimbing yang, dalam istilah mistitisme Islam disebut “mursyid”. Sang mursyid membimbing agar kita bisa mengendalikan sifat-sifat buruk semisal di atas.
Imam al-Ghazaly membuat terminologi sifat nista tersebut dengan metafor binatang. Saya yakin sang empu magnum opus Ihya ‘Ulûmiddin itu tak bermaksud merendahkan derajat hewan sebagai makhluk Allah.
Bahwa ada beberapa sifat dari binatang yang melalui kaca mata kemanusiaan itu buruk. Dan memang itu relevan serta masuk akal. Watak binatangisme merupakan perangai buruk yang mesti dipahami dan diwaspadai. Jika mendominasi, bisa membikin kemanusiaan kita luntur.
Dalam konteks kehidupan sosial berbangsa dewasa ini ternyata ada term “rasis” dalam komunikasi kita. Entah siapa yang kali mula mengenalkannya.
Sependek pemahaman saya, rasis berarti pandangan menilai ras liyan sebagai yang rendah: ras saya lebih baik dari ras kamu. Ungkapan seperti “dasar Cina”, “dasar Jawa”, dan “dasar orang timur” adalah contoh simbol verbal dari perilaku rasis. Dan, itu buruk.
Wal ‘iyâdz billâh, ternyata perundungan rasis secara verbal itu semakin menohok dengan ungkapan “monyet!”. Hari-hari kemarin kata “monyet” ini memenuhi serambi media sosial saya. Laku rasis itu ditujukan pada saudara kita warga Papua.
Monyet sebagai lema kata yang merujuk genus binatang tertentu digunakan untuk menyebut sosok makhluk mulia “manusia”. Ini sangat keterlaluan dan tak beradab. Ternyata laku rasis semakin runcing menodong-merendahkan satu ras tertentu dengan sebutan nama binatang.
Alam demokrasi kita sedang diguncang. Manusia Indonesia banyak yang kebablasan memanfaatkan kebebasan wicaranya. Mungkin kebebasan dimaknainya sebagai “bebas apa saja”. Padahal, ada norma yang mengikat dalam alam demokrasi kita. Baik norma hukum-konstitusional maupun norma sosial keadaban.
Sebagian kita gagal memahami itu. Atau, nalarnya memang cetek? Atau, akal budinya hilang sama sekali? Entahlah, yang jelas saya menolak tindakan apa pun yang rasis.
Kekayaan suku, agama, dan ras di Indonesia merupakan pelangi indah yang terukir secara presisi dalam lanskap kebinekaan. Sewajarnya warna-warna itu harus dijaga. Agar keindahan pelangi Sabang hingga Merauke tetap mewarnai kanvas Nusantara ini. Laku-laku merasa mayoritas atau superior adalah upaya busuk yang berakibat sobeknya lukisan indah Indonesia ini.
Padahal kemanusiaan ditempatkan sangat mulia dalam setiap paham agama. Menghormati ciptaan Tuhan YME berarti memuliakan Sang Pencipta. Menistakan makhuk Allah sama arti mengejek al-Khâliq.
Oknum-oknum rasis dengan simbol verbal “monyet” bagi saya terjangkit satu virus “manusiaisme”. Satu kekejian rasisme yang bukan lagi melalui penyebutan nama satu ras, tapi telah mereduksi marwah satu ras manusia, menggantinya dengan ras binatang.
Subjek rasis memosisikan dirinya sebagai “manusia” dan objek rasis sebagai “hewan”. Ini sangat fatal. Melakukan satu objektivikasi terhadap sesama manusia mengandaikan manusia lain adalah tak berotak, tak beradab, tak berhati, dan sekadar hewan yang kebetulan bernama Ahmad (misalnya).
Laku rasisme seperti itu juga menganggap hewan sebagai makhluk Allah Ta’ala yang rendah. Padahal sesungguhnya perusak alam, penyebab polusi semesta, tukang eksploitasi itu adalah kita manusia. Binatang memang tak berotak-berbudi. Tapi mereka tak pernah mengeruk gunung, membakar hutan, dan laku perusak lainnya.
Walhasil, manusia boleh merasa paling berhak atas kehidupan di muka bumi. Tapi monyet, seburuk apa pun manusia ejek, mereka tak pernah berkata “dasar Manusia!” atas segala keburukan yang kita perbuat.
Wallahul muwaffiq.