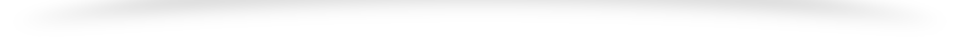Pecihitam.org– Wara’ merupakan salah satu maqam dari maqamat yang harus dilewati penempuh jalan sufi. Di antara ulama sufi yang mengharuskan maqam wara’ adalah Abu Nahsr Abdullah bin Ali Al-Sarraj At-Thusi (w. 378 H/988 M) dan Abul Qasim Abdul Karim Al-Qusyayri (w. 465 H/1072 M).
Daftar Pembahasan:
Pengertian Wara’
Wara’ menurut pengertian kebahasaannya ialah menjauhi dosa, lemah, lunak hati, dan penakut. Sementara dalam istilah Tasawuf, para sufi memberikan definisi yang beragam tentang wara’ berdasarkan pengalaman dan pemahaman masing-masing.
Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa wara’ adalah meninggalakan syubhat (atau yang meragukan) dan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna.
Pengertian serupa juga dikemukakan Yunus bin Ubayd; hanya saja ia menambahkan dengan adanya muhasabah (koreksi) terhadap diri sendiri setiap waktu.
Wara’ juga dikatakan sebagai keluar dari syahwat (kesenangan-kesenangan) dan
meninggalkan kejelekan-kejelekan.
Al-Syibli (w. 334 H/946 M) memberikan pengertian yang lebih mendalam, yakni menganggap wara’ sebagai menjauhi segala sesuatu selain Allah.
Para mufasir, menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyah (w. 751 H/1350 M), mengaitkan sifat wara’ dengan firman Allah
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْۖ
dan bersihkanlah pakaianmu (QS. Al-Mudatstsir ayat 4)
Pakaian di sini dianggap kiasan dari jiwa. Jadi, Qatâdah dan Mujahid, dua
orang tabiin, menafsirkannya dengan pengertian “dan jiwamu bersihkanlah dari dosa”.
Pendapat serupa juga dikemukakan beberapa tabiin yang lain, seperti ‘Ibrahim al-Nakha’i, Al-Dahhak, Al-Sya’bi, dan Al-Zuhri.
Sa’id ibn Jubayr menafsirkannya
dengan “hati dan niatinu bersihkanlah”, sedangkan. Al-Hasan dan Al-Qurazi menafsirkannya dengan “dan akhlakmu perbaikilah”.
Dari beberapa penafsiran tersebut, Ibn
al-Qayyim al-Jawziyah menarik kesimpulan bahwa wara’ adalah membersihkan kotoran hati, sebagimana air membersihkan kotoran
dan najis pakaian.
Antara pakaian dan hati ada hubungan lahir dan batin. Pakaian yang dikenakan seseorang akan mengindikasikan keadaan hati orang tersebut dan keduanya saling mempengaruhi.
Karena itu, Islam melarang orang (laki-laki) mengenakan pakaian yang terbuat dari emas dan sutera, sebab selain akan menimbulkan efek kurang baik, juga akan mengurangi kekhusyu’an.
Dasar & Keutamaan Sifat Wara’
Nabi SAW. secara ringkas dan lugas menjelaskan tentang wara’ dalam hadis
yang diriwayatkan At-Tirmidzi:”
مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ
“Di antara tanda kebaikan keIslaman seseorang: jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.”
Sikap warâ’ mempunyai banyak keutamaan. Karena itu, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam al-Tirmidzî di atas memerintahkan kepada Abu Hurayrah, seorang sahabat, untuk bersikap wara’, sebab wara akan menjadikannya sebagai orang yang paling ahli dalam beribadah.
Pandangan Para Sufi tentang Wara’
Para sufi memberikan apresiasi beragam tentang wara’. Ishaq ibn Khalaf, misalnya, mengatakan bahwa wara dalam perkataan lebih berat daripada wara’ terhadap emas dan perak, sebagaimana zuhud dalam perkataan lebih berat dari zuhud terhadap emas dan perak.
Abû Sulayman al-Darânî menganggap wara’ sebagai permulaan dari zuhud, sebagaimana qana ‘ah yang merupakan awal dari ridha.
Al-Hasan menganggap bahwa wara’ seberat dzarrah lebih baik daripada
seribu puasa dan shalat. Abû Hurayrah juga mengatakan bahwa orang yang wara’ dan zuhud adalah orang yang paling dekat kepada Allah.
Abu Ismail al-Harawi (w 481 H/1088 M) menganggap, bahwa wara’ adalah akhir zuhud bagi orang awam dan permulaan zuhud bagi salik (orang yang meniti jalan Tasawuf).
Dikatakan pula, seseorang tidak dapat
mencapai hakikat takwa sebelum meninggalkan sesuatu yang tidak dilarang, karena takut terperosok kepada sesuatu yang dilarang.
Sedangkan Yahyâ ibn Mu’adz mengatakan bahwa orang yang tidak menikmati lezatnya wara’ berarti belum pemah menikmati pemberian Allah SWT.
Cerita-cerita tentang Ulama yang Wara’
Diceritakan bahwa Bisyr al-Hâfi pernah
diundang dalam suatu acara. Ketika makanan telah disajikan di hadapannya, ia menjulurkan tangannya, bermaksud mengambil makanan tersebut.
Ternyata tangannya tidak mencapai
makanan tersebut. Kemudian, ia berusaha menjulurkannya lagi sampai tiga kali, tetapi tidak juga dapat menjangkau makanan.
Peristiwa tersebut diketahui seseorang, lalu ia, berkata, “Sesungguhnya tangan Bisyr al-Hâfi tidak dapat menjangkau makanan yang syubhat. Karena itu, sungguh orang yang mengundang
ini tidak layak untuk mengundang Syaikh ini”
Diriwayatkan pula bahwa seseorang pernah menulis di atas papan di rumah sewaan. Dia bermaksud menghapuskan tulisan itu dengan debu dinding rumah, karena dalam hatinya terlintas bahwa rumah ita adalah rumah sewaan.
Sebelumnya tidak pernah terlintas hal tersebut di dalam hatinya. Sehingga akhirnya tulisan itu dihapusnya. Setelah itu, ia mendengar suara hatinya sendiri membisikkan bahwa orang yang menganggap remeh terhadap apa yang menimpanya sehingga ia menghapus tulisan itu, ia akan dihisab lama oleh Allah kelak pada hari kiamat.
Dikisahkan pula bila Sufyan al-Tsawrî tidak menemukan makanan yang halal dan bersih dari syubhat, dia kadang-kadang rela tidak makan berhari-hari.
Abdullah bin Mubarok (w. 181 H/797 M) kembali dari Khurasan ke Syam hanya karena lupa mengembalikan pena yang
ia pinjam dari temannya.
Ibrahîm ibn Adham (w. 160 H/777 M) kembali dari al-Quds (Palestina) ke Bashrah (Irak) hanya untuk mengembalikan satu kurma yang terbawa pada kurma yang ia beli karena satu biji kurma itu tidak termasuk yang ditimbang dan dibelinya.
Begitu juga ketika seorang sufi menunggu seseorang yang sedang sakarat al-mawt di tengah malam. Setelah orang itu wafat, sang sufi memerintahkan kepada orang yang hadir agar segera mematikan lampu, sebab minyak lampu tersebut kini telah menjadi milik ahli warisnya.
Ilustrasi-ilustrsi tersebut memberikan
kejelasan tentang wará’ yang ditunjukkan para sufi dalam berbuat.
Mereka selalu berhati-hati dan menjaga diri dari perbuatan syubhat, apalagi
haram; serta menjaga diri dari sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan.
Macam dan Tingkatan Wara’
Menurut al-Qusyayrî yang mengutip
peryataan Yahyâ ibn Mu’adz bahwa wara ada dua macarn: Pertama, wara’ lahir, yakni semua gerak aktifitas yang hanya tertuju kepada Allah. Kedua, wara’ batin, yakni hati yang tidak dimasuki sesuatu kecuali hanya mengingat Allah.
Adapun mengenai tingkatan wara’, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah (w. 751 H/1350 M) dengan mengutip pendapat al-Harawi (w. 481 H/1088 M) mengatakan bahwa ada tiga
tingkatan wara’.
Tingkatan Pertama
Tingkatan Wara pertama adalah dengan menjauhi kejelekan-kejelekan untuk menjaga diri, memperbanyak kebaikan, dan menjaga iman. Ketiga hal tersebut harus dilakukan karena di dalamnya banyak mengandung manfaat.
Tingkatan Kedua
Tingkatkan waro’ kedua adalah dengan memelihara batas-batas sesuatu yang dibolehkan guna menetapkan diri dalam penjagaan dan ketakwaan, atau
untuk naik dan kerendahan, dan untuk
membebaskan diri dan melampaui batas-batas tersebut.
Tingkatan Ketiga
Tingkatkan ketiga adalah waro’ dari setiap hal yang mendorong kepada berantakannya waktu, atau terhadap perasaan terbelenggu oleh keadaan
tafarruq (terpisah (dari Allah]) dan juga terhadap faktor yang menghalangi keadaan jam’ (bersama Allah).
Maksudnya, bahwa orang waro’ dalam
tingkatan ini betul-betul menjaga waktu, tidak memberikan kepada sesuatupun selain Allah untuk menyelinap pada dirinya.
Ia hanya menghendaki Allah, tidak yang lain-Nya, takut, berharap, meminta, merendahkan diri, dan berkeperluan hanya kepada-Nya.
Ia telah merasakan hudur (kehadiran bersama Allah) dan ghaybah (kegaiban dari makhluk), sehingga menyebabkan ia menghabiskan kesaksiaan fananya dan kebersamaannya bersama Allah.
Demikianlah ulasan tentang waro’ yang merupakan salah satau maqam yang harus dilewati oleh seorang salik dalam meniti jalan menuju Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bisshawab.