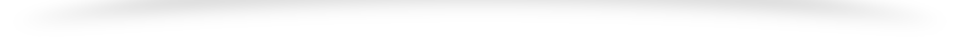Pecihitam.org – Tulisan ini mencoba mengetengahkan argumen bahwa salah satu fungsi filsafat Islam adalah untuk menjelaskan ajaran agama secara filosofis, yaitu tentang kenabian.
Tema kenabian dalam filsafat Islam ini secara lugasnya adalah jawaban bagi pertanyaan: Bagaimana Muhammad dan manusia-manusia suci lainnya bisa menjadi Nabi? Sebelum sampai ke sana, kita simak terlebih dahulu pemikiran para filsuf muslim tentang jiwa.
Daftar Pembahasan:
Filsafat Jiwa
Persoalan jiwa, sebagaimana disinggung di atas, merupakan tema penting dalam filsafat Islam. Terlebih karena agama pada dimensi esoterisnya bekerja pada wilayah kejiwaan. Persoalan jiwa (ruh, nafs) dibahas hampir seluruh filsuf muslim, terutama al-Farabi dan Ibnu Sina (bahasan ini merujuk pada Utsman Najati [terj.], 2002).
Dalam membicarakan jiwa, keduanya sangat terpengaruh oleh konsep “tangga alam” Aristoteles. Sebagaimana filsuf Yunani itu membagi makhluk hidup menjadi tumbuhan dan hewan, kemudian hewan dibagi lagi menjadi hewan itu sendiri dan manusia, al-Farabi dan Ibnu Sina juga membagi jiwa menjadi tiga, yaitu jiwa tumbuhan, jiwa hewan dan jiwa manusia.
Jiwa tumbuhan atau al-nafs al-nabatiyah adalah jiwa yang mempunyai daya untuk tumbuh (al-quwwah al-munammiyah), hasrat akan dan minum (al-quwwah al-ghadziyah) dan reproduksi (al-quwwah al-muwallidah). Sementara itu, jiwa hewan atau al-nafs al-hayawaniyah adalah jiwa yang mempunyai daya penggerak (al-quwwah al-muharrikah) dan daya persepsi (al-quwwah al-mudrikah).
Daya penggerak mengandung kemampuan gerak pada fisik, hasrat seksual dan emosi. Adapun daya persepsi mengandung kemampuan mengindra, baik indra eksternal yang terdiri penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan dan pengecapan, maupun indra internal atau indra batin yang terdiri dari daya-daya akal: indra kolektif (al-hiss al-musytarak), daya imajinasi retentif (al-khayal), daya estimasi (al-wahm), fantasi (al-mutakhayyilah) dan memori(al-hafizhah).
Keterangan singkat tentang indra internal ini saya uraikan dalam tulisan lain berjudul “Akal dalam Filsafat Islam.
Ada dua hal yang dapat dicatat sampai di sini:
Pertama, sebagaimana berlaku pada susunan “tangga alam” Aristoteles, daya-daya yang dimiliki jiwa tumbuhan juga dimiliki oleh jiwa hewan, sementara daya-daya dalam jiwa hewan tidak dimiliki oleh jiwa tumbuhan.
Dengan demikian, hewan menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada tumbuhan dalam tangga alam. Nantinya kita akan mengetahui kedudukan manusia yang lebih tinggi daripada kedua makhluk hidup itu.
Kedua, penempatan indra internal yang berisi daya-daya akal menyiratkan hewan ternyata mampu berpikir! Hal ini nampak menyanggah anggapan umum bahwa hanya manusialah yang berpikir.
Al-insan hayawan nathiq, manusia adalah hewan yang berpikir, demikian adagium yang masyhur itu. Ini kemudian memunculkan pertanyaan: berpikir macam apa yang membedakan akal manusia dengan akal hewan menurut filsuf muslim?
Jawabannya terlihat dari istilah yang digunakan untuk menyebut jiwa manusia. Al-Farabi dan Ibnu Sina, serta para filsuf muslim lainnya, menyebutnya dengan al-nafs al-nathiqah atau jiwa rasional, bukan misalnya al-nafs al-insaniyah.
Kemampuan berpikir rasional inilah yang membedakan akal manusia dengan akal hewan. Dan, berdasarkan tangga alam, jiwa manusia memiliki daya-daya yang juga dimiliki tumbuhan dan hewan, sedangkan keduanya tidak punya daya yang ada pada jiwa rasional.
Jiwa rasional manusia terdiri dari akal-akal yang lebih tinggi dibanding akal biasa sebagaimana dimiliki jiwa hewan. Pada bagian ini, daya jiwa tidak lagi disebut dengan istilah al-quwwah, melainkan al-‘aql (akal).
Jiwa rasional terbagi menjadi dua akal utama: pertama,akal praktis yang memungkinkan manusia mempertimbangkan kebajikan moral dan menyimpulkan keahlian praktisnya dan kedua, akal teoritis. Pada akal teoritis inilah kita akan menemukan bagaimana al-Farabi dan Ibnu Sina membangun argumen tentang kenabian.
Filsafat Kenabian
Akal teoritis atau disebut juga akal ilmiah merupakan alat yang memungkinkan manusia memahami hal-hal yang bersifat umum dan abstrak. Akal yang menempati posisi tertinggi dari seluruh akal ini terbagi lagi dalam bagian-bagian yang tersusun secara bertingkat. Hanya saja, susunan akal teoritis Ibnu Sina sedikit berbeda dengan susunan al-Farabi.
Pada tingkatan terendah dari akal teoritis terdapat akal materi atau akal potensial (al-‘aql al-hayulani). Akal ini, menurut al-Farabi dalam Risalah fi al-‘Aql, membuat manusia memikirkan konsep-konsep, dalam arti melepaskan wujud atau substansi sesuatu dari materinya.
Sehingga membuatnya menjadi gambaran-gambaran konseptual yang bersifat rasional (ma’qulat). Ibnu Sina dalam Ahwal al-Nafs al-Nathiqah mengibaratkannya seperti kesiapan anak kecil untuk belajar menulis.
Tingkatan selanjutnya ditempati akal bakat (al-‘aql bi al-malakah), disebut pula oleh al-Farabi dengan akal aktual. Ketika gambaran-gambaran konseptual-rasional (ma’qulat) dalam akal potensial telah terbentuk, ia tersimpan dalam akal aktual ini.
Dengan akal aktual manusia mampu memikirkan hal-hal rasional tanpa telebih dahulu memisahkan konsep-konsep dari materinya. Karena itulah akal aktual juga disebut akal bakat. Artinya, dengan akal ini manusia berbakat dan telah terbiasa memikirkan hal-hal rasional tanpa banyak usaha.
Jika al-Farabi menyatakannya sebagai satu kesatuan, Ibnu Sina justru memisahkan akal bakat dengan akal aktual (al-‘aql bi al-fi’l). Nampaknya yang membedakan keduanya adalah jenis ma’qulat yang dipikirikan.
Akal bakat memikirkan konsep-konsep yang terkait dengan hal-hal konkrit, seperti pernyataan “total lebih besar dari bagian” atau konsep cara mengendarai sepeda. Sedangkan akal aktual memikirkan konsep-konsep metafisik yang tak lagi terkait dengan, meskipun menggunakan bantuan, hal-hal yang konkrit tersebut.
Tingkatan akal tertinggi dalam susunan jiwa rasional adalah akal mustafad (al-‘aql al-mustafad), secara harfiah berarti akal yang mengambil manfaat. Jika manusia telah mampu memikirkan konsep-konsep metafisik melalui akal aktual dan menerimanya dengan cepat tanpa berupaya keras dan tanpa bersusah payah, maka akalnya telah mencapai tingkatan akal mustafad ini.
Ketercerahan akal mustafad yang mampu menangkap cahaya pengetahuan sejati ini mungkin karena keterhubungannya (ittishal) dengan Akal Aktif, semacam elemen dari ketuhanan (terletak pada tingkat kesepuluh dalam teori emanasi) yang menyimpan dan memberi bentuk-bentuk (wahib al-shuar) kepada segala wujud. Kita bisa katakan, akal mustafad adalah akal yang terhubung langsung dengan Akal Aktif atau Tuhan.
Bagi al-Farabi, akal mustafad inilah yang dimiliki oleh para Nabi sehingga Nabi mampu membaca atau menerima firman Tuhan yang “terpampang di langit”. Hanya saja, bagi Ibnu Sina akal mustafad belum mampu menangkap pengetahuan kenabian. Akal mustafad memang mampu menjadikan pengetahuan sejati hadir tanpa usaha (disebut pengetahuan hudhuri) namun pengetahuan itu lebih bersifat filosofis.
Ia menambahkan satu akal lagi, yaitu akal suci (al-‘aql al-quds). Sementara akal mustafad, dimiliki oleh para sufi atau orang-orang biasa yang mencapai tingkatan spiritual yang tinggi, akal suci inilah yang menurutnya dimiliki oleh para Nabi. Pengetahuan yang berbasis akal suci ini mengambil bentuk ilham atau wahyu.
Dengan demikian, kenabian adalah suatu kualitas jiwa manusia yang mencapai suatu kondisi rasional-spiritual tertinggi. Dengan ungkapan lebih sederhana, Muhammad dan Nabi-Nabi lainnya diangkat sebagai Nabi bukan hanya karena dipilih oleh Tuhan, melainkan karena kualitas jiwa dan akalnya yang mampu menampung pengetahuan sejati tanpa bersusah-payah.
Pengaruh Humanisme dan Mu’tazilah
Konsep kenabian dalam filsafat Islam ini nampaknya dipengaruhi oleh semangat humanisme yang melingkupi konteks kehidupan para filsuf muslim awal (Lihat misalnya Oliver Leaman dalam Nasr dan Leaman [ed.], 2003).
Secara sederhana, humanisme boleh dikatakan sebagai faham yang menjunjung tinggi manusia dengan segala kemampuannya dan bahwa manusia memiliki otoritas dalam mengetahui sesuatu dan bertindak berdasarkan kemampuannya itu.
Tumbuhnya semangat humanisme yang melatarbelakangi filsafat Islam awal dan kemudian mempengaruhi datangnya masa keemasan Islam dipengaruhi pula oleh aliran teologi Mu’tazilah yang salah satu doktrinnya adalah kebebasan berkehendak manusia. Dengan demikian, pengaruh Mu’tazilah bagi filsafat Islam awal jelas tidak dapat diabaikan.
Terlepas dari itu, dengan menelaah konsep jiwa dan kenabian dalam filsafat Islam kita dapat mengambil kesimpulan: bahwa filsafat Islam adalah upaya untuk menjelaskan doktrin-doktrin agama secara filosofis-demostratif. Bisa kita katakan filsafat Islam bermanfaat untuk membela ajaran agama.[]