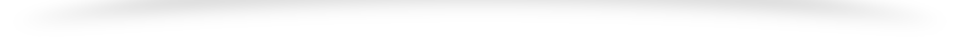Oleh: Hairus Salim, Direktur Eksekutif Yayasan LKiS
Apakah yang telah dan akan terus disumbangkan tradisi literasi pesantren pada masyarakat Indonesia sekarang ini?
Dengan mengambil pengertian paling dini dan dasar dari ‘literatur’, yakni segala sesuatu yang tertulis dan atau tercetak, sebagaimana diungkap Rene Wellek dan Austin Warren, maka dapat dikatakan bahwa pesantren memberikan sumbangan besar pada tradisi literasi di Indonesia. Puluhan dan ratusan kitab, kuning maupun putih, dalam aksara arab, arab pegon dan latin, dari berbagai disiplin dan cabang pengetahuan keagamaan, ditulis oleh kalangan santri sejak berabad yang lalu hingga sekarang. Demikian juga, ratusan bahkan hingga ribuan karya sastra, prosa mau pun puisi, dari kalangan pesantren dipersembahkan hingga akhir-akhir ini mewarnai langit sastra Indonesia.
Kesemua itu telah membentuk kepustakaan pesantren yang sangat luas dan beragam, dan terutama tradisi ilmiah yang sangat kuat. Hal ini terutama jika kita mengacu pada pengertian melek literasi, bukan sekadar sadar membaca dan menulis, tetapi berpikir jembar dan terbuka, dan mampu membaca tanda-tanda zaman. Puluhan hingga ratusan kitab yang wajib dipelajari seorang santri, telah menunjukkan bagaimana tradisi ilmiah itu dibangun dan dikembangkan. Kualifikasi apakah yang harus dimiliki seorang ahli hadis, mufassir dan ahli fiqih jelas standarnya. Dari sinilah terbangun apa yang disebut sebagai otoritas, keabsahan seseorang untuk disebut ahli di bidangnya. Karena itu bisa dimaklumi jika kalangan pesantren inilah yang paling merasa terganggu ketika ada seseorang yang datang dari antah barantah tiba-tiba mengklaim kebenaran, terhadap dan dalam suatu pendapat keagamaan, dan dengan gampangnya menyalahkan pendapat orang lain.
Pada tahun 1970, K.H. Siradjuddin Abbas menerbitkan buku berjudul “40 Masalah Agama” yang terdiri dari 4 jilid berisi bahasan masalah-masalah keagamaan. Di dalam bagian pengantar, K.H. Siradjuddin Abbas di antaranya mengatakan:
“Baik juga saya jelaskan terus terang, bahwa saya, pengarang buku ini, adalah penganut mazhab Syafi’I Rahimahullah dalam syariat dan ibadat dan faham ahlu as-sunnah wa al-jamaah dalam I’tiqad. Maka karena itu fatwa-fatwa dalam buku sejalan dengan fatwa sebagai termaktub dalam mazhab Syafii…”
K.H. SIradjuddin Abbas adalah ulama asal Sumatera Barat, yang menjadi pendiri sekaligus ketua Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI), sebuah organisasi kalangan santri yang secara keagamaan hampir bisa dikatakan memiliki akar tradisi yang sama dengan Nahdlatul Wathan (NW, NTB), al-Washliyah (Sumut), dan Nahdlatul Ulama (NU), DDI (Sulsel) dan Al-Khairat (Palu). Karena itu, bagi kalangan pesantren, barangkali ketika membaca bagian pengantar di atas tidak merasa aneh. Pengakuan identitas penulis sudah biasa dan menjadi tradisi di dalam penulisan kitab kuning.
Para penulis kitab biasanya akan menyebut nama daerah asalnya dan mazhabnya. Penyebutan ini kadang sangat kentara di dalam nama, terkadang dalam bagian ‘tarjamatul mu’allif’. Sebagai misal, saya ambil saja secara acak sebuah kitab yang ada dalam koleksi perpustakaan saya, Hasyiyah As-Showi, sebuah kitab berisi hasyiyah tafsir Jalalain. Dalam pengantar disebutkan bahwa penyusun Kitab As-Showi ini adalah al-Allamah Ahmad bin Muhammad Ash-Showi Al-Mishri al-khilwati Al-Maliki. Dengan informasi ini jelaslah bahwa sejak awal penulisnya tidak menutup-nutupi bahwa dia bermazhab Maliki, dan andai ada pendapatnya yang terkesan cenderung mengedepankan pendapat Imam Malik, dan mengesampingkan pendapat imam-imam lain, maka hal itu bisa dimaklumi. Yang menarik, kitab yang ia bahas adalah Tafsir Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua orang Jalal, Jalaludin As-Syuyuti dan Jalaluddin As-Mahalli, yang keduanya menyebutkan identitasnya sebagai ‘asy-syafi’I’ dalam bagian dari namanya. Amboi, betapa menariknya, penganut mazhab Al-Maliki mengulas kitab karya dua orang imam penganut mazhab syafi’i.
Di dalam ilmu sosial kontemporer, penyebutan identitas diri ini, disebut sebagai ‘fairness’, kejujuran sebagai landasan baru obyektivitas. Sebelumnya, para ilmuwan sosial meyakini bahwa obyektivitas dan kenetralan itu harus ada dan penting di dalam karya ilmiah dengan penerapan prosedur-prosedur teknis ilmiah dalam proses penelitian dan penulisan sebuah karya, dan mengabaikan sama sekali pentingnya identitas si peneliti atau si penulis sebagai unsur yang mempengaruhi subyektivitas. Tetapi belakangan makin disadari bahwa obyektivitas itu hanya isapan jempol belaka dan netralitas itu adalah gumpalan awan di langit, karena tak pernah betul-betul ada yang disebut sebagai obyektif. Selalu ada unsur subyektivitas di dalam penyeleksian data, penyusunan dan penafsiran serta penulisan karya yang mengakibatkan munculnya ‘biased’ di dalamnya. Kebangsaan, keagamaan, gender, dan identitas lain-lain, termasuk lembaga yang membiayai, pasti mempengaruhi karya seseorang, karena itulah ‘fairness’ menjadi salah satu ukuran baru apa yang disebut obyektivitas. Tapi seperti disebut di atas, tradisi literer di pesantren dengan kitab kuningnya sudah jauh hari mengenal tradisi ini.
Pengakuan pada orientasi keagamaan ini, dan tidak menutupi-nutupi, apalagi sampai mengklaim dengan jumawa seakan mewakili suara seluruh umat, dengan demikian juga sudah merasa menggenggam kebenaran, barangkali bisa menyumbang untuk mengurangi ketegangan keagamaan yang bersumber pada perbedaan politik ini. Kejujuran mengenai asal-muasal tradisi dan mata rantai keilmuan.
Tentu saja ilustrasi di atas hanyalah salah contoh bagaimana tradisi literasi di pesantren. Tradisi yang telah dibangun sangat panjang, dan membentuk mentalitas tersendiri: melakukan riset terus-menerus, menulis tanpa henti, dan terus memikirkan hal-hal baru dan tantangan baru. Dan dalam tradisi itu pulalah terbentuk kebiasaan berbeda pendapat. Dan berbeda pendapat itu sendiri merupakan hal mendasar dalam tradisi ilmiah. Ia menjadi resiko dari berpikir.
Kalangan pesantren tentu sudah tidak asing dengan kata-kata seperti “wa fiihi aqwalun” ( dan dalam hal itu ada beberapa pendapat) atau “wa a’alaiha qaulani” (dan atas hal itu ada dua pendapat) atau “wakhtalafu al’ulama fii…” (dan para ulama berbeda pendapat mengenai…) yang biasa muncul dalam narasi kitab kuning ketika membahas aspek suatu masalah. Kata-kata ini menunjukkan tidak ada pendapat tunggal dan hampir selalu ada banyak pendapat. Kalau pun ada kata “ittafaqa al-ulama…” (para ulama sepakat…) atau “wa la khilafa” (Dan tidak ada perbedaan pendapat…) misal dalam suatu perkara, tetap akan terjadi perbedaan dalam aspek yang lebih rinci yang lain misal menyangkut sifat, syarat, sebab, dan lain-lain.
Itulah salah satu karakter kitab kuning. Karakter yang selama ini (atau seyogyanya) telah menubuh dalam pikiran kalangan santri untuk senantiasa bersedia dan berlapang dada dalam perbedaan. Dalam kesadaran terhadap perbedaan inilah, kita jadi berendah hati dan tidak jumawa, tidak merasa paling benar sendiri. Sebaliknya, kita tetap terus saling menghormati dalam perbedaan dan tetap dalam persaudaraan.
Ribuan lembar traktat keagamaan, pedoman beribadah, hingga karya-karya sastra yang dipersembahkan orang-orang pesantren, adalah sumbangan besar bagi literature dan kepustakaan Nusantara. Tapi di luar himpunan karya kuantitatif itu, tradisi ilmiah, khususnya dalam kehidupan keagamaan itulah, yang telah disumbangkan pesantren bagi Indonesia masa kini dan masa depan.
Dalam kesadaran seperti itu pulalah, kita semestinya tak perlu merasa khawatir dan takut dengan perbedaan, dengan ikhtilaf, karena insya Allah ikhtilaf itu akan menjadi rahmah, bukan laknat. Perbedaan pada akhirnya tak lebih memandangi bentangan pelangi yang elok sehabis hujan sembari menikmati kopi sore yang hangat.
Semoga sepercik lontaran ini, akan terus mendorong lahirnya karya-karya dari pesantren, dalam bentuk apapun, dan memberikan warna dan fondasi pada keindonesiaan.
- Mengenal Imam Abu al-Hasan al-‘Ijli Pengarang Kitab al-Tsiqat - 09/03/2024
- Menteri Agama RI Luncurkan PMB PTKIN 2024 - 20/01/2024
- Gagasan tentang Pluralisme Menurut Para Sufi, Filsuf dan Faqih - 18/01/2024