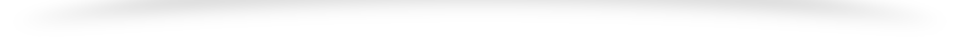Pecihitam.org – Film Joker yang baru dirilis dan sedang heboh-hebohnya saat ini dapat menuntun kita kepada konsep dasar tentang manusia menurut Filsafat Islam.
Dirilisnya film “Joker”, tepatnya pada 2 Oktober lalu dan kini tayang di bioskop-bioskop di seluruh tanah air, menjadi kehebohan baru dalam jagad perfilman.
Seperti halnya “Venom” yang terlebih dahulu dirilis oleh Marvel Studio, “Joker” hasil garapan DC Comics ini juga menceritakan latar belakang dan sebab-musabab lahirnya seorang penjahat yang nantinya menjadi musuh Batman, sang pahlawan super.
Lewat film ini kita seakan disuguhi semacam kisah pengantar tentang pertarungan kebaikan dan kejahatan dari sisi orang jahat.
Sebagaimana kisah-kisah awal karakter antagonis dalam banyak film, Joker mulanya bukanlah seorang yang jahat. Arthur Fleck yang berprofesi sebagai komedian mendapati kehidupannya penuh kegagalan.
Nestapa bertambah ketika masyarakat disekitarnya merendahkan, menyingkirkan dan memarjinalkan dirinya. Derita demi derita dilaluinya hingga muncul kebencian dan hasrat membalas dendam terhadap masyarakat yang menurutnya telah menzholiminya. Lalu lahirlah Joker.
Terinspirasi dari film Joker yang menceritakan latar belakang lahirnya seorang penjahat, tulisan ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan filosofis: bagaimana seseorang bisa berbuat jahat?
Apakah manusia pada dasarnya baik lalu karena faktor tertentu berubah jadi jahat? Ataukah manusia sebenarnya justru jahat tapi norma-norma yang membuatnya baik? Apa hakikat manusia? Mari kita telaah berdasarkan pandangan filsafat Islam.
Para filosof muslim madzhab peripatetik (masya`iyyah) – tokoh-tokohnya antara lain al-Farabi dan Ibnu Sina – menyatakan bahwa dalam proses penciptaan berupa emanasi, manusia menempati tingkatan terendah dari sepuluh hirarki wujud, bersama-sama dengan binatang dan tumbuhan (Mulyadi Kartanegara, 2003: 36).
Tapi manusia masih lebih tinggi kedudukannya dibanding binatang dan tumbuhan dilihat dari kualitas jiwa (nafs) masing-masing.
Jiwa tumbuhan disebut al-nafs al-nabatiyyah yang memiliki daya nutrisi, daya pertumbuhan dan daya reproduksi. Sementara itu, jiwa hewan disebut al-nafs al-hayawaniyyah, memiliki daya penggerak yang terdiri atas daya tarik, syahwat dan emosi.
Daya-daya dalam kedua jiwa ini dimiliki manusia, tapi tumbuhan dan hewan tidak punya jiwa dengan daya seperti yang dimiliki jiwa manusia.
Jiwa manusia disebut dengan jiwa rasional (al-nafs al-nathiqah). Jiwa inilah yang membedakan manusia dari hewan dan tumbuhan. Nampaknya konsepsi jiwa menurut para filosof muslim yang diadopsi dari pembagian jiwa Aristoteles inilah yang melahirkan semboyan “manusia adalah binatang yang berakal”.
Jiwa rasional ini dibagi lagi oleh Ibnu Sina menjadi dua, yaitu akal praktis dan akal teoritis (Utsman Najati, 1993: 167-169). Akal praktis berkemampuan memikirkan hal-hal yang bersifat parsial menyangkut mana hal-hal yang harus dilakukan dan mana yang tidak, mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Pada bagian inilah prinsip-prinsip moral bertempat dan mengalami kecerahan.
Adapun akal teoritis merupakan bagian jiwa yang mendorong daya intelektual manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membangun gagasan-gagasan teoritis dan mengembangkan pengetahuan.
Akal teoritis dapat menangkap hal-hal rasional, mempersepsinya dan menghubungkan prinsip-prinsip rasional utama dengan hal-hal aktual. Puncaknya, jika akal ini terasah dengan baik manusia dapat memperoleh pengetahuan sejati. Daya semacam ini disebut dengan akal perolehan (al-‘aql al-mustafad) yang hanya dimiliki para Nabi dan Rasul.
Di lain pihak, filsafat Islam madzhab iluminasionis (isyraqiyyah) – dengan Syuhrawardi sebagai tokoh utamanya dan dalam bagian tertentu termasuk pula Ibnu Arabi – mengatakan bahwa manusia merupakan pancaran cahaya dari Sang Sumber Cahaya (al-Nur/ Tuhan).
Filsafat isyraqiyyah memang menganalogikan proses penciptaan alam dan hirarki wujud dengan matahari dan cahayanya.
Dengan analogi tersebut, makhluk-makhluk sebagai pancaran cahaya Tuhan memiliki warna-warnanya sendiri yang khas, meski kemudian warna-warna tersebut tidak berarti apa-apa karena fakta bahwa semua warna menjadikan Cahaya Tunggal tampak (penulis juga pernah menyinggung hal ini di sini ).
Konsekuensi dari konsep pancaran cahaya tersebut di atas adalah bahwa cahaya-cahaya yang memancar bisa nampak lebih terang atau meredup, tergantung jaraknya dengan sumber cahaya. Semakin dekat dengan sumber, cahaya akan terlihat semakin terang dan sebaliknya, semakin jauh ia akan terlihat semakin redup dan gelap.
Dalam perdebatan mengenai ontologi dalam filsafat Islam, konsep ilmunasi Syuhrwardi difahami sebagai prinsip bahwa esensi mendahului eksistensi. Berdasarkan itu, manusia pada hakikatnya hanyalah ide, konsep, gagasan, esensi. Keberadaanya tak lebih dari sekedar pancaran cahaya yang tak nyata, kecuali mendapat makna.
Prinsip ini kemudian dikritik oleh Mulla Shadra yang menyatakan bahwa eksistensi (wujud) mendahului esensi (mahiyah), bahkan wujud adalah satu-satunya realitas (ashalah al-wujud).
Mengelaborasi konsep emanasi madzhab peripatetik dan kesatuan wujud (wahdah al-wujud) Ibnu Arabi, Mulla Shadra menegaskan eksistensi manusia adalah riil seperti halnya eksistensi Tuhan. Hanya saja, eksistensi manusia berada dalam gradasi wujud (tasykik al-wujud).
Dalam gradasi tersebut, manusia berasal dari Wujud Yang Satu (Tuhan) tapi wujudnya mengalami perjalanan turun ke bawah, ke tingkat yang lebih rendah.
Untuk itu, kualitas eksistensi manusia dilihat dari suatu proses evolusi dan transformasi ruhaniyah. Perjalanan ruhani itu dikenal dengan istilah yang juga menjadi judul karya terbesar Mulla Shadra “al-Hikmah al-Muta’aliyah fi al-Asfar al-‘Aqliyyah al-Arba’ah”.
Di sana ia menggambarkan empat tahapan ruhani yang terlalu luas untuk diuraikan dalam ruang tulisan yang terbatas ini. Pada intinya, dengan menapaki tahapan-tahapan tersebut manusia berpotensi meraih tingkatan wujud yang lebih tinggi.
Sebaliknya, manusia juga dapat menurun derajatnya atau tetap pada tingkatan yang rendah seperti awal keberadaannya. Oleh karena itu, eksistensi manusia berada pada derajat yang berbeda-beda tergantung pada transformasi ruhaninya (Syaifan Nur, 2002: 202).
Berdasarkan uraian di atas, manusia menurut Filsafat Islam terletak pada prinsip “manusia itu baik” atau berpotensi menjadi baik. Hal itu karena jiwa manusia yang memiliki daya-daya rasional (peripatetik), merupakan pancaran cahaya ilahi (Syuhrawardi) dan wujudnya bertransformasi ke tingkatan yang lebih tinggi (Shadra).
Jika terjadi penyimpangan, maka manusia itu baru terkungkung dalam jiwa binatang dan tumbuhan tanpa mendayagunakan jiwa rasionalnya (peripatetik), cahaya ilahinya redup (Syuhrawardi) atau ruhaninya tidak bertransformasi (Shadra).
Dengan ini, dalam hubungan sosial kita, ketika menemukan seseorang yang diduga berbuat kejahatan, kita harus terlebih dahulu berpijak pada prinsip bahwa “manusia itu baik”. Karena manusia menurut filsafat Islam hakikatnya baik, manusia yang jahat senantiasa berpotensi kembali kepada kebaikan. Bukankah pada setiap akhir pertarungan Batman selalu mengampuni Joker?!
Sumber-Sumber
- Kartanegara, Mulyadi, 2003, Pengantar Epistemologi Islam, Bandung: Mizan.
- Najati, Muhammad Utsman, 1993, Jiwa dalam Pandangan Para Filosof Muslim (terj.), Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nur Syaifan, 2002, Filsafat Wujud Mulla Shadra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar