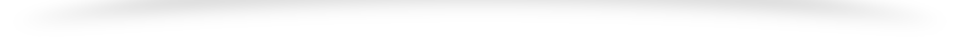Pecihitam.org – Bahasa Arab menurut al-Jabiri berperan besar dalam membentuk nalar keislaman kita, nalar keislaman yang terlalu bergantung pada nalar bayani dan tekstual.
Sudah menjadi keyakinan kaum muslimin bahwa bahasa Arab adalah bahasa agama Islam. Hal itu karena memang “takdir sejarah” mengguratkan wahyu Allah turun pertama kali di tengah masyarakat Arab dan disampaikan oleh seorang Nabi yang berwicara Arab. Sejak itu, kehidupan religius umat Islam tidak pernah lepas dari bahasa Arab dan secara umum kebudayaan Arab. Bagaimana jika al-Qur’an turun di Indonesia?
Tapi kita tidak berbicara mengenai kemungkinan historis lain jika agama Islam lahir bukan di bumi Arab. Tidak pula membicarakan bagaimana suatu produk budaya berupa bahasa mendapat kedudukan relijius yang sebegitu rupa.
Bagaimanapun, kata para ahli linguistik, bahasa adalah simbol yang menjadi penanda terhadap makna-makna. Sementara makna merupakan hasil pemahaman kultural suatu masyarakat terhadap dunia dan kehidupannya. Karena pengalaman manusia berbeda-beda, waktu dan tempatnya, maka wajarlah jika bahasa berbeda-beda pula bentuknya.
Tapi bagaimana jika bahasa merupakan suatu bentukan “resmi”, dibangun dan disahkan oleh otoritas tertentu? Inilah yang menjadi kritik Muhammad Abid al-Jabiri (1931-2010), seorang pemikir muslim kontemporer, terhadap bahasa Arab.
Kita, karena itu, harus memperhatikan bahwa bahasa Arab yang menjadi sasaran kritik al-Jabiri bukanlah bahasa Arab dengan keseluruhan ragamnya, melainkan bahasa Arab baku (fushah) yang dibentuk oleh suatu proses kodifikasi dan klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli bahasa pada abad ke-2 hingga pertengahan abad ke-3 Hijriyah. Rentang masa ini disebut era kodifikasi.
Dalam Takwin al-‘Aql al-‘Arab (terjemahan Ilham Khoiri, 2014) al-Jabiri menjelaskan bahwa era kodifikasi adalah periode ketika para ilmuwan dan cendekiawan merekonstruksi pengetahuan dalam rangka mewujudkan kerangka keilmuan sebagai referensi pemikiran Arab-Islam. Pada masa inilah hadis-hadis berhasil ditransmisikan, dikumpulkan, diklasifikasi dan dibukukan yang dengannya kemudian lahir ilmu-ilmu agama Islam semisal tafsir, fiqih dan lain-lain.
Al-Jabiri menegaskan bahwa kodifikasi bukan berarti memproduksi ilmu dan pengetahuan yang orisinil, melainkan menemukan, mengumpulkan dan mengklasifikasi ilmu-ilmu yang telah ada. Dalam proses tersebut ilmu mengalami pengurangan, penambahan, seleksi, koreksi dan pemilahan sesuai dengan bangunan pemikiran yang melingkupi peradaban Arab-Islam pada era tersebut.
Proses kodifikasi, lanjut al-Jabiri, “tidak terbatas pada upaya membentengi warisan kultural Arab-Islam dari kesirnaan dan tidak sekedar mengklasifikannya agar mudah dipelajari, tetapi sesungguhnya merupakan proses rekonstruksi terhadap warisan kultural tersebut dan menjadikannya ‘tradisi’, yaitu sebagai kerangka rujukan bagi cara pandang masyarakat Arab terhadap segala hal.”
Dengan kata lain, ilmu-ilmu Islam di era kodifikasi menjadi (di)paten(kan) dan (di)resmi(kan) lalu ditetapkan sebagai tradisi (turats) yang menjadi rujukan kebudayaan Arab-Islam di masa-masa berikutnya. Karena itu, Wajarlah jika Fazlur Rahman menyatakan dalam Islam (terjemahan oleh Irsyad Rafsadie, 2017) bahwa era kodifikasi adalah era kelahiran ortodoksi Islam.
Proses kodifikasi ilmu menghajatkan proses kodifikasi pula terhadap bahasa Arab yang menjadi bahasa sumber keilmuan Islam. Di samping karena proyek kodifikasi ilmu-ilmu yang sedang marak, ada kekhawatiran terjadinya kerusakan bahasa Arab karena menyebarnya dialek-dialek yang dianggap menyimpang dari apa yang dianggap sebagai “bahasa Arab murni”.
Upaya menemukan bahasa Arab murni tidak mungkin dilakukan di kalangan masyarakat perkotaan sebab di wilayah-wilayah itulah terjadi penyimpangan-penyimpangan bahasa. Karena itulah para ahli bahasa harus menemukan dan mengumpulkan perbendaharaan bahasa dari masyarakat yang masih memelihara bahasanya berdasarkan insting (fitrah) dan kemurnian pelafalan. Para ahli bahasa menemukan bahasa semacam itu di kalangan orang-orang Arab Badui.
Persoalannya bahasa orang-orang Arab Badui adalah bahasa masyarakat nomaden yang terisolir dari kehidupan peradaban yang lebih maju, sehingga bahasa mereka tidak mengandung kekuatan yang bersifat ilmiah dan dapat dipelajari secara ilmiah pula. Padahal, masyarakat Arab-Islam pada abad ke-2 hijriyah membutuhkan perangkat kebahasaan yang dapat mendukung proyek rekonstruksi ilmu-ilmu Islam.
Oleh karena itu, pengumpulan kosakata dan ungkapan-ungkapan bahasa Arab Badui memerlukan proses klasifikasi, koreksi dan kreasi untuk mengubahnya menjadi bahasa Arab yang ilmiah. Dari sinilah kodifikasi bahasa Arab dilakukan dan kemudian melahirkan apa yang kita kenal dengan bahasa Arab fushah, bahasa yang (di)benar(kan), bahasa yang (di)resmi(kan). Namun pada proses “pematenan”, “peresmian” dan “pemba(e)kuan” bahasa Arab itulah terletak persoalan yang dikritik oleh al-Jabiri.
Salah satu penanda kelahiran bahasa Arab fushah adalah kehadiran kamus bahasa Arab terkaya dan terbesar, yakni “Lisan al-‘Arab”. Awalnya al-Jabiri memuji proses kodifikasi bahasa Arab sebagai “mukjizatnya orang Arab” melalui analisa terhadap kamus yang disusun oleh al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi (100-170 H) tersebut.
Menurutnya, al-Khalil memiliki kepekaan sense of music dalam meneliti syair-syair Arab, lalu dengan nalar matematisnya menetapkan kategori-kategori teoritis terhadap kosakata-kosakata Arab. Al-Khalil misalnya menemukan bahwa kata-kata bahasa Arab adakalanya terdiri dari dua huruf (tsuna`i), tiga huruf (tsulatsi), empat huruf (ruba’i), atau lima huruf (khumasi).
Dalam kata-kata tersebut terdapat huruf-huruf yang bisa dibuang, sehingga kata-kata berimbuhan (mazid) dapat dikembalikan kepada bentuknya yang asli tanpa tambahan (mujarrad). Berdasarkan itu al-Khalil kemudian menyusun huruf-huruf hijaiyah satu dengan yang lain menjadi kata-kata yang terdiri dari dua huruf, tiga, empat, atau lima dengan memanfaatkan seluruh kemungkinan yang ada, seperti bada, daba, abada, adaba, bada`a, da`aba, dan seterusnya.
Langkah al-Khalil ini diikuti oleh para penyusun kamus-kamus bahasa Arab lainnya serta mendorong lahirnya ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu-ilmu ini juga menampilkan kenyataan bahwa bahasa Arab fushah adalah bahasa logis-matematis. Dalam ilmu shorf, misalnya, kita dapat mengubah kata-kata Arab kepada bermacam-macam bentuk (shighah) yang tentu saja mengubah pula makna dan fungsinya, hanya dengan mengutak-atik kata dasarnya.
Karena yang digunakan adalah nalar matematis maka realitas kebahasaan Arab fushah bertolak dari “kemungkinan kognitif” (imkan al-dzihn), tanpa memperhatikan kemungkinan riil (imkan al-waqi’). Dengan kata lain, orang bertutur bahasa Arab berdasarkan olah nalar kognitifnya sendiri, bukan dari pemahaman karsanya (fitrah-nya) terhadap realitas. Bahasa Arab fushah, karena itu, adalah bahasa yang bersifat logis dan struktural, bukan bahasa kultural.
Dengan demikian, bagi al-Jabiri, proses kodifikasi bahasa Arab merupakan peralihan dari bahasa Arab pasaran (‘amiyah) yang tidak ilmiah, yaitu bahasa yang tidak bisa dipelajari secara ilmiah karena berasal dari pengalaman langsung terhadap realitas, kepada bahasa baku yang ilmiah, yaitu bahasa yang tunduk kepada sistem kebahasaan yang terhimpun dalam ilmu-ilmu bahasa Arab, seperti nahwu dan shorf dan lain-lain. kebakuan bahasa Arab juga menjadi kebekuannya.
Akhirnya, bahasa Arab menurut al-Jabiri adalah bersifat ahistoris. Ia melampaui sejarah dan terlepas dari tuntutan-tuntutan perkembangan. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Bahasa Arab fushah telah ditetapkan sebagai turats dan dapat dipelajari secara ilmiah karena ia memiliki kategori-kategori yang beku dan final, terbatas kata-katanya, sehingga tidak mampu memperbarui diri seiring dengan perbuahan situasi dan kondisi.
Dengan peran bahasa Arab fushah sebagai pengantar ilmu-ilmu keislaman, maka apa yang kita fahami dari ilmu-ilmu tersebut adalah pemahaman orang-orang Arab di era kodifikasi, bukan dalam konteks dan ruang lingkup pemikiran masa kita sekarang, sebagaimana orang-orang Arab pada era kodifikasi memahami realitas dalam nalar orang-orang Arab Badui.
Al-Jabiri sejak awal telah menegaskan bahwa bahasa merepresentasikan nalar. Artinya, bahasa yang digunakan seseorang menggambarkan alam nalarnya. Ia mengatakan: “inna nufakkir kama natakallam” (kita berpikir sebagaimana kita berkata). Artinya, bahasa yang membatasi kemampuan kita dalam berbicara pada saat yang sama juga membatasi kemampuan kita dalam berpikir.
Dengan ungkapan yang lebih sederhana, pikiran kita dipengaruhi dan dibatasi oleh bahasa. Sementara Bahasa Arab menurut al-Jabiri berperan besar dalam membentuk nalar keislaman kita, nalar keislaman yang terlalu bergantung pada nalar bayani dan tekstual dan kesulitan memahami realitas dengan nalar irfani (intuitif) dan burhani (demonstratif-filosofis).