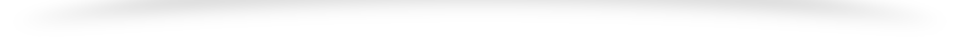Pecihitam.org – Spiritualitas manusia sudah menjadi trend komoditi bentuk yang bebas dan membebaskan, ia kadang seolah merubahkan diri menjadi penjara dalam rongga dada dari pada sebuah keutamaan.
Artinya bila manusia gagal memaknai, ia akan memvonis setiap kejadian sesuai kehendaknya.
Tentu hal ini merobek rakitan kedewasaan yang seharusnya menjadi tunggangan spiritual, bak mengusang dan mengelupas sampai bersembunyi di rongga ufuk dunia, meredum terbang entah kemana.
Kebenaran sejati yang sudah dititahkan milik Tuhan, sering dikobarkan nalar sporadis manusia yang beranaluri kelam. Ia kadang menerobos angkuh, menghantam kromo norma sosial, bahkan “menduakan” perilaku sopan sebagai atribut bernegara.
Kesatuan Nusantara yang telah lama sekali mati-matian dirajut para ulama dan negarawan besar, perlahan mengerucut dijadikan “candaan” oleh barisan manusia serampangan. Kitapun mulai khawatir, apakah ini yang digariskan Tuhan:
Kamu kira mereka (umat) itu bersatu, (padahal) hati mereka tercerai berai. QS:59:13
Hematnya, mahligai mega bernama Nusantara sah dalam pandangan dunia, namun dihuni oleh mayoritas roh benawat yang berakal pekat, akhirnya tercerai berai.
Ini disebabkan oknum individu hingga kelompok yang tidak pandai bersandiwara, enggan mau menguatkan dialogi yang kompromistis. Ada sebagian ‘geng’ fanatisme yang ingin mendaulatkan formalisasi hukum agama, juga sebagian lain upaya ingin menawarkan istilah model pembaharuan hukum agama.
Media massa nasional yang seharusnya sebagai subyek pengendali akal budi, semakin menampilkan gaya hidup tanpa kendali. Koran, internet, hingga televisi sesungguhnya telah didikte sebagai agen biro iklan daripada sebagai tempat pebentukan opini, pikiran politik dewasa dan pesan-pesan moral.
Tak ayal, dalam konten media-media itu dikiblatkan dan manusia sebagai anggota tetap budaya konsumerisme kekinian, karena kehabisan energi untuk bertahan dari pengaruh pasar dunia.
Praktek eksploitasi sumber daya manusia, akhirnya, terus terkeruk menjadi isu “purbakala” yang bernama kapitalisme. Sangat mahal untuk menjungkal model tersebut karena bisa mengorbankan banyak manusia, kecuali dengan etika kemakmuran sambil mengadopsi sistem ekonomi yang ada.
Di lain sisi, ketika masyarakat dihadapkan isu sentimen, seperti rumput kering, dilempar puntung rokok menyala saja mudah tersinggung dan terbakar, menjelma jadi “LSM” dadakan yang kasar.
Upaya Menhindari Narasi Utopis
Agama atau kepercayaan sewajarnya adalah lambang identitas kolektif dan berkepedulian sesama. Menurut analisa Weber, agama harus menjadi landasan kuat dalam mencerahkan kemajuan serta menjelma prinsip manusia kekinian.
Tetapi, dalam prakteknya, agama semakin diduplikat menjadi alat tafsir “ala” kadarnya, seperti legitimasi praktek kekuasaan kelompok tertentu, sehingga mematikan gerakan emansipatoris yang dialogis, wajar hal ini dihadapkan kapada narasi yang utopis.
Dalam realitas, kedaulatan wacana nampaknya kesulitan berkembang, seiring adanya benturan serius mulai dari pembentukan narasi anyar tanpa meninggalkan paradigma yang masih berlaku di masyarakat, hingga pembentukan narasi dengan mengabaikan paradigma yang sudah berlaku.
Tentu ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, baik diskusi kaum abangan hingga kelompok yang sudah mapan. Semuanya itu ditujukan untuk membentuk pemikiran yang ideologis.
Membincang pembentukan paradigma baru, Karl Mannheim, tokoh yang dikenal sebagai pendiri sosiolog yang berbicara dalam bukunya Ideology dan Utopia: Menyingkap pikiran dan politik, menyatakan pemikiran baru dapat bersifat ideologis atau utopis bila dikaitkan dengan pemikiran yang telah ada sebelumnya, jika pemikiran baru berpijak pada paradigm yang sudah berlaku, maka itu ideologi. Namun bila mengabaikan paradigma yang sudah ada, maka itu akan bersifat utopis.
Kemudian Mannheim membagi dua macam utopia, relatif dan absolut, bila pemikiran baru diaplikasikan menjadi sebuah paradigma baru, maka itu disebut utopia relatif.
Namun bila utopia itu tidak mungkin dipraktekan, maka kapanpun dimanapun ia akan menjadi sebutan utopia absolut. Perubahan memang memiliki banyak jendela, tapi tidak semua jendela terbuka, kadang hanya satu atau jendela yang terbuka untuk mungkin diterapkan. Hal ini menganut pakar sosial Marxist.
Dengan demikian, tawaran isu perubahan harus berpijak pada kebenaran kontekstual menyeluruh dan struktur kemasuk-akalan dari suatu orang atau kelompok, al-‘ibrotu bi khushush as-sabab laa bi ‘umum al-lafzhi.
Sehingga, kita dapat mempertimbangkan usulan tanpa menimbulkan kejumudan sosial yang meresahkan, guna memelihara cita-cita emansipatoris secara sosial dan “memihak” kepada yang tertindas serta meniliki langsung ke arus masyarakat lapisan bawah.
Membincang Dekonstruksi
Ketika manusia gagal menggunakan etika, seakan hilang ritme kesalehan sebagai pemandu jalan daya jelajah pandang. Memvonis orang bersalah hanya karena tak selera, sementara disekitarnya orang berjuang hidup dalam keterbatasan yang luar biasa.
Kebenaran yang sering digaungkan, hanyalah seperti melakukan perebutan makna secara paksa, mengacuhkan norma, bersaing mengatasnama jargon semata, sebuah anomali terstrukural yang membungkam masyarakat jelata.
Penggagas teori dekonstruksi, Jacques Derrida, konsep dialektika sosial haruslah diaktualisasikan secara kontinyu agar menjadi pengertian yang baik dan gampang diresap.
Bagi Beliau, kemajemukan realita pastinya memberikan perbedaan, dari sini timbul kontribusi makna, orang dulu menyoalkan kenapa ada putih, kerana ada hitam, kenapa ada kaya dalam realitas, karena ada kemiskinan, maka semakin jelas maknanya.
Tak ayal hal itu mempengaruhi gaya hidup manusia secara terstruktur saat itu untuk saling beroposisi, pemaknaan konse strkutural itu menyebabkan kesenjangan sosial yang tak stabil.
Diperlukan penelusuran jejak sampai ditemukan makna yang tak terungkap, Derrida menyebutnya absence (ketakhadiran), cara menampilkan makna lain.
Sehingga orang hitam juga bisa cantik, Tuhan akan menghukum si kaya yang zalim, semua manusia pasti punya rasa bersalah.
Jadi semua ini serba paradoks, tidak ada yang benar-benar abadi dalam makna, dengan kata lain logika dekonstruksi mengajarkan moral dan etika. Bilamana hal ini diaktualisasikan, bukan tidak mungkin akan mengakuisisi nurani dan rasa.
Meskipun ada titik beda, pasti juga ada rasa makna lain yang bisa melengkapi dalam realita.
Istilah sufisme, al-syai’un yu’rofu illa bi didh-dhihi, setiap ucapan atau fenomena, pasti ada suatu makna lain dalam memberikan makna yang tak terungkap.
Singkatnya, dari situlah nilai etika kesopanan bekerja, ketika moralitas dikombinasikan dengan rasa, pasti ritme kesalehan masyarakat terus berirama.
Penulis: Haris Diar Rizki. (Pendakwah, Pengajar & Pemerhati Sosial)
Editor: Baldan
- Mengenal Imam Abu al-Hasan al-‘Ijli Pengarang Kitab al-Tsiqat - 09/03/2024
- Menteri Agama RI Luncurkan PMB PTKIN 2024 - 20/01/2024
- Gagasan tentang Pluralisme Menurut Para Sufi, Filsuf dan Faqih - 18/01/2024