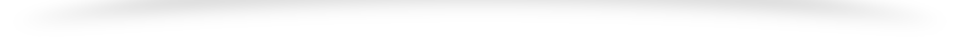Pecihitam.org – Hadits Shahih Al-Bukhari No. 659-660 – Kitab Adzan ini, Imam Bukhari memulai hadis ini dengan judul “Apabila Imam Memperpanjang (Shalat) Sementara Seseorang Memiliki Kepentingan, Lalu la Keluar dan Shalat” hadis dari Jabir bin Abdullah ini menceritakan bahwa Muadz bin Jabal biasa shalat bersama Nabi saw dan setelah itu dia pulang untuk mengimami kaumnya. Keterangan hadist dikutip dan diterjemahkan dari Kitab Fathul Bari Jilid 4 Kitab Adzan. Halaman 333-350.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ
Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami [Muslim bin Ibrahim] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu’bah] dari [‘Amru] dari [Jabir bin ‘Abdullah], bahwa Mu’adz bin Jabal pernah shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian dia kembali pulang dan mengimami shalat kaumnya.”
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ عَمْرٌو لَا أَحْفَظُهُمَا
Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ghundar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu’bah] dari [‘Amru] berkata, Aku mendengar [Jabir bin ‘Abdullah] berkata, “Mu’adz bin Jabal pernah shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dia lalu kembali pulang dan mengimami kaumnya shalat ‘Isya dengan membaca surah Al Baqarah. Kemudian ada seorang laki-laki keluar dan pergi, Mu’adz seakan menyebut orang tersebut dengan keburukan. Kejadian ini kemudian sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda: “Apa engkau akan membuat fitnah? Apa engkau akan membuat fitnah? Apa engkau akan membuat membuat fitnah?” Beliau ucapkan hingga tiga kali. Atau kata beliau: “Apakah kamu menjadi pembuat fitnah? Apakah kamu menjadi pembuat fitnah? Apakah kamu menjadi pembuat fitnah?” Lalu beliau memerintahkannya (Mu’adz) untuk membaca dua surah saja dari pertengahan Al Mufashshal.” Amru berkata, ‘Namun aku tidak hafal kedua surat tersebut.”
Keterangan Hadis: (Bab apabila imam memperpanjang (salat) sementara seseorang -yakni makmum- memiliki kepentingan lalu ia keluar dan shalat). Judul bab ini merupakan kebalikan judul sebelumnya, karena pada bab sebelumnya menjelaskan tentang bolehnya bermakmum kepada orang yang tidak berniat menjadi imam, sementara pada bab ini menjelaskan bolehnya makmum memutuskan shalat dengan imam.
Adapun perkataan Imam Bukhari pada judul bab, “Lalu ia keluar”, kemungkinan yang dimaksud adalah keluar dari keterikatan dengan imam, atau keluar dari keterikatan dengan shalat, atau keluar dari masjid. Ibnu Rasyid berkata, “Maksudnya secara lahiriah bahwa orang itu keluar dari masjid lalu shalat di rumahnya. Inilah yang diindikasikan oleh perkataannya, فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ (Maka laki-laki itu berbalik).” Ibnu Rasyid berkata pula, “Seakan-akan yang menyebabkan orang itu shalat di rumahnya adalah sabda beliau SAW ketika melihat seseorang yang sedang shalat, ‘Apakah dua shalat dilakukan bersamaan ‘.”[1]
Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa kenyataannya tidaklah demikian, karena sesungguhnya dalam riwayat An-Nasa’i disebutkan, (Maka laki-laki tersebut berbalik lalu shalat di pojok masjid). Riwayat ini masih mengandung kemungkinan bahwa laki-laki itu hanya memutuskan keterkaitan dengan imam, atau keluar dari shalat sekaligus. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, (Maka laki-laki itu menyimpang dari imam lalu salam kemudian shalat sendirian).
Ketahuilah, bahwa hadits ini telah diriwayatkan dari Jabir oleh Amr bin Dinar, Muharib bin Datstsar, Abu Az-Zubair dan Ubaidillah bin Miqsam. Riwayat Amr yang dikutip oleh Imam Bukhari di tempat ini berasal dari Syu’bah, sementara riwayat Amr yang beliau kutip dalam pembahasan tentang “Al Adab” berasal dari Sulaim bin Hayyan. Riwayat Amr yang dikutip oleh Imam Muslim berasal dari Ibnu Uyainah. Adapun riwayat Muharib akan disebutkan setelah dua bab kemudian, dan riwayat ini dikutip pula oleh An-Nasa ‘i diiringi oleh riwayat Abu Shalih. Riwayat Az-Zubair dinukil oleh Imam Muslim, sedangkan riwayat Ubaidillah dikutip oleh Ibnu Khuzaimah. Hadits ini memiliki jalur-jalur periwayatan yang lain, aku akan menyebutkan apa-apa yang dibutuhkan seraya menisbatkan kepada sumbernya. Hanya saja aku menyebutkan hal ini lebih dahulu untuk memudahkan pemahaman.
يُصَلِّي مَعَ اَلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (shalat bersama Nabi SAW) Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya melalui Manshur dari Amr, عِشَاء الْآخِرَة (Shalat Isya’ yang akhir), hal ini memberi indikasi bahwa shalat yang senantiasa dilakukan oleh Mu’adz sebanyak dua kali adalah shalat Isya’.
ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمه (kemudian beliau pulang dan mengimami kaumnya). Dalam riwayat Manshur disebutkan, فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاة (Maka beliau mengimami mereka pada shalat tersebut). Sementara dalam riwayat Imam Bukhari yang terdapat dalam pembahasan tentang “Al Adab” (Tata Krama) disebutkan, فَيُصَلِّي بِهِمْ الصَّلَاة (Beliau melakukan shalat itu dengan mengimami mereka), yakni shalat yang disebutkan sebelumnya. Riwayat-riwayat ini menjadi bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa shalat yang dilakukan oleh Mu’adz bersama Nabi SAW bukan shalat yang dia lakukan saat mengimami kaumnya.
Kemudian dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمه فَأَمَّهُمْ (Maka suatu malam beliau shalat Isya’ bersama Nabi SAW, kemudian beliau mendatangi kaumnya lalu shalat mengimami mereka). Dalam riwayat Al Humaidi dari Ibnu Uyainah disebutkan, ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَنِي سَلِمَةَ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ (Kemudian dia kembali ke Bani Salimah lalu melakukan shalat dengan mereka). Tapi riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat sebelumnya, sebab kaumnya Mu’adz adalah Bani Salimah. Dalam riwayat Asy-Syafi’i dari Mu’adz disebutkan, ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيهَا بِقَوْمِهِ فِي بَنِي سَلِمَة (Kemudian beliau balik dan melakukan shalat itu dengan mengimami kaumnya di Bani Salimah). Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad, ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا (Kemudian beliau batik lalu mengimami kami).
فَصَلَّى الْعِشَاءَ (lalu shalat Isya’) Demikian yang disebutkan dalam mayoritas riwayat. Namun dalam riwayat Abu Awanah dan AthThahawi melalui jalur Muharib disebutkan, صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْمَغْرِب (Beliau shalat Maghrib dengan mengimami sahabat-sahabatnya). Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Abu Zubair. Apabila dipahami, peristiwa ini terjadi lebih dari sekali; atau yang dimaksud dengan “Maghrib” adalah shalat Isya’ dalam konteks majaz (kiasan), maka kedua versi riwayat itu dapat dipadukan. Adapun apabila tidak dipahami demikian, maka versi yang terdapat dalam Shahih Bukhari lebih patut untuk dijadikan pedoman.
فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ (lalu beliau membaca Al Baqarah). Hal ini dijadikan dalil untuk membantah mereka yang berpendapat makruh mengatakan “Al Baqarah”, karena yang seharusnya dikatakan adalah surah Al Baqarah. Akan tetapi dalam riwayat Al Ismaili dari Al Hasan bin Sufyan dari Muhammad bin Basysyar (guru Imam Bukhari pada riwayat ini) disebutkan, فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ (Lalu beliau membaca surah Al Baqarah), dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan lafazh yang serupa dengannya. Sementara dalam riwayat Imam Bukhari dalam pembahasan tentang “Al Adab” (tata krama) disebutkan, فَقَرَأَ بِهِمْ الْبَقَرَة (Maka beliau mengimami mereka dengan membaca Al Baqarah). Secara lahiriah, penghapusan atau penulisan kata “surah” bersumber dari perawi hadits.
Maksud “membaca surah Al Baqarah” adalah memulai membacanya. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Imam Muslim dengan lafazh, فَافْتَتَحَ سُورَة الْبَقَرَةِ (Maka beliau memulai membaca surah Al Baqarah). Sementara dalam riwayat Muharib disebutkan, فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ النِّسَاءِ (Maka beliau membaca surah Al Baqarah atau An-Nisaa’), yakni disertai keraguan. Kemudian dalam riwayat As-Sarraj dari Mis’ar dari Muharib disebutkan, فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ (Maka beliau membaca surah Al Baqarah dan surah An-Nisaa’). Demikian aku melihat manuskrip Az-Zaki Al Barzali. Bila hal ini akurat, maka kemungkinan Mu’adz membaca surah Al Baqarah pada rakaat pertama dan surah An-nisaa’ pada rakaat kedua.
Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Buraidah disebutkan dengan sanad yang akurat, فَقَرَأَ اِقْتَرَبَتْ اَلسَّاعَة (Maka beliau membaca surah iqtarabat as-saa’ah). Tapi riwayat ini menyalahi yang umum (syadz) kecuali bila dipahami bahwa peristiwa tersebut terjadi lebih dari satu kali.
Dalam riwayat-riwayat yang disebutkan tidak tercantum keterangan nama laki-laki yang dimaksud, tetapi Abu Daud AthThayalisi meriwayatkan dalam Musnad-nya serta Al Bazzar dari Thalib bin Habib, dari Abdurrahman bin Jabir dari bapaknya, dia berkata مَرَّ حَزْم بْن أُبَيِّ بْن كَعْب بِمُعَاذ بْن جَبَل وَهُوَ يُصَلِّي بِقَوْمِهِ صَلَاة الْعَتَمَة فَافْتَتَحَ بِسُورَةٍ طَوِيلَةٍ وَمَعَ حَزْمٍ نَاضِح لَهُ (Hazm bin Ubay bin Ka’ab melewati Mu’adz bin Jabal, sementara beliau sedang shalat mengimami kaumnya shalat Isya’. Maka beliau membaca surah yang sangat panjang, sementara Hazm membawa serta unta pengangkut air untuk menyiram tanaman) (Al Hadits).
Al Bazzar berkata, “Kami tidak mengenal seorang pun yang menyebutkan nama laki-laki tersebut dalam riwayat Jabir kecuali Ibnu Jabir.” Abu Daud meriwayatkan dalam kitab As-Sunan melalui jalur lain dari Thalib, lalu dijadikannya sebagai riwayat Ibnu Jabir dari Hazm sebagai pelaku kisah ini. Namun Ibnu Jabir tidak bertemu dengan Hazm. Di samping itu disebutkan dalam riwayatnya,”Shalat Maghrib.” Hal ini sama dengan perbedaan yang dinukil dalam riwayat Al Milharib.
Ibnu Lahi’ah meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Jabir, dengan menyebutkan nama Hazim, tetapi sepertinya perubahan ini dilakukannya sendiri. Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Syahin melalui sanadnya Kemudian Imam Ahmad, An-Nasa’i, Abu Ya’la, serta Ibnu As-Sakan meriwayatkan melalui sanad shahih dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, dia berkata, كَانَ مُعَاذ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَدَخَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ (Suatu ketika Mu’adz sedang shalat mengimami kaumnya, lalu Haram masuk sementara ia hendak menyiram pohon kurmanya).
Sebagian ulama menduga bahwa yang dimaksud adalah Haram bin Milhan, paman Anas. Pendapat inilah yang ditegaskan Al Khathib dalam kitab Al Mubhamat, akan tetapi saya tidak menemukan dalam riwayat penyebutan nasab laki-laki tersebut. Ada pula kemungkinan ini hanyalah perubahan dari kata “Hazm”, sehingga tampaklah keserasian semua riwayat yang ada. Nampaknya, ini juga yang menjadi kecenderungan sikap Ibnu Abdul Barr, dimana dia menyebutkan dalam deretan para sahabat seorang yang bernama Haram bin Ubay bin Ka’ab, seraya menyebutkan kisah ini sebagai kisah beliau. Kemudian Ibnu Abdul Barr menyebutkan bahwa riwayat yang mencantumkan nama laki-laki tersebut adalah riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas. Tetapi penyebutan nama bapaknya tidak saya temukan dalam riwayat Abdul Aziz.
Sehubungan dengan nama laki-laki ini telah dinukil pendapat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mu’adz bin Rifa’ah dari seorang laki-laki Bani Salimah yang bernama Sulaim, bahwasanya ia mendatangi Nabi SAW dan berkata, يَا نَبِيّ اللَّهِ إِنَّا نَظَلُّ فِي أَعْمَالِنَا فَنَأْتِي حِينَ نُمْسِي فَنُصَلِّي ، فَيَأْتِي مُعَاذ بْن جَبَل فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَنَأْتِيه فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا (Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami tetap berada dalam pekerjaan kami hingga sore hari dan kami pun shalat. Lalu Mu’adz bin Jabal datang. Kemudian ia menyeru untuk shalat dan kami pun mendatanginya, namun dia memperpanjang shalat atas kami). (Al Hadits).
Dalam hadits ini disebutkan pula bahwa laki-laki yang dimaksud mati syahid dalam perang Uhud. Dengan demikian, riwayat tersebut tergolong mursal, karena Mu’adz bin Rifa’ah tidak hidup satu masa dengan laki-laki tersebut.
Imam Thahawi dan Thabrani meriwayatkan melalui jalur ini dari Mu’adz bin Rifa’ah, bahwa seorang laki-laki dari Bani Salimah…dan seterusnya. Lalu beliau menyebutkan hadits tadi dengan jalur mursal. Al Bazzar juga meriwayatkan melalui jalur Iain dari Jabir seraya menyebutkan nama orang tersebut, yaitu Sulaim. Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Hazm melalui jalur yang sama disebutkan bahwa nama orang tersebut adalah Salm. Namun sepertinya ini merupakan kesalahan penukilan, wallahu a’lam.
Sebagian ulama menyatukan riwayat-riwayat yang saling berbeda dengan menyatakan bahwa hal itu menceritakan dua kisah yang berbeda. Pendapat ini didukung oleh adanya perbedaan versi dalam menentukan shalat yang dilakukan saat itu; apakah ia shalat Isya’ atau shalat Maghrib. Demikian juga dengan perbedaan surah yang dibaca; apakah surah Al Baqarah atau surah “iqtarabat assaa’ah’ .” Di tambah lagi dengan perbedaan udzur (alasan) laki-laki tersebut; apakah karena shalat yang panjang, atau karena ia baru selesai bekerja sehingga sangat lelah, atau karena saat itu ia hendak menyiram kebun, atau karena ia mengkhawatirkan air yang ada di kebunnya seperti pada hadits Buraidah. Akan tetapi cara kompromi ini dianggap musykil, karena tidak mungkin kita berprasangka bahwa Mu’adz bin Jabal ketika diperintahkan Nabi SAW untuk tidak memperpanjang shalat, dia kembali memperpanjang shalatnya. Hanya saja kemusykilan ini dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa kemungkinan pada pertama kali Mu’adz membaca surah Al Baqarah. Ketika apa yang dilakukannya itu dilarang Nabi SAW, maka beliau membaca surah “iqtarabat as-saa’ah”, dimana surah ini termasuk surah yang panjang dibanding surah-surah yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca seperti yang akan dijelaskan.
Ada pula kemungkinan larangan yang pertama disebabkan adanya kekhawatiran apabila perbuatan tersebut akan menjauhkan orang-orang yang barn memeluk Islam dari agama Islam. Kemudian setelah mereka merasa tentram dalam agama ini, maka Mu’adz mengira bahwa faktor yang melandasi larangan tersebut tidak ada, sehingga beliau membaca surah “iqtarabat as-saa’ah”, sebab dia mendengar Nabi SAW membaca surah Ath-Thuur pada shalat Maghrib. Namun ketika Mu’adz membaca surah tersebut, di antara makmumnya ada yang memiliki kepentingan mendesak.
Sementara itu Imam An-Nawawi menyatukan riwayat-riwayat tersebut dengan cara lain, dia menyatakan bahwa kemungkinan Mu’adz membaca surah Al Baqarah pada rakaat pertama, maka saat itu ada seorang laki-laki yang berbalik. Lalu pada rakaat kedua beliau membaca surah “iqtarabat As-Sa’adah” dan ada pula seorang laki-laki lain yang berbalik.
Dalam riwayat Abu Zubair yang dinukil oleh Imam Muslim disebutkan, فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَّا (Maka berangkatlah seorang laki-laki di antara kami). Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang dimaksud berasal dari Bani Salimah, dan juga mendukung pandangan mereka yang mengatakan bahwa nama laki-laki tersebut adalah Sulaim, wallahu a’lam.
فَانْصَرَفَ اَلرَّجُلُ (maka seorang laki-laki berbalik [pulang]). Huruf alif dan lam pada kata اَلرَّجُلُ berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang telah ada pada pikiran pendengar (Al Ahd Adz-Dzilmi), akan tetapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah jenis. Seakan-akan dikatakan, “Salah seorang di antara laki-laki.” Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, (Maka seorang laki-laki berdiri lalu berbalik). Sementara dalam riwayat Sulaim bin Rayyan, فَتَجَوَّزَ رَجُل فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً (Maka seorang laki-laki meringkas dengan melakukan shalat yang ringan). Dalam riwayat Ibnu Uyainah yang disebutkan oleh Imam Muslim, فَانْحَرَفَ رَجُل فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ (Maka seorang laki-laki berbalik seraya memberi salam lalu shalat seorang diri). Hal ini sangat jelas menyatakan bahwa orang itu memutuskan shalatnya. Akan tetapi Al Baihaqi menyebutkan bahwa lafazh فَسَلَّمَ (seraya memberi salam) hanya dinukil oleh Muhammad bin Abbll’i (guru Imam Muslim) sendiri dari Ibnu Uyainah. Demikian pula dengan murid-murid gurunya Amr bin Dinar, serta murid-murid Jabir, semuanya tidak menyebutkan perihal salam. Sepertinya dia memahami lafazh ini menunjukkan bahwa laki-laki tersebut memutuskan shalatnya, sebab salam merupakan pintu keluar dari shalat. Sementara riwayat-riwayat yang lain menyatakan bahwa orang itu hanya memutuskan keterikatan dengan imam tanpa keluar dari shalat, bahkan ia meneruskan shalatnya sendirian.
Ar-Rafi’i berkata dalam kitab Syarh Al Musnad ketika membahas riwayat Asy-Syafi’i dari Ibnu Uyainah sehubungan dengan hadits ini, فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ فَصَلَّى وَحْدَهُ (Maka salah seorang laki-laki di belakangnya berpindah lalu shalat sendirian). Dari segi lafazh riwayat ini mengandung kemungkinan bahwa orang itu memutuskan shalat, kemudian berpindah dari tempat shalatnya lalu memulai shalat sendiri. Tetapi kemungkinan ini tidak dapat diterima dari sisi syara’, sebab shalat fardhu tidak boleh diputus setelah seseorang masuk memulai shalat.”
Atas dasar ini maka ulama madzhab Syafi’i menjadikannya sebagai dalil bahwa makmum boleh memutuskan keterikatan dengan imam lalu menyempurnakan shalatnya sendirian. Imam An-Nawawi membantah hal itu dengan mengatakan bahwa hadits tersebut tidak berindikasi demikian, karena tidak ada keterangan bahwa laki-laki itu memutuskan keterikatan dengan imam dan melanjutkan shalatnya seorang diri. Bahkan dalam riwayat yang menyebutkan orang itu memberi salam, terdapat petunjuk bahwa ia juga memutuskan shalat yang dilakukannya bersama imam kemudian memulainya dari awal. Maka, hadits itu menjadi dalil bolehnya memutuskan shalat atau membatalkannya karena suatu alasan (udzur).
فَكَأَنَّ مُعَاذًا يَنَالُ مِنْهُ (maka Mu’adz mencelanya) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ (Maka seakan-akan Mu’adz mencelanya). Yakni memberi penilaian negatifterhadap orang itu. Hal ini diterangkan lebih jelas dalam riwayat Sulaim bin Rayyan, dengan lafazh, فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِق (Hal itu sampai kepada Mu’adz, maka beliau berkata, “Sesungguhnya ia seorang munafik.”). Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Abu Zubair. Sementara dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, فَقَالُوا لَهُ : أَنَافَقْت يَا فُلَان ؟ قَالَ : لَا ، وَاَللَّه لَآتِيَنَّ رَسُول اَللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلَأُخْبِرَنَّهُ (Mereka berkata kepadanya, “Apakah engkau telah menjadi orang yang munafik wahai falan?” Laki-laki itu berkata, “Tidak, demi Allah aku akan mendatangi Rasulullah SAW, dan sungguh aku akan memberitahukan kepadanya.”). Sepertinya yang pertama mengucapkan hal itu adalah Mu’adz, kemudian sahabat-sahabatnya menyampaikannya kepada laki-laki tersebut.
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (maka hal itu sampai kepada Nabi SAW). Ibnu Uyainah menjelaskan dalam riwayatnya bahwa laki-laki tersebut yang datang menemui Nabi SAW dan mengadukan Mu’adz, demikian pula dalam riwayat Muharib dan Abu Zubair. Sedangkan dalam riwayat An-Nasa’i disebutkan, فَقَالَ مُعَاذ : لَئِنْ أَصْبَحْت لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى اَلَّذِي صَنَعْت ؟ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّهِ عَمِلْت عَلَى نَاضِحٍ لِي (Maka Mu’adz berkata,”Apabila Subuh telah tiba, sungguh aku akan menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW.” Lalu Mu’adz menceritakannya kepada beliau SAW, maka Nabi SAW mengirim utusan kepada laki-laki tersebut, dan beliau SAW bertanya, “Apakah yang menyebabkanmu melakukan hal itu?” Laki-laki tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, aku bekerja di atas hewan penyiram milikku…”) lalu disebutkan hadits selengkapnya. Seakan Mu’adz lebih dahulu mengadukan perkara itu; dan ketika laki-laki tersebut datang, ia pun mengadukan Mu’adz.
فَقَالَ فَتَّان (maka beliau bersabda, “Orang yang banyak berbuat fitnah…’). Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, أَفَتَّان أَنْتَ (Apakah engkau akan menjadi orang yang banyak berbuat fitnah). Kemudian Al Muharib memberi tambahan lafazh, ثَلَاثًا (Tiga kali).
أَوْ قَالَ فَاتِنًا (atau beliau mengatakan, “Pembuat fitnah”) Keraguan dalam kalimat ini berasal dari perawi. Dalam riwayat Abu Zubair dikatakan, أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَاتِنًا (Apakah engkau hendak menjadi pembuat fitnah). Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Mu’adz bin Rifa’ah disebutkan, يَا مُعَاذ لَا تَكُنْ فَاتِنًا (Wahai Mu’adz! janganlah engkau menjadi pembuat fitnah). Kemudian dalam hadits Anas diberi tambahan لَا تُطَوِّلْ بِهِمْ (Janganlah engkau memperpanjang (shalat) atas mereka).
Adapun makna fitnah dalam hadits ini, yaitu bahwa memperpanjang shalat menyebabkan orang-orang keluar dari shalat dan menjadikan mereka tidak menyukai shalat jamaah. Al Baihaqi meriwayatkan dalam pembahasan tentang “Asy-Syu’ab” dengan sanad yang shahih dari Umar, dia berkata, لَا تُبَغِّضُوا إِلَى اَللَّهِ عِبَادَهُ يَكُونُ أَحَدكُمْ إِمَامًا فَيُطَوِّلُ عَلَى الْقَوْمِ الصَّلَاة حَتَّى يُبَغِّضَ إِلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ (Janganlah kalian menjadikan hamba-hamba Allah SWT menjadi benci kepada-Nya, yaitu salah seorang di antara kalian menjadi imam lalu memperpanjang shalat, hingga menimbulkan rasa benci pada mereka (makmum) terhadap apa yang mereka lakukan).
Ad-Dawudi berkata, ”Tidak tertutup kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan lafazh فَتَّان adalah ‘penyiksa’ yakni ia menyiksa para makmum dengan shalatnya yang lama. Makna seperti ini juga terdapat dalam firman Allah SWT surah Al Buruuj ayat 10, إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ (Sesungguhnya orang-orang yang berbuat fitnah terhadap orang-orang mukmin) dikatakan bahwa maknanya adalah menyiksa mereka.”
وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّل ، قَالَ عَمْرو ) أَيْ : اِبْن دِينَار ( لَا أَحْفَظُهُمَا (dan beliau memerintahkan untuk membaca dua surah sedang di antara surah-surah mufashshal. Amr -yakni Ibnu Dinar- berkata, “Aku tidak ingat keduanya”). Sepertinya Amr bin Dinar mengatakan hal ini ketika sedang meriwayatkan hadits tersebut kepada Syu’bah karena dalam riwayat Sulaim bin Rayyan dari Amr dikatakan, اِقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحْ اِسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا (Bacalah wasy-syamsi wa dhuhaaha dan sabbihisma rabbikal a ‘laa atau yang sepertinya).
Kemudian dia berkata dalam riwayat Ibnu Uyainah yang dinukil oleh Imam Muslim, اِقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا (Bacalah yang ini…dan bacalah yang ini…). Ibnu Uyainah berkata, “Aku berkata kepada Amr, sesungguhnya Abu Zubair telah menceritakan kepada kami bahwa beliau SAW bersabda, اِقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْل إِذَا يَغْشَى وَبِسَبِّحْ اِسْم رَبِّك الْأَعْلَى (Bacalah wasy-syamsi wa dhuhaaha, wallaili idzaa yaghsyaa dan sabbihisma rabbikal a’laa).” Amr berkata, “Sama seperti ini.”
Hal itu dinyatakan secara tegas oleh Muharib dalam riwayatnya dari Jabir. Kemudian dalam riwayat Al-Laits dari Abu Zubair yang dikutip oleh Imam Muslim dinyatakan, di samping tiga surah tadi disebutkan pula surah iqra bismirabbika alladzi khalaq (Al ‘Alaq). Ibnu Juraij memberi tambahan “Wadhdhuhaa” dalam riwayatnya dari Abu Zubair, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq. Dalam riwayat Al Humaidi dari lbnu Uyainah, disebutkan di samping tiga surah di atas disebutkan pula “Wassamaa ‘i dzaatil buruuf’ dan “Wassamaa ‘i wath-thaariq”. Adapun sehubungan dengan surah-surah muf ashshal telah dinukil sejumlah pendapat seperti yang akan diterangkan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur’an, dan yang paling benar di antara pendapat-pendapat itu adalah dimulai dari surah ‘Qaaf hingga surah terakhir dalam Al Qur’an.
أَوْسَط (sedang). Ada kemungkinan yang dimaksud adalah “yang pertengahan”, sementara contoh surah yang disebutkan merupakan surah-surah pendek. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah “yang serasi” yakni yang sesuai dengan keadaan di antara surah-surah) mufashshal.
Hadits ini telah dijadikan dalil sahnya seorang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunah, atas dasar bahwa niat Mu’adz pada shalat yang pertama (yakni yang dilakukannya bersama Nabi SAW) adalah niat shalat fardhu, sementara pada kesempatan yang kedua (yakni saat mengimami kaumnya) adalah niat shalat sunah. Hal ini didukung oleh riwayat Abdurrazzaq, Asy-Syafi ‘i, Ath-Thahawi, Ad-Daruquthni serta selain mereka, melalui jalur periwayatan Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar, dari Jabir sehubungan dengan hadits di bab ini yang mana diberi tambahan, هِيَ لَهُ تَطَوُّع وَلَهُمْ فَرِيضَة (Shalat itu merupakan shalat sunah baginya dan shalat fardhu bagi para makmum). Hadits ini adalah hadits shahih, para periwayatnya adalah perawi dalam Shahih Bukhari. lbnu Juraij telah menyatakan secara tegas -dalam riwayat Abdurrazzaq- bahwa ia mendengar riwayat itu langsung dari gurunya. Dengan demikian, hilanglah dugaan bahwa Ibnu Juraij melakukan tadlis (penyamaran) dalam riwayat ini. Maka perkataan Ibnu Al Jauzi bahwa hadits ini tidak shahih, tidak dapat diterima. Sementara perkataan Ath-Thahawi bahwa Ibnu Uyainah telah menukil hadits ini melalui Amr dengan lafazh yang lebih lengkap, tanpa menyebutkan keterangan tambahan tadi, juga tidak mempengaruhi keorisinilan hadits tersebut, karena Ibnu Juraij lebih senior daripada Ibnu Uyainah dan ia lebih dahulu belajar kepada Amr dibanding Ibnu Uyainah. Seandainya tidak demikian, maka tambahan tersebut berasal dari orang tsiqah (terpercaya) dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih tsiqah darinya atau lebih banyak jumlahnya, sehingga tidak perlu tawaqquf (tidak menentukan pendapat) dalam menyatakan keshahihan-nya.
Adapun penolakan Ath-Thahawi bahwa kemungkinan lafazh tersebut berasal dari perawi (mudraj), maka dapat dikatakan, “Kaidah dasar mengatakan bahwa lafazh dalam suatu hadits tidak dapat dikatakan sebagai lafazh perawi (mudraj) kecuali ada bukti yang kuat.” Kalimat apa saja yang digabungkan ke dalam hadits harus dinyatakan sebagai bagian hadits, khususnya apabila dinukil melalui dua jalur periwayatan yang berbeda sebagaimana riwayat di tempat ini, karena Imam Syafi’i telah menukil hadits tersebut melalui jalur lain dari Jabir disertai riwayat pendukung dari Amr bin Dinar, dari Jabir.
Sedangkan perkataan Ath-Thahawi bahwa yang demikian itu hanyalah dugaan dari Jabir juga tidak dapat diterima, sebab Jabir termasuk salah seorang yang shalat bersama Mu’adz, sehingga hams dipahami bahwa ia mendengar hal itu dari Mu’adz. Kita tidak boleh berprasangka bahwa Jabir menceritakan sesuatu dari seseorang tanpa menyaksikannya sendiri, kecuali apabila orang itu memberitahukan sesuatu itu kepadanya.
Sikap para ulama dalam madzhab kami yang mendukung keterangan tambahan dalam riwayat tersebut dengan dalil sabda beliau SAW, “Apabila qamat untuk shalat telah dilakukan, maka tidak ada shalat kecuali shalat fardhu”, bukanlah dalil yang kuat. Sebab intinya hanyalah larangan untuk melakukan shalat selain shalat yang karenanya qamat dilakukan, tanpa ada hubungannya dengan urusan niat fardhu atau sunah. Apabila hadits tersebut mengharuskan niat shalat fardhu, niscaya Mu’adz dilarang untuk shalat mengimami kaumnya (shalat fardhu). Demikian halnya dengan pendapat sebagian ulama dalam madzhab kami yang tidak membolehkan untuk menduga bahwa Mu’adz meninggalkan keutamaan shalat fardhu di belakang imam paling utama serta di masjid yang sangat utama. Pernyataan ini meski mengandung unsur yang mendukung pendapat mereka (bolehnya bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat sunah), namun pendapat lain yang menyalahinya bisa saja mengatakan, “Jika yang demikian itu berdasarkan perintah Nabi SAW, maka tidak ada halangan bagi Mu’adz untuk mendapatkan keutamaan karena bermakmum kepada beliau SAW.”
Pendapat yang serupa adalah pendapat Al Khathtabi, dia mengatakan bahwa lafazh Isya’ dalam kalimat (dia shalat Isya’ bersama Nabi SAW) pada hakikatnya adalah shalat Isya’ (fardhu), maka tidak boleh dikatakan bahwa Mu’adz meniatkan shalat tersebut sebagai shalat sunah. Karena, bagi orang yang tidak sependapat dengannya akan mengatakan, “Apa yang dikatakannya tidak menafikan bahwa Mu’adz meniatkan shalat sunah bersama Nabi SAW”. Adapun perkataan Ibnu Hazm, “Sesungguhnya pendapat yang tidak membolehkan seseorang yang melaksanakan shalat fardhu bermakmum kepada imam yang shalat sunah, mereka tidak memperbolehkan juga bagi orang yang sedang shalat fardhu untuk meniatkannya sebagai shalat sunah apabila qamat telah dilakukan. Lain bagaimana mereka mengatakan Mu’adz melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mereka sendiri?” Apabila pernyataan ini benar, maka akan menjadi kritik yang sangat tajam. Namun jawaban yang paling selamat adalah berpegang dengan keterangan tambahan yang telah disebutkan.
Adapun perkataan Ath-Thahawi yang menyatakan bahwa perbuatan Mu’adz tersebut tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak berdasarkan perintah Nabi SAW dan taqrir (persetujuan) beliau SAW, maka untuk menjawabnya dapat dikatakan bahwa para ulama tidak berselisih, jika pendapat seorang sahabat tidak diselisihi oleh sahabat lainnya, maka pendapat tersebut dapat dijadikan hujjah. Demikian juga halnya dengan masalah ini, karena orang-orang yang diimami oleh Mu’adz saat itu adalah para sahabat Nabi SAW. Di antara mereka terdapat tiga puluh orang yang mengikuti perjanjian Aqabah dan empat puluh orang yang mengikuti perang Badar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm. Lain Ibnu Hazm menegaskan bahwa tidak dinukil dari seorang sahabat perkataan yang melarang perbuatan demikian, bahkan pendapat yang membolehkannya telah dinukil dari Umar, Ibnu Umar, Abu Darda’, Anas dan selain mereka.
Ath-Thahawi berpendapat, “Apabila semua argumentasi di atas dapat diterima, tetap tidak dapat dijadikan hujjah, karena ada kemungkinan perbuatan itu dilakukan ketika dibolehkan melaksanakan shalat fardhu dua kali.” Kemudian hukum ini dihapus (mansukh). Ibnu Daqiq Al Id menanggapi pendapat Ath-thahawi dengan mengatakan bahwa pernyataaan itu berkonsekuensi menetapkan penghapusan suatu hukum berdasarkan kemungkinan, padahal yang demikian tidak diperbolehkan. Untuk itu, yang menjadi keharusan adalah mengemukakan dalil atas dakwaan adanya pengulangan shalat fardhu. Demikian komentar Ibnu Daqiq.
Sepertinya Ibnu Daqiq Al Id tidak sempat meneliti kitab Ath Thabawi, karena dalam kitab itu beliau telah menyebutkan dalil mengenai persoalan tadi, yaitu hadits Ibnu Umar yang dinisbatkannya kepada Nabi SAW, (Janganlah kalian melakukan satu shalat dua kali dalam satu hari). Dari jalur lain dengan sanad mursal disebutkan, (Sesungguhnya penduduk Aliyah biasa shalat di rumah-rumah mereka, kemudian mereka shalat bersama Nabi SAW: Lalu hal ini sampai kepada Nabi SAW dan beliau pun melarangnya). Meskipun riwayat ini shahih, namun untuk dijadikan dalil yang mendukung apa yang dikatakannya nampaknya kurang tepat, karena ada kemungkinan larangan melakukan shalat dua kali tersebut adalah apabila keduanya diniatkan sebagai shalat fardhu. Kemungkinan ini yang ditegaskan oleh Al Baihaqi untuk menyatukan dua hadits yang nampak bertentangan, Bahkan apabila seseorang mengatakan bahwa larangan tersebut telah dihapus (mansukh) oleh hadits Mu’adz, maka perkataannya tidak jauh dari kebenaran. Dalam hal ini tidak boleh mengatakan bahwa kisah Mu’adz terjadi lebih dahulu, karena Mu’adz sendiri meninggal pada perang Uhud. Sedangkan perang Uhud terjadi pada akhir tahun ketiga setelah hijrah, sehingga tidak ada halangan bila larangan tersebut dikeluarkan pada tahun pertama dan penghapusannya terjadi pada tahun ketiga. Di samping itu, Nabi SAW telah bersabda kepada dua orang laki-laki yang tidak turut shalat bersama beliau SAW, (Apabila kalian berdua telah shalat di tempat tinggal kalian, kemudian mendatangi masjid jamaah maka shalatlah bersama mereka. karena shalat itu bagi kalian berdua adalah sebagai shalat sunah). Riwayat ini dinukil para penulis kitab Sunan dari hadits Yazid bin Al Aswad Al Amiri dan di-shahih-kan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Kejadian ini berlangsung pada haji Wada’ di masa-masa akhir kehidupan Rasulullah SAW.
Dalil yang membolehkan perbedaan niat antara makmum dan imam adalah perintah Nabi SAW kepada orang-orang yang hidup sesudahnya, di saat para penguasa telah mengakhirkan pelaksanaan shalat dari waktunya. Beliau bersabda, (Lakukanlah shalat itu di rumah-rumah kamu tepat pada waktunya, kemudian jadikanlah shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunah).
Sedangkan perkataan Ath-Thahawi bahwa Nabi SAW telah melarang Mu’adz melakukan perbuatan tersebut berdasarkan sabdanya dalam hadits Sulaim bin Harits, (Engkau boleh memilih antara shalat bersamaku atau engkau
meringankan shalat bersama mereka). Lalu dia mengklaim bahwa makna sabda tersebut adalah, “Engkau boleh memilih antara shalat bersamaku dan tidak shalat mengimami kaummu, atau engkau meringankan shalat bersama kaummu dan tidak shalat bersamaku”. Sungguh suatu pernyataan yang membutuhkan analisa lebih mendalam, sebab bagi yang tidak sependapat dengannya akan mengatakan bahwa makna sabda Nabi SAW tersebut adalah, “Engkau boleh memilih antara shalat bersamaku saja jika tidak mau meringankan shalat bersama kaummu, atau engkau shalat ringan bersama kaummu dan juga shalat bersamaku”. Makna terakhir ini lebih baik daripada apa yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi, karena keringanan dihadapkan dengan sikap meninggalkan keringanan pula, dan merupakan perkara yang diperselisihkan.
Adapun sikap sebagian ulama mendukung bahwa hukum yang terdapat dalam hadits Mu’adz telah dihapus (mansukh), dengan alasan bahwa shalat Khauf terjadi berkali-kali dengan tata cara pelaksanaan yang sangat berbeda dengan shalat dalam kondisi normal. Apabila orang yang shalat fardhu boleh bermakmum kepada imam yang melaksanakan shalat sunah, niscaya Nabi SAW akan shalat mengimami mereka berkali-kali,[2] dengan tata cara yang sama dengan shalat saat kondisi normal; dan karena Nabi SAW tidak melakukannya maka menunjukkan bahwa hal itu merupakan perbuatan yang dilarang.
Sebagai jawabannya, telah dinukil suatu berita yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Nabi SAW pernah shalat Khauf sebanyak dua kali mengimami para sahabatnya, sebagaimana dinukil oleh Abu Daud dari Abu Bakrah. Riwayat serupa dinukil pula oleh Imam Muslim dari hadits Jabir. Adapun sikap beliau SAW yang shalat mengimami mereka dengan tata cara yang berbeda dengan shalat dalam kondisi normal bertujuan untuk menjelaskan bahwa yang demikian itu diperbolehkan.
Sedangkan perkataan sebagian ulama bahwa perbuatan Mu’adz tersebut didukung oleh kondisi darurat karena kurangnya penghafal Al Qur’an saat itu, merupakan pernyataan yang tidak mempunyai landasan yang kuat, sebab batas minimal yang dibaca dalam shalat adalah yang dihafal mayoritas sahabat. Adapun selebihnya tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan hal yang terlarang dalam shalat menurut syara’.
Pelajaran yang dapat diambil:
1. Dianjurkan meringankan pelaksanaan shalat untuk menyesuaikan dengan kondisi mal(mum. Adapun pendapat mereka yang membolehkan imam untuk memperpanjang shalat apabila mengetahui bahwa makmum ridha dengan hal itu, cukup, rumit bila dihadapkan pada kenyataan dimana imam terkadang tidak mengetahui kondisi mal(mum yang datang setelah imam masuk dalam shalat, sebagaimana kejadian yang tercantum dalam hadits bab ini. Dengan demikian memperpanjang shalat adalah makruh hukumnya secara mutlak, kecuali bila jamaah tersebut adalah orang-orang terisolir. Mereka semua ridha bila shalat diperpanjang, dan shalat itu dilakukan di suatu tempat yang tidak akan ada seorang pun selain mereka yang turut bergabung.
2. Kebutuhan yang bersifat duniawi dapat menjadi alasan untuk memendekkan shalat.
3. Diperbolehkan melakukan satu shalat dua kali dalam sehari.[3]
4. Makmum boleh memutuskan keterkaitan dengan imam karena suatu udzur (alasan syar’i). Namun jika tanpa adanya suatu udzur, maka sebagian ulama berdalil dengan hadits ini untuk membolehkannya, namun pandangan mereka mendapat kritik dari ulama yang lain. Ibnu Al Manayyar berkata, “Apabila benar demikian maka perintah untuk para imam agar meringankan shalat kehilangan faidahnya.” Tapi perkataan ini masih perlu ditanggapi, karena faidah perintah meringankan shalat adalah untuk melestarikan shalat jamaah. Hal itu tidak menafikan bolehnya shalat sendirian. Serupa dengan ini sikap sebagian ulama yang menjadikan kisah di atas sebagai dalil akan wajibnya shalat jamaah.
5. Boleh melaksanakan shalat sendirian di masjid yang sedang dilaksanakan shalat jamaah di dalamnya karena suatu udzur. Dalam hadits ini terdapat bentuk pengingkaran yang sangat halus, karena pengingkaran tersebut diungkapkan dalam bentuk pertanyaan.
6. Hukuman peringatan diberikan sesuai dengan keadaan.
7. Hukuman peringatan boleh diwujudkan hanya dalam bentuk perkataan.
8. Boleh mengingkari perkara-perkara yang tidak disukai. Adapun diulanginya pengingkaran tersebut sampai tiga kali adalah untuk memberi penegasan. Dalam pembahasan tentang “ilmu” telah dijelaskan bahwa apabila berbicara beliau SAW mengulangi perkataannya hingga tiga kali.
9. Orang yang secara lahiriah telah melakukan kesalahan diperbolehkan untuk mengemukakan alasan.
10. Boleh mengecam orang yang telah melakukan kesalahan, meski ia memiliki alasan tersendiri, dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan kesalahan serupa. Lalu orang yang mengecam tersebut tidaklah tercela bila tindakannya dilandasi oleh suatu penafsiran.
11. Meninggalkan shalat jamaah merupakan perbuatan orang-orang munafik.
[1] Maksudnya, laki-laki tersebut shalat sendirian sementara shalat berjamaah sedang berlangsung pada tempat yang sama- penerj.
[2] Yakni Nabi SAW akan mengimami setiap kelompok dari para sahabatnya- penerj.
[3] Perkara ini tidak dapat dipahami tanpa batasan tertentu, bahkan sesungguhnya diperbolehkannya hal itu apabila mendapat justifikasi syar’i; seperti seseorang yang shalat di suatu jamaah kemudian ia hadir pada jamaah yang lain, maka ia disyariatkan melakukan shalat kembali karena adanya perintah mengenai hal itu seperti yang terdapat dalam hadits hadits shahih. Demikian pula halnya dengan seorang imam rawatib (tetap) bagi jamaah kedua, sebagaimana pada kisah Mu’adz.
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 663-664 – Kitab Adzan - 30/08/2020
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 662 – Kitab Adzan - 30/08/2020
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 661 – Kitab Adzan - 30/08/2020