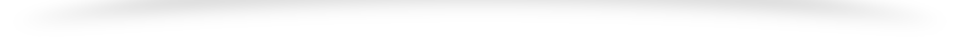Pecihitam.org – Sufisme merupakan bagian penting, jika tidak dapat disebut sebagai inti dari keseluruhan ajaran Islam. Spiritualitas yang terkandung dalam ajaran sufisme merupakan ekspresi paling tinggi dari kehidupan religius.
Hal ini karena manusia, melalui ritual sufistik, dapat menghadirkan diri dalam relung jiwanya bersama Realitas Absolut, sumber dan tujuan hakiki kehidupan. Pengalaman mistik ini, perlahan-lahan dapat menyingkap rahasia identitas kemanusiaannya, bahwa dirinya hanyalah entitas lemah dan kecil di hadapan-Nya.
Sufi artinya suci, yakni manusia-manusia yang selalu menyucikan diri dengan latihan-latihan kejiwaan atau batin. Sufi berasal dari kata Shafa atau Shafwun yang berarti bening. Hati seorang sufi selalu bening, karena ada kejernihan batin.
Para ahli sufi sebenarnya sejajar dengan istilah nimpuna dalam mistik kejawen. Yakni manusia-manusia yang memiliki hikmah dalam hidupnya. Manusia-manusia yang melakukan ajaran sufi tersebut berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan (Suwardi Endraswara, 2014).
Secara historis, kemunculan sufisme dipastikan terjadi pada abad ke-2 H / ke-8 M, dan secara beransur-ansur telah berkembang menjadi kelompok sufi yang beragam di sepanjang daerah-daerah Islam. Tidak seperti golongan lain, golongan sufi cenderung lebih bersikap akomonatif dan inklusif.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh R K. Khuri (1996) dalam Freedom, Modernity and Islam: Towards Creative Synthesis sebagai berikut: “Sebab kaum sufi hanya memperhatikan pada watak yang ada dalam hati manusia yang terdalam, dan mereka tidak peduli akan tuntutan orang-orang bahwa muslim yang sejati, di manapun, harus memperlihatkan bentuk (identitas) luaran yang sama. Mereka amat toleran terhadap perbedaan-perbedaan lokal, bahkan termasuk perbedaan antara Kristen dan Islam sekalipun”.
Umat Islam yang lain ingin membedakan identitas mereka dari umat non muslim untuk menunjukkan superioritas mereka dalam hal otentisitas dan kebenaran dari apa yang mereka anut. Sementara kaum sufi cenderung lebih mengakomodasi perbedaan dan mengambil unsur-unsur dari tradisi agama lain.
Sikap ini, dengan pengaruh populer dan pandangan esoterik mereka dalam masalah-masalah agama, menjadikan mereka terus-menerus menjadi target bagi para sarjana non sufi. Hasilnya seringkali berujung pada penyiksaan dan bahkan eksekusi terhadap beberapa tokoh sufi.
Dalam ketidakstabilan teologi seperti ini unsur-unsur intoleransi antara sesama umat Islam berkembang dan tumbuh. Sunni dan Syiah saling melempar tuduhan sebagai ekstremis dan bahkan sebagai bid’ah, sementara penganut sufi dicap oleh lawan-lawan mereka sebagai ajaran yang menyimpang.
Tuduh-menuduh bid’ah, murtad, dan bahkan kafir terus berlanjut hingga zaman modern sekarang dengan kedok yang beragam dan dengan intensitas yang bervariasi.
Terlepas dari pro-kontra tersebut, di sini akan sedikit diuraikan karakteristik sufi sebagai salah satu khazanah pemikiran Islam yang cukup populer dalam kesejarahan Islam.
Sufisme dicirikan sebagai pengalaman dalam merasakan kehadiran Tuhan di dalam seorang salik, dan juga keinginan untuk pengetahuan langsung dari-Nya.
Pengetahuan transenden tersebut dapat dicapai melalui pengalaman subjektif-intuitif melalui penyerahan diri dan pemurnian jiwa terus-menerus di hadapan-Nya. Dalam masa perjalanan tersebut, seorang salik menyibukkan dirinya dengan keterikatan khusus untuk mengingat Allah dan hidup asketik.
Pada akhir perjalanan spiritual, seorang salik akan mendapatkan pengetahuan langsung, kebenaran-kebenaran rohani dan pada tahap tertinggi merasakan kehadiran Tuhan dalam kesadaran manusiawi.
Sufisme sebagai pandangan hidup memiliki semangat revolusi spiritual yang besar dalam Islam. Hal ini karena sufisme mampu tampil sebagai pengisi ruang batin masyarakat muslim di tengah formalitas Islam ortodoks yang kaku.
Berbeda dari syariah yang melihat manusia dari sisi eksoterik, sufisme lebih menitikberatkan perhatiannya pada pembentukan jiwa manusia melalui serangkaian latihan-latihan spiritual. Dengan mendidik dan memperdalam kesadaran spiritual umat Islam, sufisme telah memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat muslim.
Meskipun terma sufisme baru dikenal pada abad ke-2 H, akan tetapi hal ini tidak menafikkan bahwa praktik sufisme telah diketahui oleh masyarakat muslim generasi pertama.
Masyarakat muslim periode awal mendapatkan ajuran hidup zuhud di dunia dan mengutamakan kehidupan akhirat dari ayat-ayat al-Qur’an dan contoh kehidupan Nabi Muhammad. Dari perilaku, etika, moral, dan pandangan hidup sebagian besar umat Islam generasi awal dapat dikatakan bahwa meskipun penyematan nama “sufi” datang belakangan, namun secara de facto laku sufi sudah dipraktikkan oleh umat Islam sejak awal mula kemunculannya (Ali Sami’ an-Nashar, 1977).
Sufisme merupakan kemampuan intuitif, emosional, dan spiritual, yang menurut kaum sufi kemampuan-kemampuan tersebut akan mengendap jika tidak diaktualisasikan melalui latihan yang benar secara teratur. Dengan demikian, satu definisi sufisme adalah suatu tren dalam agama Islam yang tujuannya membentuk kemunikasi langsung antara Allah dan manusia.
Latihan dalam dunia sufi dikenal dengan ‘menapaki jalan’ atau tarekat yang tujuannya adalah untuk menyingkapkan tabir yang menutupi hakikat diri dari yang Sejati, dan sehingga akan menjelma atau masuk ke dalam Kesatuan yang tak terpisahkan.
Latihan sufistik ini, sebagai bentuk reaksi atas rasionalisasi Islam dalam bidang hukum dan teologi, lebih berorientasi pada kebebasan spiritual, yakni memberikan kebebasan pada kemampuan spiritual dan intuisi kita yang hakiki untuk mengaktualisasikan diri secara leluasa.
Dasar dari ajaran sufisme dalam Islam adalah rasa takut terhadap penghakiman Tuhan, sehingga menghasilkan kesadaran yang mendalam atas dosa dan kelemahan manusia, dan maka dari itu, yang bisa dilakukan hanyalah kepasrahan penuh kepada Kehendak Allah. Abad pertama Islam merupakan abad yang baik bagi penyebaran sufisme sebagai akibat dari ketidakpuasan atas materialisme dan praktik politik dan agama.
Pada paruh kedua abad 1 H, pergerakan sufisme masih ‘ortodoks’ dan pemimpinnya adalah orang-orang yang “dianggap paling saleh”. Gerakan asketik pada awal abad kedua Islam, dengan semangat penolakan terhadap materialisme dan hasrat keduniawian lainnya, secara beransur-ansur menyatu dengan kecenderungan ke arah sufisme secara matang, sehingga berkembanglah apa yang biasa dikenal dengan tasawuf dalam bentuknya yang paling klasik (Margaret Smith, 1973).
Asketisme sufi berkembang melalui semacam “keutamaan”, yakni upaya untuk mengukur ibadah dan ritual melampaui apa yang disyaratkan dalam hukum agama, dan penolakan atas anggapan batal atau sahnya suatu hal.
Contoh dari ritual dan kepercayaan asketik sufi misalnya; memakai jubbah tambalan, makan hanya yang halal, puasa sunnah dengan berpendangan bahwa puasa sebenarnya adalah mengosongkan diri dari nafsu, dan menghabiskan banyak waktunya untuk shalat dan membaca al-Qur’an sebagai bentuk ekspresi kedekatan dengan Allah, serta ibadah yang lain seperti dzikir, atau mengingat Allah.
Di antara gagasan sufi yang paling penting adalah penolakannya terhadap dunia, yang berarti peninggalkan kenikmatan-kenikmatan hidup yang serba sementara, dan bahkan meninggalkan hasrat untuk hidup bahagia selama-lamanya. Rabi’ah al-Adawiyah (w. 185 H) merupakan sufi pertama yang memberikan penekanan pada gagasan tentang cinta yang tidak egois kepada Allah.
Menurut Imam al-Qusyairi (w. 465 H), sufi yang sesungguhnya adalah yang tidak tertarik pada dunia dan sejenisnya. Sufi yang sesungguhnya harus mau mengorbankan semua barang material yang dimilikinya untuk berlatih hidup sabar dan berserah diri kepada kehendak Allah, serta lapang dada dalam mengadapi segala kesusahan di dunia ini agar lebih dekat dengan Allah di akhirat kelak.
Sufisme merupakan spiritualitas yang sangat kompleks. Dalam hal ini ada sisi moral, emosi, kognisi, da nada spekulasi. Awal mula gerakan sufi merupakan gerakan moral sebagai sebuah metode untuk menyempurnakan diri. Gerakan tersebut untuk merealisasikan nilai-nilai keagamaan Islam secara penuh.
Namun perkembangan selanjutnya gerakan sufi banyak ragam tambahan-tambahan menjadi gerakan eskatik. Perkembangan yang demikian pada masa imam Ghazali dibatasi dengan pemahaman sufi yang berlebihan. Namun setelah beliau meninggal, gerakan tersebut mulai mengendor sehingga sufisme berkembang menjadi hipnotisme secara masal dalam bentuk kelompok sufi yang populer dikenal dengan tarekat-tarekat (Fazlur Rahman, 1997).
Tujuan utama dari seluruh latihan sufistik adalah pengalaman spiritual yang bersifat langsung, kesadaran mistik berupa penyatuan dengan Tuhan. Bagi sufi, tujuan ini hanya bisa dicapai dengan cara setia mengikuti ajaran sufi, dengan tahapan-tahapan yang beragam, yang akan membuat jiwanya menjadi semakin bersih sehingga mampu mencapai kualitas-kualitas tertentu dan naik dari satu tahap ke tahap yang lebih tinggi hingga akhirnya, dengan seizing dan pertolongan Tuhan, menemukan tempat kembalinya di dalam Tuhan.
Mungkin penjelasan sistematis pertama tentang sufisme sebagai sebuah jalan hidup dan pemikiran ada dalam Kitab al-Luma’ karya Abu Nasr al-Sarraj (w. 378 H), seorang ahli sufi dari kota Tus di daerah Khurasan, Iran. Sarraj membicarakan tujuh tahapan pencapain spiritual dari tarekat sufi, yakni taubat, wara’, zuhud, sederhana, sabar, iman, dan tawakal.
Selanjutnya, Sarraj menyebutkan ada sepuluh kondisi jiwa sebagai anugerah dari Allah; ketenangan, dekat dengan Allah, rasa cinta, takut, harapan, rindu, kerukunan, kedamaian, kontemplasi, dan kepastian.
Sarraj menyatakan bahwa siapapun bisa ikut dalam tarekat sufi dan perpartisipasi dalam tradisi mistis ini, akan tetapi ia juga mencatat bahwa ada seperangkat standar yang tegas yang berlaku bagi siapa saja yang ingin terjun dalam bidang latihan disiplin diri, kesadaran diri, pemahaman intuitif dan mistik, dan kepekaan emosional serta rasa ini.
Menurut al-Junaid (w. 298 H), tahap taubat yang pertama bukan hanya sebatas pengakuan dosa-dosa yang masih diingat, tetapi juga dosa-dosa yang terlupakan. Tahap awal dari jalan sufi mencakup sikap sabar dan syukur, rasa takut dan harapan. Rasa takut dan harapan tersebut seperti kedua sayap burung ketika sedang terbang, jika salah satunya patah, maka ia akan jatuh, jika keduanya patah maka ia akan mati.
Jadi para sufi adalah para salik pencari Tuhan. Menurut mereka jalan menuju Tuhan itu banyak sekali, sebanyak bilangan bintang-bintang di langit, atau sebanyak napas manusia.
Namun yang menjadi soal, akan terbang ke mana para sufi itu dalam menemukan Tuhan? Apakah ke langit atau ke bulan? Tidak, akan tetapi Tuhan bisa dicari dan diketemukan dalam diri manusia masing-masing, yaitu dengan jalan bercermin atau mengaca diri mereka sendiri.
Meski begitu, harus diingat pula bahwa pengalaman kasyaf dan fana’ dalam sufisme tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai cita ideal hanya bisa dicapai melalui tarekat, yang terdiri dari penyucian diri dengan meniti maqam-maqam, meditasi dengan perantara zikir dan berbagai macam aurad lain, serta melewati berbagai ihwal.
Intinya, sufisme adalah satu kesatuan yang utuh dengan inti ajarannya pada pengalaman kasyaf. Bagi para sufi, pengalaman kasyaf ini merupakan dalil yang paling meyakinkan, lantern apa yang mereka namakan dengan hakikat dan makrifat merupakan puncak pengalaman kasyaf. Tanpa ini, niscaya sufisme hanyalah semacam bongkahan kosong tanpa makna.
- Perbedaan Syariat dan Fiqih dalam Terminologi Hukum Islam - 14/12/2019
- Perbedaan Wacana Sufisme di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah - 13/12/2019
- Disiplin Sufisme dalam Sejarah Pemikiran Islam - 10/12/2019